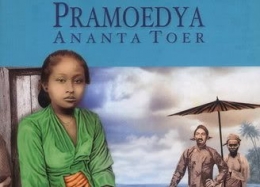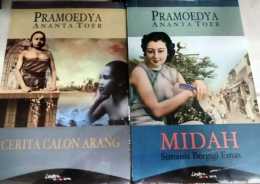Di titik inilah, saya melihat Gadis Pantai sebagai sebuah realitas sosial yang mampu direkam oleh Pram —sebagai sastrawan, dengan daya cipta dan kreatifnya— dan kemudian menyoroti bagaimana berbagai konflik yang terjadi di dalam cerita itu, antara peradaban laut, yang mewakili asal usul Gadis Pantai, dengan peradaban —di salah satu wawancaranya Pram menyebutnya— Jawaisme, antara Gadis pantai dengan Bendoro, antara orang kebanyakan dengan priyayi. Berbagai konflik itu akan dilihat secara didaktis. Artinya, saya melihat, konflik tak selamanya harus bersitegang, berbenturan, tetapi dengan cara diam-diam pun itu adalah sebuah konflik, perlawanan diam-diam.
Melalui Gadis Pantai, kita mengerti bagaimana representasi perempuan dalam benak Pram. Pun kita tahu, sebagaimana diungkapkan Pram sendiri, bahwa tokoh Gadis Pantai ialah ingatan dan kenangan akan neneknya yang dikaguminya, neneknya yang dipaksa keluar dari lingkungan rumah tangganya oleh suaminya sendiri, kakek Pram. Melalui Gadis Pantai, Pram mengkritik tata-sosial masyarakat Jawa yang feodalistik, sebuah tata-sosial yang tak pernah peduli dan selalu menindas perempuan dari segala sisi. Saya rasa, selain mengkritik Jawaisme, Pram juga memberi sebuah pemahaman yang menarik kepada kita, yakni perihal ketertindasan perempuan sejak dalam keluarga, padahal di keluarga peluh dan tenaga perempuan terserap banyak, ketimbang lelaki.
Sekali lagi, melalui Gadis Pantai kita mengerti, bahwa perempuan di mata Pram adalah sosok yang memiliki peranan yang besar dalam laju-kebudayaan. Pram paham betul, kiranya, peranan perempuan dalam tata-sosial semakin termarjinalkan oleh karena pranata sosial, politik dan ekonomi tak menghendakinya. Sedekat yang saya tahu, Pram tak menyebut hal-ihwal itu sebagai partriakhi, Pram tak menggunakan terminologi feminisme untuk menjelaskan ketertindasan perempuan, dus Pram pun tidak menggunakan patologi ideologi feminisme untuk menunjukkan perempuan melawan ketertindasannya.
Saya kira, itulah jawaban mengapa Pram juga tak banyak berbicara perihal kontradiksi gender. Tapi saya rasa, Pram menyadari ada 'proyek besar' sehingga tata-sosial yang menjerat perempuan sedemikian rupa. Dengan Gadis Pantai, Pram melihat mekanisme ‘proyek besar’ itu kerap melalui pranata sosial, misalnya keluarga. Oleh karena itu, di dalam Gadis Pantai, Pram begitu piawai mengolah gejolak dan kontradiksi di pranatasosial yang bernama keluarga itu. Misalnya, saat Gadis Pantai harus mematuhi kehendak bapaknya yang mengawinkannya kepada sebilah keris, yang menyimbolkan bendoronya.
“Kau mau diam, tidak?” hardik bapaknya, saat Gadis Pantai merengek-rengek minta pulang dan tidak mau dinikahkan. (lihat. hlm. 3-4).
Adegan itu menggambarkan kepada kita, bahwa pernikahan (sebuah pra-syarat untuk menuju lembaga sosial yang bernama keluarga) adalah sebuah petaka bagi perempuan seperti Gadis Pantai. Entah mengapa adegan itu mengingatkan saya pada sebuah cerita yang diulang-ulang ibu saya tentang perjuangan nenek saya memperjuangkan dan mempertahankan rumah tangganya, nenek saya adalah tiang kokoh penyanggah asal usul saya.
Pun begitu, menurut saya, Gadis Pantai adalah epos besar perihal keluarga yang kerap merenggut perempuan. Di sana —di Gadis Pantai— kita menyaksikan bagaimana keluarga selalu ‘meminta tumbal’, perempuan (entah anak perempuan ataupun istri). Gadis Pantai itu sendiri yang harus keluar dari keluarganya di kampung nelayan. Atau, perempuan-perempuan yang dijadikan 'istri-istri' bendoro lainnya. Di titik ini kita tahu, bahwa pandangan masyarakat tentang perempuan selalu berada di bawah telapak kaki lelaki (suami).

Jawaban Pram saya rasa sangat lugas. Baginya, ketertindasan perempuan bermula dari Jawaisme itu sendiri. Tapi perlu saya tambahkan, kiranya. Yakni perihal kontruksi wacana yang mendikotomikan antara perempuan dan lelaki sebagai relasi kekuasaan. Maksudnya, dalam Gadis Pantai (dan saya rasa beberapa tokoh-tokoh perempuan dalam karya Pram lainnya) perbedaan antara perempuan dan lelaki tidak hanya dipandang berbeda secara psiko-biologis, melainkan secara ekonomi-politik. Kontruksi wacana inilah yang kerapkali merenggut perempuan. Dan Pram betul, melalui hal-kultural itulah kontruksi wacana itu kerapkali berdampak massif.
Tengoklah upaya Orde Baru Soeharto melakukan de-ideologisasi peranan perempuan di ranah publik. Melalui politik-kultural yang bias gender dan seksualitas Orde Baru mampu menjinakkan perempuan. Dan hal itu berdampak hingga hari ini. Saya rasa, hal itu juga tak luput dari Pram. Dengan demikianlah, kita bisa membaca tokoh-tokoh perempuan dalam karya-karya Pramoedya —tokoh Midah dalam Midah Si Gigi Emas,tokoh Larasati dalam Larasati, tokoh Sri dalam Dia yang Menyerah, tokoh Dedes dalam Arok Dedes, hingga Ontosoroh dalam Bumi Manusia— adalah upaya Pram untuk rubuh-bangunkan sosok perempuan yang dibentuk oleh kekuasaan (baca: Orde Baru Soeharto). Artinya, Pram menyadari betul, bahwa di setiap kekuasaan selalu ada potensi untuk menjinakkan perempuan dengan berbagai cara dan karakter yang berbeda.
Karena dalam pemahaman Pram, perempuan adalah bagian integral (dengan lelaki) dalam upaya memperjuangkan perubahan. Dalam konteks GERWANI di fase Revolusi Indonesia, misalnya, bagaimana GERWANI turut serta dengan kaum lelaki untuk mengupayakan tujuan ‘Revolusi yang belum selesai’. Dengan pemahaman seperti itu kita bisa megerti, mengapa anggota GERWANI tidak mesti gundul atau berbikini ria untuk disebut sebagai ‘aktivis perempuan’, bahkan saya rasa, apa yang dilakukan anggota GERWANI bukanlah mengejar label ‘aktivis-perempuan’ atau bukan. Sebab, dalam catatan sejarah Indonesia, gerakan perempuan adalah berhimpun dengan gerakan massa rakyat dalam upaya Revolusi Indonesia. Sampai di sini, kita bisa memahami bahwa terminologi dan patologi ‘feminisme’ muncul jauh ketika Orde Baru Soeharto sudah kembang-kempis di kebanalan-kekuasaannya, kira-kira di akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an.
Saya rasa, kekeliruan (bukan kesalahan) kaum perempuan yang melabeli dirinya sebagai ‘aktivis-perempuan’ atau ‘feminis’ adalah gagal-paham dalam melihat konteks historis yang melingkupi bagaimana akhirnya (yang kemudian disebut) gerakan perempuan di masa Revolusi Indonesia (baca GERWANI, dkk, dll, dsb) itu muncul. Karena jika kita telisik terminologi dan patologi ‘feminisme’ di tahun 1990-an adalah respon terhadap situasi perempuan yang tersubordinat dalam Orde Baru Soeharto. Artinya ada sebuah kondisi yang membuat teori-teori dan pendekatan feminisme digunakan dalam melihat ketertindasan perempuan tanpa melihat dan memperhatikan konteks historis yang memunculkan ketertindasan itu.