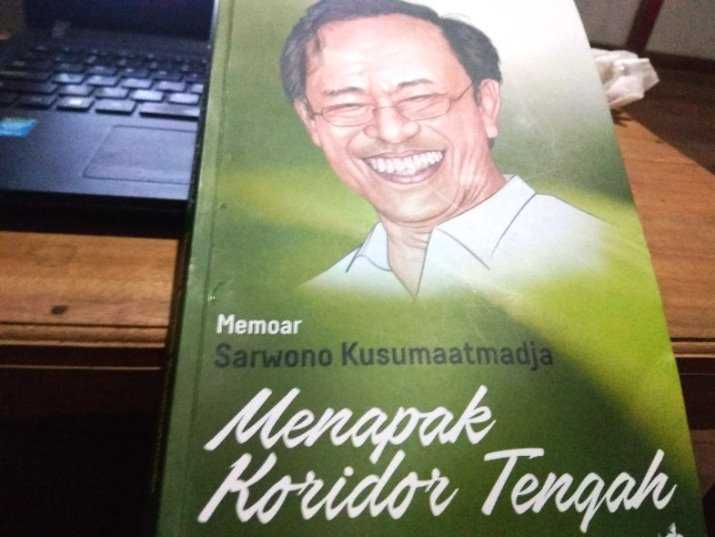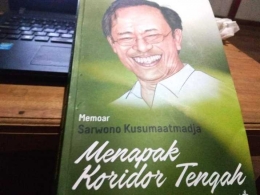"Sarwono itu kader. Dia mengerti strategi. Jalan pikirannya seperti tentara. Dan dia bagus menangani krisis," demikian Moerdiono menirukan kata-kata Pak Harto ( hal 189)
17 Mei 1997. Di layar kaca SCTV, Ira Koesno terlihat "ngotot" memastikan bahwa opsi reshuffle kabinet dan seruan reformasi yang berangsur-angsur (gradual) adalah solusi yang akan membawa Indonesia keluar dari krisis.
Namun Pak Sarwono yang menjadi narasumber pagi itu tetap teguh berpendapat jika tindakan politik tidak lagi berguna. Situasi krisis (baca: kegagalan sistem politik dan ekonomi mengelola masalah dan risiko) yang menyertai senjakala negara Orde Baru saat itu sudah tiba pada dimensi moral. Ibarat gigi yang sudah sakit, maka ia harus dicabut agar tumbuh gigi baru. Bukan dengan menambal yang justru akan melahirkan masalah yang lebih kompleks.
Pak Sarwono mungkin adalah sedikit orang yang berani menganjurkan perubahan menyeluruh atas rezim Orde Baru secara terbuka. Apa yang disampaikan lewat analogi gigi sakit yang harus dicabut, dalam bahasa politik ini adalah delegitimasi serius.
Pasalnya, tema yang bertahun-tahun lama menjadi "barang haram" dalam diskursus politik Orde Baru adalah mengenai suksesi kepemimpinan nasional. Wakil presiden boleh berganti-ganti, Soeharto jangan! Ditambah lagi, Pak Sarwono sendiri pernah menjadi bagian yang sangat dekat dengan istana. Yakni saat menjadi Sekretaris Jendral Golongan Karya mendampingi Sudharmono, SH lantas diangkat sebagai menteri.
Apakah analogi mencabut gigi yang sakit itu muncul karena atmosfir yang menaungi langit kekuasaan Orde Baru telah berwarna senja? Dan karena itu juga, pernyataan seperti ini "tidak terlalu signifikan" dalam mendorong massifnya protes-protes ekstra-parlementarian? Dengan kata lain, dengan tidak menyebut krisis moral pun, kejatuhan Soeharto adalah sebuah keniscayaan historis?
Saya tidak punya jawaban tentang ini. Saya hanya memiliki sedikit cerita dari hasil bacaan yang barangkali dapat membantu memahami mengapa pernyataan seperti itu bisa muncul. Sebuah bacaan biografis. Karena itu, memamahi konteks yang saya maksud bukanlah pada "rasionalisasi politik saat itu" namun berakar pada narasi sejarah yang lebih luas dari hidup seorang tokoh.
Yang saya maksudkan adalah bacaan atas buku berjudul "Menapak Koridor Tengah" (MKT). MKT merupakan memoar yang ditulis Pak Sarwono sendiri, yang berkisah dari masa kecilnya, pergulatan aktivisme politik kampus, hingga mencapai posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1988-1993). Dan sudah diluncurkan pada HUT-nya yang ke-75 di Jakarta Selatan pada Sabtu 28 Juli 2018.
Buku ini terbagi dalam empat bab dan merupakan seri pertama. Memang dalam bagian pertama ini, kita belum menemukan jawaban dari pertanyaan di atas. Namun kita diberikan "peta jalan" untuk melihat bagaimana sang tokoh merintis sejarah dirinya hingga masuk ke dalam lingkaran elit politik nasional.
Empat Parameter bagi Kisah Biografis
Bagi saya, dalam mempelajari sejarah hidup seorang tokoh politik, setidaknya ada empat pertanyaan yang sekaligus menjadi standar mengapa sebuah biografis harus diselesaikan atau hanya sampai pada halaman pengantar saja. Keempat pertanyaan tersebut juga dapat dipilah dari dua tahapan besar, yakni "Society in Man" dan "Man in Society".
Secara spesifik, keempat hal tersebut adalah, Pertama, dari latar belakang keluarga seperti apa sang tokoh dilahirkan, dalam perjumpaan nilai-nilai seperti apa hingga masa remaja? Apa momen-moment kunci dalam perjalanan sang tokoh yang sangat mendasar dalam pembentukan dirinya?
Pada MKT, kita akan membaca bahwa ibu dan ayahnya memiliki penguasaan bahasa Belanda yang baik. Selain itu, ibunda yang biasa dipanggil Mimi, adalah seorang yang aktif dalam kegiatan sosial, mengurus panti asuhan, mengajar di sekolah dasar dan berpartisipasi dalam pemberantasan buta huruf (hal 12).
Sedangkan sang ayah, tergolong sosok dengan kepribadian yang kuat dan "semau gua". Seperti Mimi yang memiliki jiwa sosial begitu kuat, sang ayah juga. Bedanya, sang ayah terbiasa melakukan aktivisme sosialnya lewat layanan kesehatan seorang diri. Ayahnya juga orang yang tidak memiliki prasangka rasial, agama dan sosial.
Selain nilai diri yang hidup lewat ibu dan ayahnya, salah satu yang turut penting adalah lingkungan keluarga yang terbiasa menerima bermacam-macam jenis tamu. Saat itu, kata Pak Sarwono, konflik dengan para penjajah sudah selesai. Republik masih berusia muda dan ketegangan baru muncul dari kebijakan-kebijakannya. Tidak bisa tidak, para tamu yang berkumpul pada malam hari sering membahas politik sambal makan, minum kopi dan merokok (hal 20).
Pak Sarwono adalah salah satu penyimaknya. Selain mendengar percakapan, juga dengan membaca surat kabar. Sebab itu, boleh dikata Sarwono kecil telah mengakrabkan diri dengan diskusi-diskusi politik yang tumbuh bersama pelajaran tentang kepedulian sosial dan kesungguhan dalam mengabdikan diri pada kerja-kerja kemanusiaan sebagaimana dimiliki ayah dan ibunya.
Kedua, apa atau bagaimana struktur motivasi atau preferensi sang tokoh, yang menjadi spirit dalam perjalanan hidupnya, baik dalam masa pasang atau surut, termasuk momen yang membuatnya berada dalam titik nadir sejarah dibentuk? Dalam konteks pak Sarwono, kita bicara soal kehidupan pra-aktivisme politik yang membentuk karakter sang tokoh.
Peristiwa penting lain yang perlu dicatat dalam periode remaja sebelum kuliah adalah sesudah ayahnya wafat, kehidupan keluarga sempat berkubang pada "gali lubang, tutup lubang". Saat itu, mereka sering sekali bolak-balik pegadaian dalam melewati masa-masa sulit.
Beruntung, ada seorang kerabat yang juga pejabat di Kementrian Luar Negeri yang sering ikut membantu. Pejabat itu bernama Soedarsono, ayah dari Juwono Soedarsono. Oom Soedarsono inilah yang meminta ijin untuk mengajak Sarwono muda ke luar negeri dan bersekolah di sana.
Pak Sarwono disekolahkan di King's School, di Gloucestershire, Inggris. King's School adalah sekolah dengan mata pelajaran humaniora sebagai favoritnya. Di sini, Pak Sarwono tampil sebagai anak muda yang berprestasi. Dirinya mampu melampaui hambatan-hambatan "psiko-kultural" yang rentan jatuh pada inferioritas di depan anak-anak asli Inggris.
Sarwono remaja sukses menembus barisan elit siswa, bahkan menjadi satu-satunya siswa yang meramalkan Charles de Gaulle akan menjadi presiden Perancis, di tahun 1958 (hal 41).
Dua penjelasan atas pertanyaan ini bisa kita anggap mewakili fase "Society in Man". Berikutnya, kita akan masuk pada fase "Man in Society".
***
Selanjutnya, Ketiga, jejaring politik atau lingkungan pergaulan seperti apa yang memungkinkan sang tokoh berhasil naik lantas masuk ke dalam lingkaran pengambil keputusan penting dari sebuah orde politik. Dalam konteks ini, kita akan melihat bagaimana masa-masa aktivisme di kampus yang juga merupakan jejak awal dari jalan politik yang kelak membawanya ke level "inti elit" nasional.
Selain kuliah di ITB di jurusan Teknik Sipil, Sarwono muda juga aktif pada Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB), organisasi mahasiswa lokal. PMB, berdiri 1948, adalah organisasi yang anggotanya berasal dari kampus papan atas, selain ITB, juga ada Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Katholik Parahyangan (Unpar).
Saat itu, katanya, suhu politik di kampus sedang hangat. Terpolarisasi antara yang pro-komunis dan yang antikomunis. PMB sendiri mengkader anggotnya dalam semangat anti-komunis. Pertanyaannya, bagaimana kaderisasi dilakukan dalam masa itu?
Ada keterangan yang penting terkait ini. Saya kutipkan agak panjang,
..di PMB, para mahasiswa senior mencari mahasiswa pemula yang berpotensi menjadi andalan. Itu dilakukan dengan melalui wawancara dan penugasan dengan cara-cara aneh guna memancing sikap-sikap dasar dan kreativitas. Misalnya saya disuruh mencari dua ekor kutu busuk yang perintahnya diberikan pada tengah malam dan kedua makhluk itu harus dihadirkan waktu apel pagi pukul 05.00. keesokan harinya saya ditanya mana di antara kutu busuk itu yang jantan dan mana yang betina. (hal 72)
Sesudah membaca kesaksian ini, saya terus ingat pada sebuah pertemuan di tahun 2000an awal, di Jakarta. Saat itu, kami dari beberapa daerah kumpul-kumpul untuk mendiskusikan rancangan kaderisasi yang lebih up to date-niatnya begitu sih.
Dalam kumpul-kumpul ini, seorang narasumber juga menceritakan model rekrutmen yang dilakukan melalui wawancara dan penugasan bertingkat.
Pada titik tertentu, ketika situasi genting-bayangkan saja dalam suasana sedang mendorong perubahan-maka sistem yang seperti ini akan bermutasi menjadi unit bertahan yang saling menutup diri dan menjaga rahasia, khususnya dalam mengamankan posisi kepemimpinan tertinggi organisasi.
Narasumber itu bernama Soeripto. Ternyata nama ini saya temukan dalam buku Menapak Koridor Tengah sebagai sosok yang sama ngetopnya dengan Rahman Tolleng di dunia aktivisme mahasiswa saat itu. Pendapat keduanya sering dikutip kala itu.
Selain cerita cara rekrutmen, satu yang penting dari hari-hari di ITB adalah saat itu, pertentangan ideologi begitu kencang di dalam kampus. Pertentangan ini merupakan pantulan dari situasi nasional yang diperparah oleh tiadanya mekanisme suksesi serta kesengsaraan yang makin meluas.
Saat itu, di kalangan aktivis mahasiswa, puncak konflik sedang terbangun. Mereka gelisah dan tegang.
Saya mencatat ketegangan dan kegelisahan itu belum menjalar ke masyarakat. Di kalangan orang biasa, ada anggapan bahwa semuanya merupakan kejadian-kejadian kecil saja. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa kejadian-kejadian sporadis itu adalah bagian dari ledakan besar yang akan terjadi. Ketenangan orang banyak itu seperti keheningan sebelum badai, quiet before the storm. (hal 80).
Kesaksian seperti ini membawa kita melihat konteks dari pembentukan aktivisme yang dilatari oleh benturan ideologi dan rezim politik yang sedang menuju senjakala. Saat itu, kampus begitu riuh dengan polarisasi politik. Sebuah era baru sedang menanti lahir dari benturan keras.
Memang, Pak Sarwono tidak menyebut situasi Perang Dingin yang menjadi bingkai besarnya, namun MKT tetap mengakui adanya aliansi dengan penguasa militer di masa-masa itu dalam konteks "kontra ideologi" terhadap anasir politik komunis. Aliansi yang terus terpelihara hingga masa menjadi politisi penuh waktu.
Keempat, bagaimana sang tokoh bersikap atas situasi politik yang dinamis dan mampu menghadirkan dirinya dalam peran politik yang membuatnya layak disebut sebagai tokoh. Di titik ini, kita akan melihat bagaimana Pak Sarwono tampil sebagai menteri dengan akses langsung kepada presiden Soeharto.
Saat itu tahun 1971 dan menjelang pemilu. Golkar sendiri sedang dalam transisi dari Sekber Golkar yang masih bermitra dengan TNI. Jika konteksnya Bandung atau Jawa Barat secara umum, maka itu merujuk pada Kodam VI/Siliwangi. Saat itu kepengurusan Golkar diambilalih oleh militer. Sebelumnya, relasi mahasiswa dan militer memang sudah terjalin sejak 1966, saat kejatuhan Soekarno.
Pada periode awal berpolitik inilah, ABRI merupakan institusi yang memasukkan mereka ke dalam Golkar, menjadi caleg dan selanjutnya duduk di DPR.
Lantas, apa yang dimaksud dengan "Koridor Tengah"?
Koridor Tengah adalah dua batas yang tidak boleh dilanggar karena akan berdampak pada stabilitas nasional. Yang pertama adalah larangan mengubah UUD'45 dan Pancasila sementara yang kedua adalah suksesi kepemimpinan nasional. Khusus yang terakhir, jika ada upaya yang dianggap serius untuk mengganti presiden, apapun rumusannya dan siapa pun yang melakukannya, langsung diambil tindakan untuk memadamkannya (hal 140).
Dus, kita boleh mengerti jika opsi Koridor Tengah dalam politik bukanlah sikap permanent. Ia dibentuk oleh kondisi politik dan sejauh apa hubungan antar kekuatan-kekuatan yang menopangnya tetap solid. Dalam perkembangan kemudian, Koridor Tengah yang dimaksud adalah sikap untuk tidak masuk ke dalam lingkaran dalam Cendana. Sebuah sikap yang, seperti wawancara di SCTV itu, kemudian menjadi berhadap-hadapan.
Dari buku ini juga, kita bisa melihat bagaimana perjalanan politik yang menciptakan dirinya sebagai politisi sipil yang sukses membangun relasi dengan kelas militer, khususnya dengan LB Moerdani. LB Moerdani atau familiar dikenal Benny Moerdani sendiri adalah orang yang ditugaskan oleh Soeharto untuk mengawasi dirinya sebelum diputuskan sebagai Sekjen Golkar.
***
Saya kira, Menapak Koridor Tengah termasuk yang "lulus sensor" jika ditakar dengan empat parameter sederhana versi saya di atas. Lebih dari itu, saya rasa buku ini tergolong memoar yang penting dipelajari generasi muda, generasi yang tidak mengalami tiga zaman apalgi berada di pusat pusaran politiknya.
Jelas saja ada banyak sekali cerita yang merupakan "real politik" di balik layar dari satu peristiwa politik nasional yang tidak cukup di-cover oleh mass media saat itu yang bisa dilihat di sini. Misalnya saja, salah satunya adalah cerita tentang Soeharto sebagai presiden yang selalu membaca laporan menterinya dan mengajak berdiskusi. Kebiasaan yang hilang menjelang kejatuhannya.
Atau cerita tentang Moerdiono, yang sangat lamban dalam berbicara, sejatinya adalah seorang petinggi negara yang memiliki kehati-hatian yang tinggi sekali. Atau cerita tentang dampak Revolusi Iran yang sempat membuat Gokar diserang. Atau ketegangan di balik pencalonan Soedharmono sebagai wakil presiden ke-5 yang sempat membuat Benny Moerdani kecewa dengan sikap Soeharto.
Intinya, buku ini perlu dibaca untuk melihat sejarah Orde baru dari sisi pelakunya; dari sisi manusia dalam Sejarah. Bahwa kisah yang dituturkan masih harus diperiksa "obyektivitas historisnya", itu sudah di luar koridor artikel ini. Barangkali di waktu yang lain.
Tabik.
***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H