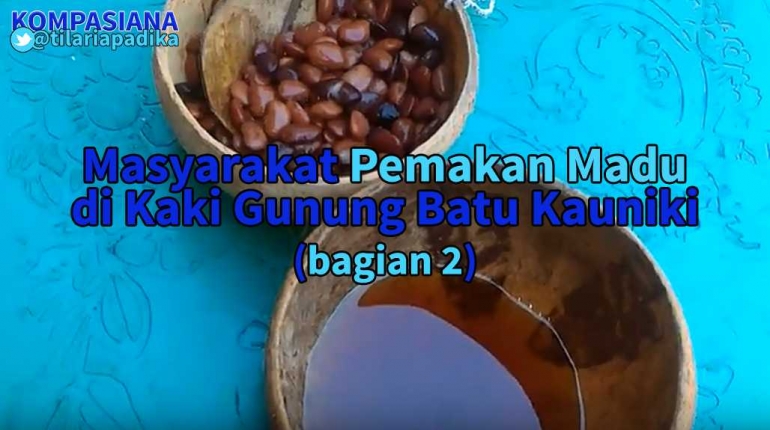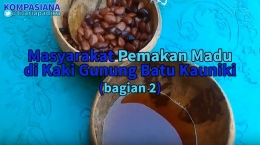Saya tidak pernah menyangka jika di Oh'aem I ini, madu dijadikan seperti sup saja. Heh, kalian seperti hidup di surga. Bahkan bocah-bocah Pandawa dan Kurawa yang berlimpah susu dan mentega akan cemburu kepada kalian," batin saya penuh iri.
Pastikan Om-Tante telah membaca "Bagian 1" artikel ini.
Baru beberapa puluh meter mobil berjalan, kami harus berhenti. Di depan sedang ada pengerjaan jalan. Bau aspal panas menyengat. Drum roller kecil merayap malas, mondar-mandir seperti setrika, meratakan kerikil yang disebar para buruh dari tumpukan muntahan sejumlah truk.
Truk-truk memperhatikan gerak drum roller. Sejumlah truk yang tak sabar menderumkan mesin, seperti mendesak drum roller bergegas. Mungkin juga mereka sedang bergunjing, mensyukuri kenyataan, ternyata mereka bukan kendaraan terlambat di muka bumi seperti cemo'oh banyak mobil kecil lincah yang mereka dijumpai di jalanan kota yang ramai. "Jalan sepanjang 1,5 km dari dana desa," kata seorang warga.
Heuh, bersyukurlah desa-desa ini, mereka sudah bisa mengelola sendiri dananya, memastikan kondisi jalan tidak mengundang umpatan. Jalan raya yang baru saja kami lewati mungkin milik kabupaten atau provinsi, atau pusat. Entahlah. Yang pasti selama 5 tahun beberapa kali saya lalui, tak ada perbaikan.
Tanpa menunggu persetujuan rombongan, saya segera turun, melangkahkan kaki menuju rumah terdekat.
"Haloooo, mama, kantor desa masih jauh?"
"Mungkin 200 meter lagi, Pak," jawab ibu-ibu di rumah itu.
Tante Lesti, admin Perkumpulan Pikul tadi informasikan acara baru akan dimulai jam 16 sore. Ini baru pukul 12. Saya punya kesempatan foto-foto ume bubu---makanya baca "Bagian 1" dulu agar Om-Tante tidak bingung sendiri baca ini-- yang sudah sejak tadi bikin penasaran.
"Mama punya ume bubu di belakang?"
"Pasti ada, Pak."
"Heee, baguslah. Boleh saya lihat-lihat? Mama-mama belum ke kantor desa kah?"
"Kami sedang masak untuk acara di kantor desa nanti."
"Ah, kebetulan sekali." Saya bergegas ke belakang, hendak melihat ume bubu sekaligus menyaksikan bagaimana mama-mama ini mengolah pangan lokal untuk festival nanti. Kekesalan saya karena penundaan penjemputan sehari akan terbayar sudah.
Yang ingin saya tahu adalah bagaimana proses persiapan pangan lokal ini, bukan sekedar wujud jadi mereka saat sudah terhidang rapih di meja-meja festival.
Aiiihh, itu bapak-bapak sedang ramai di belakang, persis di depan ume bubu. Sedang apa mereka?
"Bapak-bapak sedang parut kelapa dan labu untuk masak, Pak," kata ibu-ibu seperti tahu pertanyaan di kepala saya.
"Begitukah? Jadi acara festival ini bikin bapak-bapak terpaksa masuk dapur."
"Tidak, Pak. Di sini sudah biasa, bapak-bapak ikut masak," kata ibu-ibu. Saya tidak percaya. Belum pernah saya lihat yang seperti ini di tempat lain.

"Oiii, hari ini terpaksa masuk dapur kah?"
"Tidak, Pak. Kami di sini begini sudah. Urusan masak itu laki-perempuan ikut semua," kata salah seorang bapak, lelaki muda yang tampak cerdas oleh matanya yang memancarkan semangat.
"Ah, yang benar saja. Berarti bapak boleh masuk ke loteng ume bubu juga?" Saya masih belum bisa percaya.
"Bisa, Pak?"
"Eh, kan ini istana perempuan. Di tempat lain tidak boleh."
Soal ume bubu, baca "Bagian-1" artikel ini.
"Makanya kami kalau ke tempat lain heran, laki-laki tidak ikut masuk dapur," jawab mereka.
"Begitu ya? Saya boleh masuk ke ume bubu, Mama?"
"Bisa, Pak," jawab ibu yang tampaknya pemilik rumah. Ia lantas minta suaminya ambilkan senter dan temani saya ke dalam ume bubu.
Saya tidak ceritakan lebih jauh soal ume bubu di sini. Jadi kita loncati saja ke bagian saya dipersilakan masuk ke ruang makan. Di situ, pada sejumlah baskom, beberapa jenis pangan lokal yang sudah dimasak menunggu dibawa ke kantor desa, tempat festival malam nanti.
Saya sudah kenal bahan pangan di meja itu, meski umumnya masih berupa tetumbuhan dan bahan mentah.
Ada beragam jenis keladi (putih dan ungu), sejumlah Dioscorea (uwi), dan 'pisang tanah'. Tetapi agar mereka senang, saya berpura-pura bertanya dengan nada penasaran yang dibuat-buat. Ini teknik khas saya untuk memancing orang bersemangat menceritakan apa yang dia tahu.
Teknik pasang ekspresi penasaran dan celetukan takjub ini selalu berhasil menggali kisah dan informasi orang-orang. Saya bahkan menggunakannya juga pada anak saya, membuatnya bangga saat menyangka saya baru tahu suatu hal darinya.
"Jadi sekarang kamu tahu, Papa?" tanyanya dengan mata berbinar-binar, tidak berharap jawaban selain ya.
"Iya, Jyestha. Thanks' ya, sekarang Papa tahu. Ternyata begitu ya."
Teknik itu sekali lagi berhasil pada ibu-ibu ini. Mereka bukan saja bercerita tentang cara pengolahan, bagaimana mereka memasaknya, seberapa sering menghidangkannya bagi keluarga, tetapi juga mengambilkan mangkok dan sendok agar saya bisa mencicipi.
Mereka mengambilkan saya semangkuk kacang kratok (Phaseolus lunatus L), yang dalam bahasa lokal disebut koto, sementara dalam Melayu Kupang disebut arbila, dan madagascar bean dalam bahasa Inggris. Bentuknya seperti kacang merah untuk sup brenebon, resep masakan peninggalan Belanda yang sangat diakrabi orang NTT.
Menurut Dr. Wayan Mundita, birokrat Universita Nusa Cendana dan botanis yang kerab merendah dengan menjuluki diri sendiri sebagai 'guru kecil', kratok aslinya berasal dari pengunungan Andes dan Meso-Amerika. Di Pegunungan Andes, kratok telah didomestifikasi sejak 1500 SM. Pak Wayan tidak tahu kapan persisnya kratok masuk ke Timor Barat, tetapi ia menduga bersamaan dengan masuknya jagung dan labu.
Om-om bisa mengetahui berbagai jenis pangan lokal NTT dari buku karya Pak Wayan ini (klik untuk unduh). Saya membantu Pak Wayan memimpin tim pengumpul data untuk Pulau Lembata.
Kratok ada dua jenis. Kratok domestifikasi tidak beracun, kratok liar beracun. Yang dikonsumsi masyarakat Desa Oh'aem I dan saat ini disuguhkan kepada saya adalah kratok liar. Untuk menghilangkan racunnya, kratok harus dimasak berulang kali dan air rebusannya dibuang tiap periode, 1 jam sekali.
"Bagaimana kalau ini masih mengandung racun? Apa dampaknya?"
"Bisa mati, Pak. Sapi saja mati kalau makan yang masih beracun," jawab ibu-ibu bersemangat seperti berharap saya akan keracunan.
Gleg! Jika sapi yang bobot tubuhnya mungkin 3 kali lipat saya saja bisa mati, bagaimana dengan saya? Tetapi baiklah, ibu-ibu ini sudah bertahun-tahun mengolah kratok, tentu mereka menjamin semangkuk kratok liar di tangan saya ini sudah aman disantap.
Yang bikin saya terkesima, ternyata hidangan kratok a la Oh'aem berteman madu. Saya disodori semangkuk madu. Semangkuk, lho Om-Tante! Paduan madu dan kratoknya ini namanya losi.
Simak nih video saya menikmati kratok campur madu.
Lalu, mereka sodori pula wijen tumbuk. Saya coba mencampurkannya dengan kratok dan madu. Wuiiih, lezatnya.
Beberapa jenis pangan lokal lain yang diolah kelompok ini---ada 10 kelompok dari 3 desa yang tampil--dan akan mereka tampilkan dalam festival malam nanti antara lain dua jenis uwi (gadung-gadungan), "pisang tanah," tumbukan wijen, kacang nasi, pisang yang direbus dengan madu---dengan madu, lho, bukan air atau minyak--dan keladi ungu dan putih.
Dugaan saya, uwi (gadung-gadungan) yang dimiliki kelompok ini adalah Dioscorea esculenta dan satu lagi Dioscorea yang belum bisa saya duga jenisnya. Dioscorea esculenta memiliki umbi utama yang berbulu seperti gadung (Dioscorea hispidia) yang beracun itu dan umbi gantung atau umbi udara seperti Dioscorea bulbifera.
Sementara yang mereka sebut pisang tanah sebenarnya ganyong. Nama ilmiahnya banyak: Canna indica L. sin, C. coccine P. Miller, C. edulis Kerr-Gawler, dan C. orientalis Roscoe. Ganyong memang berdaun seperti pisang yang masih kecil. Bagian yang dimakan sebenarnya rimpang. Rasa rimpang ganyong lumayan manis.
Setelah menikmati sejumlah pangan lokal, saya mengikuti mereka ke atas bukit untuk mengambil madu hutan. Ternyata madu yang ada di sana adalah Apis cerana tetapi bersarang di lubang batu.
Madu di Timor ini ada tiga jenis. Yang pertama adalah jenis Apis dorsata. Ukurannya besar, koloninya juga besar, gampang marah dan sengatannya bisa bikin mati. Apis dorsata tidak bisa dibudidayakan.
Jenis kedua adalah Apis cerana. Ukurannya lebih kecil, menyengat tetapi tidak terlampau sakit---tetap bengkak juga sih--dan bisa dibudidayakan dalam kotak persegi. Ada juga klancengan atau madu trigona, tetapi jarang saya lihat dan tidak dibudidayakan di sini.
Lihat nih, video orang Oh'aem I mengumpulkan madu dan anak-anak yang menikmati madu dengan sarang-sarangnya.
Setelah hampir jam 16.00, saya menuju kantor desa. Di sana akan ada 10 kelompok masak dari 3 desa yang memamerkan beragam jenis pangan lokal, lebih banyak, unik, dan menarik.
Eh, di jalan saya bertemu Tante Andi dan kawan-kawannya. Tante Andi---dia pasti cemberut disebut tante---dan kawan-kawannya datang jauh-jauh dari Jakarta.
Mereka orang Oxfam Indonesia yang turut berkontribusi bersama Perkumpulan Pikul Kupang dalam menghidupkan kembali tradisi budidaya dan konsumsi pangan lokal di sejumlah desa di Kabupaten Kupang.
Menurut saya pasangan Oxfam dan Pikul ini lumayan berhasil sebab bisa mendorong sejumlah lembaga dan komunitas untuk turut ambil peran. Saya akan ceritakan pula lembaga-lembaga dan komunitas-komunitas ini nanti saat ceritakan serunya festival pangan.
Harap bersabar, ya Om-Tante. Saya harus menunggu sumbangan foto dari fotografer cilik Ike Nggili, anak suami-istri sahabat saya, Om Frits Nggili dan Tante Silvia Fanggidae.
Pastikan Om-Tante datang lagi nanti, dan jangan lupa share atuh. Sharing is caring, nggak sharing is garing.
Tabik. [@tilariapadika, 17/6/2018]
Baca artikel-artikel Tilaria Padika tentang Nusa Tenggara Timur [klik] dan tentang Pangan [klik]
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H