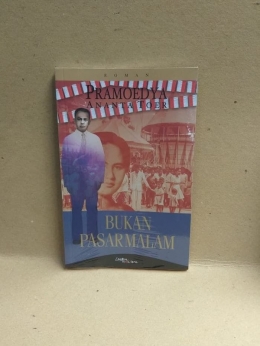Karya sastra adalah hasil dari buah peradaban. Hasil dari masyarakat, tak bisa dilepaskan dari masyarakat, dan selalu membicarakan apa yang ada di masyarakat. Sastra adalah institusi sosial[1].
Begitu pula sastra dapat dipandang sebagai gejala sosial[2]. Sastra adalah cermin lain yang menggambarkan kehidupan dengan dunianya sendiri, dengan caranya sendiri, namun tak pernah benar-benar lepas dari peradaban yang melahirkan karya sastra itu sendiri.
Hubungan sastra dan masyarakat dapat diteliti dengan berbagai cara. Bisa melihatnya melalui faktor-faktor di luar teks sendiri, gejala konteks sastra; teks sastra itu sendiri tidak ditinjau. Selain itu bisa juga melihatnya dari segi hubungan antara (aspek-aspek) teks sastra dan susunan masyarakat.
Salah satu pisau bedah dalam ilmu sastra -- sastra dan masyarakat -- yang paling populer adalah kritik sastra marxis yang terkenal dengan istilah realisme sosialis.
Realisme sosialis adalah suatu pandangan adanya hubungan dialektik antara sastra dan kenyataan. Dari satu pihak kenyataan tercermin dalam sastra sehingga sastra dianggap menyajikan suatu tafsiran yang tepat mengenai hubungan-hubungan di dalam masyarakat, di lain pihak sastra juga mempengaruhi kenyataan sehingga mempunyai tugas mendampingi partai komunis dalam perjuangannya membangun masyarakat yang lebih baik.[3]
Realisme sosialis menuntut pengarang agar melukiskan kenyataan selaras dengan kebenaran dan fakta sejarah. Pendeknya suatu karya yang bergenre realisme sosialis diharuskan dan sengaja dibentuk sesuai dengan kondisi yang benar-benar ada atau kenyataan, sehingga menjadi cerminan kritik atau refleksi bagi suatu masyarakat atau peradaban.
Salah satu karya sastra yang berbau realisme sosialis yang ada di Indonesia -- objek yang dibahas -- adalah roman Bukan PasarMalam karya penulis legendaris Pramoedya Ananta Toer.
Bukan Pasar Malam berisi tentang sebuah cerita perjalanan seorang anak revolusi, seorang mantan gerilyawan yang pernah masuk bui karena dinamika politik Indonesia diawal kemerdekaanya yang belum stabil, pulang kampung karena ayahnya yang sedang sakit.
Dari perjalanan tersebut tergambarf bagaimana gejolak batin yang dialami sang tokoh ketika melihat keadaan sang ayah yang makin rapuh melawan berbagai penyakit. Namun, disamping kondisi ayahnya yang semakin tergolek tanpa kekuatan, sikap nasionalis dan keperwiraan dibangun dengan begitu sederhana yang menyentuh.
Sebagai seorang mantan gerilyawan, guru sekolah rakyat yang jasanya tak pernah diketaui banyak orang, rela mengasingkan diri dari segala kemunafikan, kenaifan jabatan yang pada saat itu diperebutkan oleh banyak orang.
Berbagai dialog serta gambaran yang dibangun Pram seolah berarti kritik sosial yang menampar kondisi masyarakat Indonesia di awal berdirinya republik tentang pembesar-pembesar negeri yang hanya asyik mengurus dan memperkaya diri sendiri.
Kebopengan yang tergambar dalam barisan huruf per huruf dalam roman Bukan Pasar Malam membuka mata pembaca akan bejatnya perilaku pembesar negeri yang terselip dibalik megahnya republik di awal berdiri.
Memang tidak dijelaskan secara jelas, namun dari gembaran yang dicerminkan tokoh ayah sebagai korban dari jalannya sejarah, yang terbaring lusuh karena digerogoti penyakit, di sebuah rumah sakit yang perihal perawatannya bisa dibilang tidak layak, dengan sikap dokter dan perawat yang tidak profesional, meski dia adalah seorang pahlawan mantan gerilyawan yang memperjuangkan kemerdekaan.
Kritik yang dicipta secara halus ini dapat dilihat dari penolakan tawaran menjadi anggota perwakilan daerah, dan membalasnya dengan perkataan yang pedis untuk didengar,
"Perwakilan rakyat? Perwakilan rakyat hanya penggunng sandiwara. Dan aku tidak suka menjadi badut, sekalipun badut besar".
Ditegaskan lagi sikap keperwiraan dan tulusnya nasionalisme yang dilukiskan ketika mendapat tawaran menjadi koordinator pengajaran daerah yang sejatinya mampu menjadi jalan dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya, dia malah menolaknya. Dan lagi-lagi membalasnya dengan halus dan penuh keprihatinan bagi yang membaca.
"Tempatku bukan di kantor, tempatku ada di sekolahan. Kita guru-guru di tanah air kita ini jangan sampai kurang seorang pun juga."
Diperparah lagi dengan sikap balasan warga setempat dengan mengatakan antek Belanda, menyerah pada Belanda, bukan manusia, yang sangat meruntuhkan hati dan jauh dari akar kebenaran.
Inilah wajah suram kondisi masyarakat Indonesia di awal kemerdekaan yang sedikit digambarkan Pramoedya Ananta Toer di romannya Bukan Pasar Malam, penuh curiga, egoisme, mau menang sendiri, mau enak sendiri, omong kosong, nasionalisme nihil, dan kebopengan-kebopengan lain yang ada dan selalu ada sejak republik ini lahir.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H