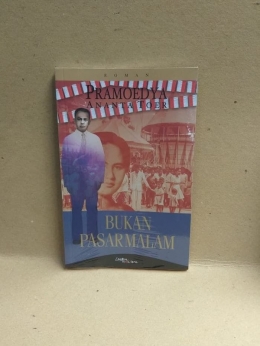Kebopengan yang tergambar dalam barisan huruf per huruf dalam roman Bukan Pasar Malam membuka mata pembaca akan bejatnya perilaku pembesar negeri yang terselip dibalik megahnya republik di awal berdiri.
Memang tidak dijelaskan secara jelas, namun dari gembaran yang dicerminkan tokoh ayah sebagai korban dari jalannya sejarah, yang terbaring lusuh karena digerogoti penyakit, di sebuah rumah sakit yang perihal perawatannya bisa dibilang tidak layak, dengan sikap dokter dan perawat yang tidak profesional, meski dia adalah seorang pahlawan mantan gerilyawan yang memperjuangkan kemerdekaan.
Kritik yang dicipta secara halus ini dapat dilihat dari penolakan tawaran menjadi anggota perwakilan daerah, dan membalasnya dengan perkataan yang pedis untuk didengar,
"Perwakilan rakyat? Perwakilan rakyat hanya penggunng sandiwara. Dan aku tidak suka menjadi badut, sekalipun badut besar".
Ditegaskan lagi sikap keperwiraan dan tulusnya nasionalisme yang dilukiskan ketika mendapat tawaran menjadi koordinator pengajaran daerah yang sejatinya mampu menjadi jalan dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya, dia malah menolaknya. Dan lagi-lagi membalasnya dengan halus dan penuh keprihatinan bagi yang membaca.
"Tempatku bukan di kantor, tempatku ada di sekolahan. Kita guru-guru di tanah air kita ini jangan sampai kurang seorang pun juga."
Diperparah lagi dengan sikap balasan warga setempat dengan mengatakan antek Belanda, menyerah pada Belanda, bukan manusia, yang sangat meruntuhkan hati dan jauh dari akar kebenaran.
Inilah wajah suram kondisi masyarakat Indonesia di awal kemerdekaan yang sedikit digambarkan Pramoedya Ananta Toer di romannya Bukan Pasar Malam, penuh curiga, egoisme, mau menang sendiri, mau enak sendiri, omong kosong, nasionalisme nihil, dan kebopengan-kebopengan lain yang ada dan selalu ada sejak republik ini lahir.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H