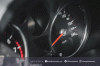Dr.-Ing. Suhendra. Pengalaman sebagai konsultan industri Jerman lebih dari 10 tahun. Saat ini dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
Mobil listrik sering kali digambarkan sebagai jawaban atas krisis lingkungan global. Dengan emisi lokal yang hampir nol saat digunakan, kendaraan ini menawarkan janji masa depan yang lebih hijau. Namun, realitas di balik transisi ini menyimpan tantangan yang tidak dapat diabaikan.
Pengalaman Jerman sebagai salah satu pusat inovasi otomotif dunia memberikan gambaran jelas tentang kesenjangan antara visi ideal dan kenyataan di lapangan.
Beberapa catatan berikut semoga dapat dijadikan patokan untuk konsumen dan pasar Indonesia.
Belajar dari Volkswagen dan Ford
Di pabrik-pabrik besar seperti Volkswagen dan Ford, perubahan skala besar telah dilakukan untuk memenuhi tuntutan zaman. VW, misalnya, mengubah total fasilitasnya di Zwickau menjadi pabrik khusus mobil listrik. Langkah ini dianggap sebagai bukti keberanian industri Jerman dalam menghadapi era baru. Namun, hasilnya justru memperlihatkan sisi gelap dari ambisi besar ini.
Angka produksi yang terus menurun menunjukkan bahwa permintaan pasar belum siap mendukung lonjakan penawaran. Mobil listrik, dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan mobil berbahan bakar fosil, belum mampu menarik konsumen massal. Ford, yang juga beralih ke produksi listrik penuh, kini menghadapi ancaman keberlanjutan operasional.
Permasalahan ini tidak hanya soal angka dan grafik penjualan, tetapi juga menyangkut manusia di balik industri. Teknologi mobil listrik yang lebih sederhana membutuhkan tenaga kerja yang jauh lebih sedikit.
Dampaknya terasa nyata di banyak wilayah, dengan pengurangan tenaga kerja dan ancaman pengangguran yang meluas. Padahal, industri otomotif adalah salah satu tulang punggung ekonomi di negara seperti Jerman. Perubahan ini, meskipun penting, memaksa kita untuk menghadapi realitas sosial yang berat.

Tantangan Infrastruktur
Di luar pabrik, tantangan lain juga mengintai. Infrastruktur pendukung untuk mobil listrik, seperti jaringan stasiun pengisian daya, masih jauh dari memadai. Banyak konsumen ragu untuk beralih karena takut tidak bisa mengisi daya kendaraan mereka dengan mudah, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses listrik yang stabil.
Masalah ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik, di mana transisi teknologi tidak hanya berfokus pada kendaraan itu sendiri, tetapi juga ekosistem di sekitarnya.
Ironisnya, isu lingkungan yang menjadi pilar utama mobil listrik juga menjadi salah satu kelemahan terbesarnya. Proses produksi baterai lithium, yang menjadi inti kendaraan listrik, melibatkan penambangan besar-besaran yang merusak lingkungan.
Wilayah seperti Chili dan Bolivia, yang kaya akan cadangan lithium, menghadapi ancaman pengurasan sumber daya air dan kerusakan ekosistem. Selain itu, proses manufaktur baterai menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar, menyamai emisi mobil berbahan bakar fosil dalam beberapa tahun pertama penggunaannya.
Paradoks ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa sebagian besar listrik yang digunakan untuk mengisi daya mobil listrik dihasilkan dari bahan bakar fosil. Di banyak negara, ketergantungan pada batubara dan gas alam mengurangi dampak positif lingkungan yang seharusnya diberikan oleh kendaraan ini. Lebih jauh lagi, kurangnya infrastruktur untuk mendaur ulang baterai memperbesar masalah limbah beracun yang dapat mencemari tanah dan air jika tidak dikelola dengan baik.
Masalah-masalah ini mengingatkan kita bahwa mobil listrik bukanlah solusi instan. Dalam beberapa kasus, total emisi dari siklus hidup mobil listrik bahkan dapat menyamai, atau melampaui, kendaraan konvensional. Namun, ini bukan alasan untuk menyerah. Sebaliknya, ini adalah seruan untuk berpikir lebih dalam dan bertindak lebih cerdas. Inovasi teknologi harus terus didorong, terutama dalam hal baterai yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan mudah didaur ulang. Infrastruktur energi terbarukan juga harus diperluas agar mobil listrik benar-benar dapat berjalan dengan daya yang bersih.
Pengalaman Jerman adalah pelajaran berharga bagi dunia. Ia mengajarkan bahwa transisi teknologi besar-besaran memerlukan perencanaan matang, dukungan ekosistem yang holistik, dan, yang paling penting, kesabaran.
Mobil listrik mungkin bukan jawaban akhir, tetapi mereka adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih baik. Dengan komitmen kolektif, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang, dan visi transportasi berkelanjutan tidak hanya menjadi mimpi, tetapi kenyataan.
Paradoks Ramah Lingkungan Menjadi Barang Mewah
Mobil listrik, dengan teknologi canggih dan janjinya untuk masa depan yang lebih hijau, tampak seperti jawaban yang sempurna untuk tantangan transportasi modern. Namun, di balik kemilau keberlanjutan, muncul kenyataan pahit bahwa kendaraan ini sering kali menjadi simbol eksklusivitas, jauh dari jangkauan masyarakat umum.
Harga rata-rata sebuah mobil listrik, bahkan untuk model kecil, berkisar sekitar 57.000 Euro (sekitar 950 juta rupiah). Bagi banyak orang, angka ini sulit dibayangkan. Di sejumlah negara, ini setara dengan dua kali lipat gaji tahunan rata-rata seorang pekerja.
Filosofi awal para produsen besar seperti Volkswagen adalah menciptakan kendaraan untuk rakyat -- terjangkau, praktis, dan dapat diakses semua kalangan. Ironisnya, mobil listrik justru membalikkan prinsip ini, menciptakan kesenjangan baru dalam aksesibilitas.
Salah satu alasan utama tingginya harga adalah komponen baterai lithium-ion. Komponen ini menjadi inti dari mobil listrik, tetapi proses produksinya sangat kompleks dan membutuhkan teknologi canggih.
Selain itu, fitur-fitur modern seperti perangkat lunak pintar, sensor otomatis, dan kemampuan pengisian daya cepat semakin menambah biaya produksi. Alhasil, mobil listrik menjadi kendaraan yang lebih dekat ke barang mewah ketimbang solusi transportasi massal.
Meskipun banyak pemerintah memberikan subsidi untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, subsidi ini sering kali tidak cukup untuk menjangkau konsumen kelas menengah ke bawah. Harga setelah subsidi tetap tinggi, menciptakan hambatan besar bagi mereka yang ingin beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil.
Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga mengguncang industri. Produsen besar seperti Ford, yang telah mengalihkan fokus penuh pada produksi mobil listrik, menghadapi tantangan berat.
Penurunan permintaan dan harga jual yang tidak kompetitif membuat banyak perusahaan harus memangkas produksi. Bahkan perusahaan yang telah menginvestasikan miliaran dolar dalam infrastruktur mobil listrik menemukan bahwa ekspektasi pasar tidak sejalan dengan realitas penjualan.
Paradoks ini menggambarkan ketidakcocokan antara tujuan mulia mobil listrik sebagai kendaraan ramah lingkungan yang inklusif dengan realitas pasar yang menjadikannya barang mewah. Jika tujuan akhirnya adalah keberlanjutan yang adil bagi semua, maka harga dan aksesibilitas harus menjadi prioritas utama. Teknologi tidak hanya harus maju, tetapi juga harus memastikan bahwa ia dapat dinikmati oleh lebih banyak orang, bukan hanya segelintir kalangan.
Pasar Indonesia perlu mengkritisi kehadiran mobil listrik. Mobil listrik mungkin adalah kendaraan masa depan, tetapi masa depan itu tidak akan inklusif kecuali hambatan harga dan aksesibilitas berhasil diatasi. Ketika mobil listrik benar-benar menjadi "mobil untuk rakyat," barulah janji transportasi hijau akan benar-benar terasa nyata.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI