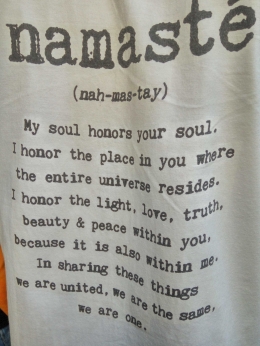Biasanya, hanya acara partai politik yang getol mengadakan acara tertentu dan dihadiri perwakilan dari berbagai daerah. Di luar itu, ada Kompasianival yang bebas dari kepentingan politik, namun juga mampu mendatangkan pengunjung dari berbagai daerah di Nusantara.
Itu bukan kata pengurus Kompasiana. Melainkan, itulah yang saya saksikan, setidaknya dalam delapan tahun terakhir, meski nama "Kompasianival" sendiri baru muncul belakangan.
Apa pun namanya, di ajang inilah saban tahun saya bisa menyaksikan banyak penulis Kompasiana dari berbagai daerah, berbagai latar belakang sosial, dan bermacam-macam profesi.
Hanya di awal-awal saja yang sedikit beraroma "Javasentris", beraroma Jakarta, namun belakangan makin meng-Indonesia.
Bayangkan, bagaimana animo mereka yang datang, merogoh kocek sendiri untuk dapat menghadiri acara tersebut. Meskipun mereka menyadari, selain harus mengeluarkan uang untuk transportasi, penginapan, juga untuk berbagai keperluan di Jakarta yang selama ini memang menjadi satu-satunya tempat acara itu diadakan.
Dari Aceh hingga Papua akan dengan mudah Anda temukan di acara tersebut. Satu sisi mengherankan, apa yang membuat mereka rela bersusah payah dan mengeluarkan uang untuk itu?
Silaturahmi. Terlepas perbedaan agama, suku, dan latar belakang daerah, di sana para pecinta dunia kepenulisan membaur. Di sana mereka menguatkan jejaring. Di situ juga mereka menunjukkan, seperti inilah Indonesia; bahwa perbedaan bukan hal yang harus dimusuhi, tapi dari perbedaan itu justru dapat melahirkan kekuatan.
Kekuatan apa yang mereka bangun? Ini adalah pertanyaan yang pantas diketengahkan, terlebih ketika politik acap melahirkan berbagai gonjang-ganjing, di sini mereka membangun kekuatan untuk menjaga tradisi diskusi, tradisi persaudaraan, hingga tradisi literasi yang telah menjadi napas mereka.
Ya, seluruh peserta Kompasianival itu adalah mereka yang memiliki minat yang sama; membaca dan menulis. Tradisi ini sempat menjadi hal langka di negeri ini, sebab penulis acap harus berjibaku hanya untuk mendapatkan tempat di koran-koran.
Di zaman media arus utama seperti koran menjadi satu-satunya "destinasi" para penulis--di luar dunia perbukuan--literasi acap menjadi masalah dalam hal peluang berkembang. Koran menjadi berhala, dan tak sedikit yang memilih mundur teratur, alih-alih mengasahnya, justru banyak calon penulis "mati muda".
Ya, di era itu, banyak yang memilih berhenti menekuni dunia kepenulisan. Bahkan aktivitas itu sempat terkesan hanya milik akademisi, pemuka masyarakat, dan para pewarta saja. Kehadiran dunia blogging, lalu lahir Kompasiana mendekati pengujung dekade pertama 2000-an, menawarkan keran lebih lebar untuk calon penulis hingga penulis profesional.
Di sini para penulis dapat mengasah kemampuannya, menjadikan aktivitas menulis tak lagi hanya domain kalangan tertentu. Sementara yang profesional bisa menjadi sahabat bagi penulis amatir untuk makin terasah. Kompasiana menjembatani itu. Kompasianival mengeratkan hubungan mereka; sesama pejuang literasi yang sering memilih rendah hati hingga mereka bahkan tak merasa dirinya sebagai pejuang. Rendah hati, bukan rendah diri, sebab di sini mereka bisa berbicara secara sejajar tanpa sekat.
Kompasianival merajut itu. Mereka yang mencintai dunia literasi saling mengakrabkan diri, hingga ada yang sepenuhnya memilih aktivitas ini sebagai mata pencaharian atau sekadar menjadikannya sebagai wahana berbagi. "It makes writing as habits". Mereka menjadikan menulis sebagai kebiasaan. Dengan kebiasaan ini, mereka tak hanya berbagi sudut pandang-sudut pandang baru, tapi juga menjadi bagian dari cara mereka mempertahankan tradisi belajar.
Ya, menulis akan selalu menuntut siapa pun yang menekuninya untuk selalu belajar. Sains berkembang, teknologi melesat, sampai dengan pola pikir dan peradaban berubah. Menulis lantas menjadi budaya yang tak lagi menjadi sesuatu yang asing, melainkan telah menyatu dengan mereka, dan menjadi diri mereka sendiri.
Kompasiana urun andil dalam memasyarakatkan tradisi ini. Bukankah dunia-dunia maju tak pernah lepas dari tradisi berdialektika, menjadikan berpikir kritis sebagai tradisi? Menulis adalah jembatan paling terang untuk budaya berpikir kritis dapat terus berjalan. Kompasiana menjadi salah satu tiang di jembatan penting dalam peradaban tersebut.
Kemajuan identik dengan tumbuhnya tradisi berpikir. Kelahiran Plato, Socrates Emile Durkheim, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, dan para pemikir dunia lainnya telah mengubah dunia, dan perubahan itu hampir tak pernah lepas dari dialektika, dari berpikir, dan melibatkan kebudayaan menulis.
Tanpa adanya kekuatan dari budaya literasi, pikiran Plato akan berhenti seiring dengan kematiannya, pikiran Nietszche akan bertahan hanya saat ia masih bernapas saja, dan berbagai pemikiran penting akan ikut terkubur bersama pemilik pikiran itu sendiri.
Namun budaya menulis telah menyelamatkan sangat banyak pikiran penting yang berasal dari lintas-zaman dan lintas-peradaban. Menulis telah membantu satu generasi dapat berkaca dari generasi sebelumnya, hingga menggerakkan mereka menciptakan sesuatu yang lebih baik.
Kompasiana urun andil di sana. Menyelamatkan pemikiran, yang terekam lewat ribuan tulisan. Kompasianival itu sendiri menjadi perayaan mereka yang bekerja menyelamatkan kekayaan pikiran. Maka kenapa Kompasianival adalah pesta sangat berharga bagi siapa saja. Sebab inilah pesta mereka orang-orang berharga yang sedang bekerja menyelamatkan khasanah paling berharga dari yang ada pada manusia: pikiran.*
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H