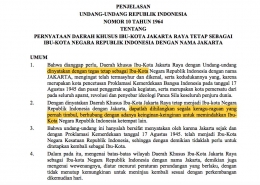Pemindahan ibu kota negara kembali jadi perbincangan. Presiden Joko Widodo sudah mengambil keputusan setelah melakukan rapat kabinet terbatas. Prosesnya tentu masih panjang. Kajian teknokratik dan lobi-lobi politik sedang dan akan terus dilakukan.
Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa ibu kota baru akan berada di luar Pulau Jawa. Bahkan, Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro terang-terangan menyebut Pulau Kalimantan hampir dipastikan akan menjadi lokasi ibu kota baru.
Di samping alasan pemerataan pembangunan, kondisi Jakarta dengan kompleksitas permasalahan jadi pertimbangan lain. Jakarta sudah berkembang melampaui daya tampung dan daya dukung lingkungannya.
Akan tetapi, mesti disadari bahwa pemindahan ibu kota tidak akan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Jakarta.
Banjir, macet, polusi dan segudang problem lain tetap menanti untuk diselesaikan. Maka, menjadi penting memikirkan langkah apa yang akan dilakukan jika kelak Jakarta tak lagi menyandang status sebagai ibu kota.
Ibu Kota yang Tak Diinginkan
Jakarta menjadi ibu kota republik ini sepertinya sekadar kebetulan dalam sejarah. Kebetulan kota ini adalah tempat proklamasi Indonesia. Jakarta tidak benar-benar diinginkan atau malah dirancang sebagai ibu kota.
Faktanya, penetapan Jakarta sebagai ibu kota memang baru dikeluarkan pada tahun 1964 melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta.
UU tersebut keluar setelah hampir 19 tahun galau menentukan ibu kota yang ideal. Wacana pemindahan ibu kota sejatinya bukan hal baru. Bahkan sudah terjadi di masa awal revolusi kemerdekaan. Presiden Soekarno pernah membentuk Panitya Agung untuk menentukan calon ibu kota.
Situasi darurat di masa itu turut memengaruhi. Ibu kota pernah dipindahkan sementara ke Yogyakarta pada (1947-1948 dan 1949-1950). Pada periode itu pemerintahan darurat juga pernah diselenggarakan di Bukittinggi, Sumatera Barat (1948-1949).
Menyikapi berbagai desakan dan tuntutan pemindahan ibu kota, baru pada 22 Juni 1962 --tepat pada saat peringatan ulang tahun kota Jakarta ke-435, Soekarno menegaskan bahwa Jakarta akan tetap jadi ibukota.
Pidato yang sama ia ulangi dua tahun berselang, sehingga akhirnya Penetapan Presiden Nomor 10 Tahun 1964 dibuat berlaku surut sejak 22 Juni 1964.
Gagasan memindahkan ibu kota tidak benar-benar hilang setelah itu. Justifikasi bahwa Bung Karno telah memilih salah satu kota di Kalimantan Tengah untuk menjadi ibu kota baru sepertinya tidak tepat. Setidaknya bisa kita merujuk pada penjelasan Penetapan Presiden Nomor 10 Tahun 1964, khususnya poin kedua yang berbunyi :
"Dengan dinyatakan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya tetap menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Jakarta, dapatlah dihilangkan segala keragu-raguan yang pernah timbul, berhubung dengan adanya keinginan-keinginan untuk memindahkan Ibu-Kota Negara Republik Indonesia ke tempat lain"
Di masa kepemimpinan Soeharto, sempat muncul kabar rencana pemindahan pusat pemerintahan ke daerah Jonggol, Jawa Barat. Di era Susilo Bambang Yudhoyono juga ide ini pernah dikaji, meski tanpa menunjuk alternatif lokasi.

Kekhususan Jakarta
Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota saat ini menerima desentralisasi asimetris, yaitu kewenangan yang berbeda jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Pengaturan itu termuat dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan asas lex spesialis melalui UU tersebut, maka ada beberapa hal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak berlaku di Jakarta. Apa saja sih perlakuan berbeda yang didapat Jakarta dengan menyandang status ibu kota negara?
Satu hal yang paling mudah diingat mungkin soal perlakuan dalam pemilihan kepala daerah (gubernur). Jika di daerah lain peraih suara terbanyak -berapapun angkanya- langsung terpilih, tidak demikian dengan pemilihan Gubernur Jakarta. Pemenangnya harus meraih suara 50% + 1 (Pasal 11).
Putaran kedua akan digelar jika pada putaran pertama tidak ada yang memenuhi kualifikasi tersebut. Seperti pilkada 2017 lalu, pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (meraih 42,99% suara) bisa mempertahankan kursi gubernur dan wakil gubernur andai pengaturannya sama dengan daerah lain.
Tapi dengan aturan yang berbeda, maka digelarlah putaran kedua yang kita tahu bersama dimenangkan oleh Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno.
Selain perbedaan dalam pilkada ini, sepertinya tidak banyak yang tahu apa lagi kekhususan Jakarta. Otonomi tunggal adalah yang utama. Tidak seperti di daerah lain di mana kabupaten/kota adalah daerah otonom, di Jakarta hanya ada kabupaten/kota administrasi. Perbedaan kedudukan ini melahirkan sejumlah turunan.
Lima walikota dan satu bupati di Jakarta tidak dipilih melalui pemilihan kepala daerah langsung. Mereka adalah ASN dari jalur karier yang ditunjuk oleh gubernur (Pasal 19).
Kota/kabupaten administrasi dalam struktur organisasi Pemprov DKI Jakarta adalah perangkat daerah, tak ubahnya dinas dan badan. Walikota dan bupati kedudukannya sejajar dengan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
Selain tak ada pilkada walikota/bupati, warga Jakarta juga tidak memilih DPRD di level kota/kabupaten administrasi. DPRD hanya ada di tingkat provinsi. Maka, tidak ada juga Peraturan Daerah (Perda) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat kota/kabupaten.
DKI Jakarta juga diberikan kewenangan khusus dalam bidang tertentu, seperti tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan permukiman, transportasi, industri dan perdagangan serta pariwisata (Pasal 26).
Gubernur dibantu oleh empat orang Deputi untuk menangani urusan-urusan tersebut (Pasal 14). Jabatan struktural eselon 1 ini khas, karena tidak ada di daerah manapun.
Gubernur Jakarta mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan serta menghadiri rapat kabinet yang membahas kepentingan ibu kota negara (Pasal 31 dan Pasal 26).
Di samping itu, masih ada beberapa perbedaan minor pemerintahan daerah di Jakarta dengan daerah lain, misalnya soal jumlah anggota DPRD (Pasal 12), keberadaan Dewan Kota/Kabupaten (Pasal 24) dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (Pasal 25).
Masa Depan Jakarta
Pertanyaan menarik saat ini adalah, jika ibu kota pindah bagaimana dengan desentralisasi asimetris terhadap Jakarta? UU 29/2007 sudah pasti akan dicabut. Apakah itu juga artinya Jakarta akan mendapat perlakuan yang sama dengan daerah (baca: provinsi) lain di Indonesia?
Setidaknya ada tiga pilihan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, Jakarta tetap mendapat kewenangan khusus berupa otonomi tunggal di tingkat provinsi sekalipun bukan lagi ibu kota. Salah satu konteks penerapan desentralisasi asimetris adalah kesulitan teknokratis suatu pemerintah daerah (Lay, 2010).
Otonomi pada wilayah kota berpotensi menimbulkan ketidaksangkilan. Setiap wilayah kota juga memiliki eksternalitas yang tak bisa dipisahkan dengan kota di sekitarnya.
Pengaturan dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang kompak dan terintegrasi merupakan suatu kebutuhan agar penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah lebih efisien dan efektif.
Kedua, pemerintahan daerah di Jakarta diperlakukan sama dengan daerah lain. Berarti, kota/kabupaten di Jakarta akan menjadi daerah otonom. Pilihan ini sejujurnya yang paling berisiko.
Bisa dibayangkan bagaimana kacaunya kalau walikota/bupati di Jakarta tidak sejalan dengan gubernur. Belum lagi potensi perbedaan kebijakan antara satu kota dengan kota lain di Jakarta.
Ketiga, Jakarta ditetapkan sebagai satu kota yang cuma dipimpin seorang wali kota. Menilik sejarah, sampai tahun 1959 Jakarta juga masih berstatus sebagai kotapraja bagian dari provinsi Jawa Barat.
Dengan luas wilayah yang 'cuma' sekitar 660 km2 --tidak beda jauh dibandingkan dengan Pulau Samosir di tengah Danau Toba---Jakarta lebih pantas disebut kota alih-alih provinsi. Hanya saja, ruang lingkup kewenangan wali kota tidak sebanding dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi Jakarta.
Kedudukan provinsi ditambah status daerah khusus ibu kota yang melekat saat ini saja tidak cukup untuk membantu Jakarta menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Apalagi kalau Jakarta cuma dipimpin seorang wali kota, layaknya Bogor, Tangerang atau Bekasi.
Dengan melihat berbagai konsekuensi, maka kajian soal pemindahan ibu kota hendaknya tidak hanya fokus pada pemilihan calon ibu kota baru. Nasib Jakarta kelak juga harus menjadi perhatian.
Bagaimana pengaturan yang ideal bagi kota ini perlu dipikirkan masak-masak. Jangan sampai timbul kesan 'habis manis sepah dibuang' bagi calon mantan ibu kota ini.
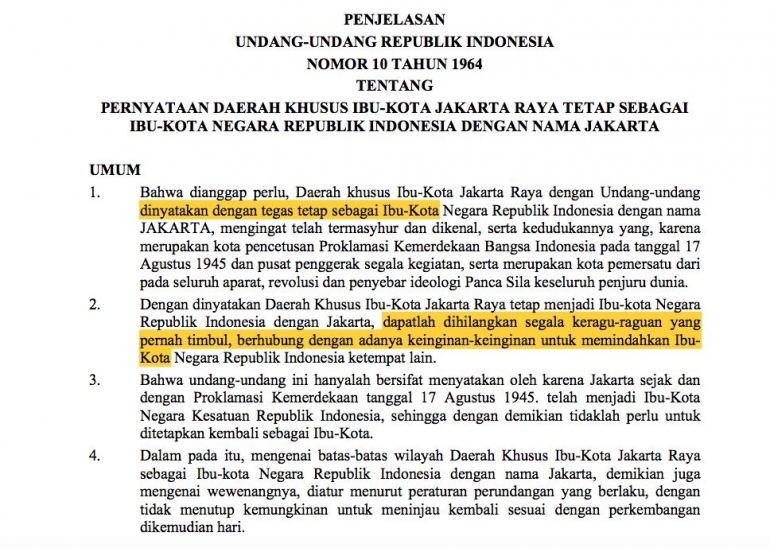
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H