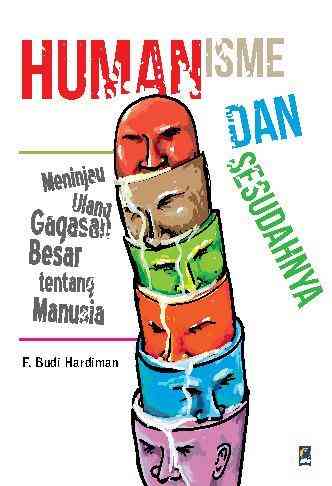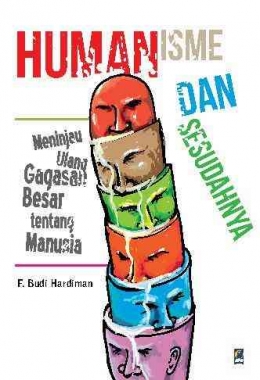Kalau ada pihak yang dengan yakinnya mengumumkan perang terhadap politik identitas, yang berarti juga perang terhadap terorisme, radikalisme, intoleransi (diskursus politik identitas di Indonesia memang terutama adalah motif agama) dan lain sebagainya itu wajar saja. Mengingat negara kita memiliki kekayaan--di samping sumber daya alam--suku dan etnik yang melimpah, yang masing-masing memiliki adat dan tradisi yang dijunjung tinggi; juga agama.
Bahwa radikalisme dan intoleransi mengancam langgengnya kekayaan itu, apalagi terhadap minoritas. Di Indonesia, radikalisme selalu dalam pengertian agama, khususnya Islam, oleh sebab itu jika kata ini atau yang serupanya dibunyikan, yang terbayang di benak kita adalah kelompok-kelompok Islam fundamentalis.
Lebel Islam fundamentalis belakangan agaknya lebih vulgar, maka istilah lain yang lebih masuk akal dicoba untuk ditampilkan, yaitu "manipulator agama". Mungkin fundamentalis itu tidak sampai melakukan aksi teror, tetapi menggunakan agama secara fideistik (agama sebagai satu-satunya solusi di atas yang lainnya) demi mencapai tujuan-tujuannya.
Manipulator agama atau tindakan memanipulasi agama dilatari oleh pemahaman yang sempit terhadap ajaran agama. Sikap menjadi eksklusif, segalanya tidak penting kecuali doktrin agama itu sendiri. Kendati pada akhirnya agama dijadikan alat untuk menindas, serta mencederai hak-hak minoritas, atau melukai kemanusiaan.
Sebagai antitesa, humanisme muncul dengan membawa nilai-nilai universalitas manusia. Humanisme itu sendiri adalah paham yang melihat manusia sebagai makhluk yang dengan kodratnya patut dihormati. Humanisme hadir sebagai pembebas terhadap sikap-sikap yang melucuti hak-hak asasi manusia.
Model humanisme Indonesia misalnya ada pada diri Gus Dur (ada yang menulis buku "Humanisme Gus Dur"). Sebab Gus Dur memang tampil sebagai pembela kemanusiaan, melindungi hak-hak minoritas yang bukan hanya dalam tataran wacana, tetapi juga dalam tindakan, utamanya ketika ia menjabat sebagai Presiden RI keempat. Keputusannya yang paling penting adalah diakuinya agama Konghucu, yang sebelumnya digolongkan ke dalam agama Budha. Gus Dur mengakhiri status mereka yang merasa hidup seperti setengah manusia menjadi manusia seutuhnya yang punya hak setara.
Karena merupakan antitesa, humanisme sendiri dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Selain karena datangnya dari barat yang sekuler, pertimbangan utama humanisme bukanlah agama, melainkan kemanusiaan. Ditambah lagi, lahirnya humanisme dilatari terutama oleh sikap kritis terhadap fenomena kekerasan atas nama agama, serta kekolotan dalam beragama.
Satu buku yang bagus dalam mengupas humanisme adalah buku yang ditulis oleh F. Budi Hardiman, "Humanisme dan Sesudahnya: Meninjau Ulang Gagasan tentang Manusia". Buku itu tipis, dan merupakan bahan kuliah di Komunitas Salihara.
Humanisme merupakan suatu paham yang berupaya untuk mengembalikan manusia pada kemanusiaannya, setelah sekian lama hidup di bawah penindasan monopoli tafsir institusi agama, dalam hal ini Kekristenan abad pertengahan. Jauh sebelum itu, konsep humanisme sudah ada sejak zaman Yunani kuno, melalui paidea--tulis Hardiman--yang mengolah bakat-bakat kodrati manusia. Serta zaman Romawi kuno yang menyebut manusia animal rationale.
Menjadi manusia seutuhnya, memang menjadi cita-cita para pemikir humanisme. Misalnya Auguste Comte yang meletakkan humanisme pada tahap positif (ilmiah), tingkatan tertinggi dalam perkembangan masyarakat setelah tahap teologis dan metafisis. Di sini, Comte pun mengandaikan agama dalam tahap teologis harus dilampaui jika ingin menjadi manusia seutuhnya.
Darwin pun demikian. Teori evolusi sendiri menampilkan tidak adanya ruang bagi analisis berbasis agama bagi perkembangan manusia. Semuanya berlangsung secara biologis melewati proses alamiah (seleksi alam).
Ludwig Feuerbach, yang mewarisi tradisi kritik agama dari zaman Xenophanes membalik pengandaian kitab suci. Tulis Hardiman: "Jika Kitab suci berkata bahwa tuhan menciptakan manusia menurut citranya, Feuerbach berkata bahwa manusia menciptakan tuhan menurut citranya."
Jadi, semuanya tergantung dari cara berpikir manusia. Manusia bisa mengeluarkan Tuhan dan segala ketakutan yang ditimbulkannya dari pikiran, lalu berkehendak sesuai dengan kodratnya sendiri.
Ketiga tokoh di atas cukup meyakinkan bahwa humanisme patut dicurigai merupakan agenda ateisme untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Ditambah lagi dengan kehadiran Nietzsche yang melalui tokoh Ubermensch nya, tampil sebagai pembunuh Tuhan dengan mendeklarasikan bahwa Tuhan telah mati.
Namun sesungguhnya kata Hardiman, humanisme tidak bermaksud menyerang agama, melainkan kepercayaan terhadap agama yang menyebabkan manusia menjadi tertutup, teralienasi, dan melakukan tindakan teror.
Misalnya Karl Marx, dengan mengutip Kern, Hardiman menyebut Marx memandang bahwa, "Unsur manipulatif agama terletak pada fungsinya yang menutupi akar-akar sesungguhnya kemiskinan serta alienasi kelas-kelas melarat." Agama menghadirkan harapan dan ilusi, yang disesap oleh kelompok termarjinalkan bagai opium, sebagai tempat pelarian dari kondisi ketertindasannya oleh kelas borjuis. Padahal ketertindasan itu hanya dapat diakhiri dengan satu jalan humanisme: perubahan struktural masyarakat.
Bahkan Nietzsche yang membunuh Tuhan pun, bisa jadi yang dibunuh bukan Tuhan yang sesungguhnya, melainkan konsep ketuhanannya. Hardiman memberi ilustrasi yang menggelitik: bagaimana mungkin kaum ateis yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan dapat membunuh Tuhan? Tuhan hanya dapat dibunuh kalau dia ada, dan hidup. Sedang ateis tak percaya Tuhan ada.
Namun bukannya tanpa konsekuensi. Humanisme yang menampilkan diri di dalam sejarah sebagai penyempurna kemanusiaan manusia, ternyata punya borok yang sama dengan pemahaman agama yang kolot. Humanisme menyimpan eksklusifisme dan alienasi manusia.
Jangan dikira bahwa penjajahan Eropa terhadap negara-negara dunia ketiga semata demi invasi ekonomi dan teritorial belaka. Di balik praktik kolonialisme, ada visi humanisme yang dibawa-bawa. Dunia ketiga diandaikan sebagai kawasan yang dihuni oleh manusia-manusia terbelakang. Sebagai bangsa yang maju, maka Eropa memiliki panggilan moral untuk memajukan bangsa-bangsa itu, melalui jalan kolonialisme, mendidik mereka supaya menjadi manusia yang utuh.
Humanisme juga merupakan sebuah kedok bagi Nazisme Hitler di Jerman. Pembersihan etnik Yahudi dalam Kamp Konsentrasi demi penyelamatan ras Aria, yang menurut Hitler, adalah ras unggul yang harus dibiarkan hidup. Agar umat manusia selamat dari ketertinggalan dan kebobrokan secara rasial.
Komunisme, menghabisi kelas borjuis demi terciptanya kondisi kemanusiaan yang setara. Utamanya di era Stalin, ia tidak hanya eksklusif terhadap kelas borjuis tetapi juga memakan kamerad-kameradnya sendiri yang berjasa dalam mendirikan rezim komunis Soviet.
Tiga contoh di atas adalah anomali humanisme. Mereka ingin mewujudkan kemanusiaan yang agung namun memperlakukan manusia yang tidak sama dengan mereka seolah bukan manusia. Mereka mencabut rasa manusiawi atas manusia yang mereka hadapi. Kalau begitu, humanisme tak ubahnya ajaran terorisme yang eksklusif, hanya saja terbalut dalam jubah yang berbeda dari kelompok agamis.
Mari kita berkaca pada dunia politik dewasa ini, seolah pihak yang memerangi politik identitas berjubah agama mengesankan diri sebagai kelompok humanis. Mereka memosisikan diri sebagai antitesa kelompok agama yang intoleran, karena mereka sendiri humanis, toleran, nasionalis, namun humanisme dijalankan dengan cara melontar pelbagai olok-olokan, serta memberi julukan anti-pancasila kepada lawan politiknya.
Mereka memang lebih menyebut diri nasionalis ketimbang humanis, dan memuja tokoh-tokoh yang dipandang nasionalis juga. Namun cara-cara mereka yang menganggap diri menjadi pelindung kaum minoritas, toleran, serta cara berpikirnya moderat (maju), serta memandang manusia berdasarkan kemanusiaannya, mengklaim diri lebih manusiawi. Hal itu sudah dengan sendirinya menerangkan bahwa mereka sebenarnya pengusung humanisme, walau bukan humanis yang ateis.
Sikap kelompok humanis ini rupanya sama saja dengan mereka yang ekstremis agama, yang melontarkan eksklusivisme dalam bentuk pembid'ahan (yang terburuk dari itu adalah pengkafiran), yang merupakan musuh utama mereka. Mereka juga punya kosakata "kadrun" untuk melabeli lawan mereka, yang juga mencela dengan julukan "cebong"; keduanya sama saja.
Jadi, kalau begitu apakah humanisme adalah gagasan usang yang harus ditinggalkan? Hardiman memandang bahwa humanisme adalah gagasan yang bagus bagi kemanusiaan. Hanya saja perlu dilepaskan dari klaim keabsolutannya. Yaitu anggapan bahwa manusia adalah pusat kenyataan perlu diubah menjadi manusia merupakan bagian dari lingkungan, di mana manusia terhubung secara interaktif, bukan secara hierarkis antara manusia yang manusiawi dengan manusia yang tertutup.
Caranya adalah (1) menyadari apa yang dikatakan oleh Richard Rorty bahwa humanisme secara pragmatis berupaya mewujudkan solidaritas sosial. Namun solidaritas itu tidak dapat tercapai jika humanisme diposisikan sebagai metafisika kemanusiaan. Yaitu Manusia dengan M besar dibedakan dengan m kecil. M besar dipandang sebagai manusia yang humanis dan m kecil tidak humanis.
(2) pemikiran seperti ini merupakan konsekuensi dari dekonstruksi Derrida yang mengandaikan metafisika kemanusiaan dalam antinomi biner. Humanisme menjadi kutub superior dan yang lainnya menjadi inferior, di mana humanisme akan selalu memandang dirinya yang paling benar, dan kebenaran itu akan dijadikan acuan kemanusiaan universal.
(3) oleh sebab itu, seperti yang diandaikan oleh Jurgen Habermas, humanisme memerlukan tindakan reflektif, yaitu melihat kembali ke belakang bagaimana jalannya humanisme selama ini. Dari hasil reflektif itu akan ditemukan lubang-lubang atau ketidaksesuaian visi humanisme itu sendiri yang perlu diperbaiki.
Walhasil, F. Budi Hardiman menawarkan konsep humanisme lentur. Yaitu humanisme yang tidak mengabaikan nilai-nilai agama, dan tidak anti terhadap agama. Sebab bagaimanapun, manusia di samping makhluk biologis, juga adalah makhluk spiritual. Manusia mendapatkan inspirasi dalam menjalani hidup bukan hanya dari proses intelektual semata, tetapi juga spiritualitas, ketentraman batin dalam memilih jalannya terasah dalam praktik-praktik ritual keagamaan.
Juga (humanisme) tidak memosisikan manusia sebagai pusat kenyataan, di mana Manusia dengan M besar merasa mereka adalah penentu kemanusiaan manusia. Melainkan manusia harus disadari sebagai makhluk yang saling mengisi, interaktif, di mana kemanusiaan terbangun lewat satu sistem bahasa yang sama, yang nyambung lewat interaksi.
Begitupula dalam konteks politik kita. Kelompok humanis seharusnya bukan hanya mereka yang memerangi praktik manipulasi agama, atau politik identitas. Tetapi humanisme terbentuk dari interaksi antar manusia secara sehat, melampaui sekat-sekat agama, suku, dan antar golongan.
Yang kita butuhkan adalah humanisme yang inklusif, yang tidak menyekat manusia berdasarkan stereotipenya sendiri. Budi Hardiman menyebutnya sesudah humanisme (ia lebih memilih istilah itu ketimbang post-humanisme), yaitu humanisme yang ditinjau kembali; kemanusiaan yang mampu menjalin jaringan antar anggota komunitas dan lingkungan, dan jauh dari sikap diskriminatif.
***
Judul buku: Humanisme dan Sesudahnya: Meninjau Ulang Gagasan Besar tentang Manusia
Penulis: F. Budi Hardiman
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)
Tahun: Cet. I, 2012
Tebal: xi + 90 halaman
ISBN: 978-979-91-0459-5
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H