Perbedaan itu membuat cara pandang saya sebagai seorang murid juga terpengaruh. Matematika terkesan menjadi momok. Sesuatu yang mengerikan, lebih horor dari sekadar film horor.
Karena yang ditampilkan adalah keruwetan dan kerumitan-kerumitan yang sebenarnya sangat sederhana. Sementara bahasa, kala itu tak cukup membuat risau.
Malah, saya menganggap pelajaran bahasa sebagai pelajaran yang paling gampang dan tak perlu menguras terlalu banyak pikiran.
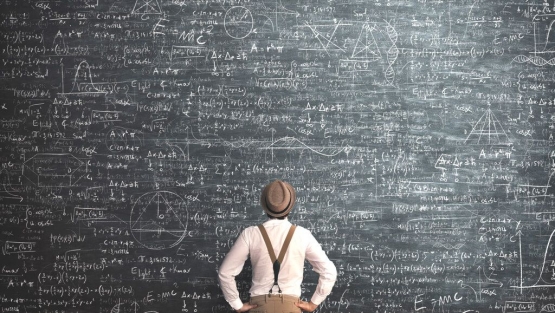
Saking remehnya saya menganggap pelajaran bahasa, rupanya nilai terendah di NEM saya ada pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Sementara, nilai mata pelajaran matematika dan mapel-mapel IPA ketika itu malah lumayan tinggi. Selisihnya juga lumayan jauh dari nilai bahasa Indonesia.
Di lain hal, dulu waktu masih menyandang predikat sebagai pelajar, tak jarang saya mendengar semacam pemeo. Bahwa anak-anak IPA itu pasti lebih pintar dari anak-anak IPS apalagi bahasa.
Tak heran jika banyak orang yang membanggakan kelas IPA dibandingkan kelas lain. Bahkan, dalam beberapa kali sambutan saat upacara, secara implisit, kepala sekolah kerap menyebut anak-anak IPS sebagai biang masalah di sekolah.
Ingatan saya yang sekilas itu, saat berhadapan dengan kawan saya yang ahli matematika, seolah dihancurkan hingga remuk tak berbentuk.
Pikiran yang kadung menemukan bentuk dan pola dalam diri saya seolah dipreteli. Bagaimana bisa matematika dianggap sebagai bahasa? Begitulah, pertanyaan yang membisiki pikiran saya ketika itu.
Kawan saya yang memang piawai berbicara itu kemudian memberi uraian. Bahwa sudah sejak dahulu bahasa dipahami sebagai sebuah sistem.
Maka, di dalam sistem itu ada pola dan struktur yang terbangun dari unsur-unsur tertentu. Melalui sistem itu pula, di dalam bahasa terdapat konstruksi pikiran.








