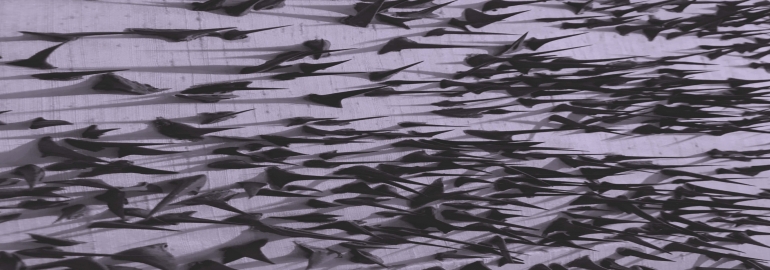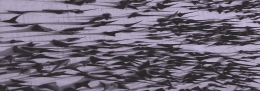Auschwitz adalah tempat yang aneh, tulis Rm. Agustinus Rachmat Widiyanto, OSC dalam kunjungannya bersama romobongan peziarah ke Auschwitz-Birkenau. Sebuah penjara yang berlokasi di tempat yang sepi, tersembunyi, terpencil dan berlokasi di tengah padang rumput yang luas, dibatasi oleh pagar kawat listrik dan berduri.
Kalau kita masuk ke dalam kompleks penjara itu, perlahan-lahan rasa sepi itu berubah menjadi rasa ngeri, saat kita menyaksikan sisa-sisa kekejaman dan penderitaan anak manusia, sepatu dan pakaian yang kumal dan lusuh, gumpalan rambut wanita yang dipangkas untuk menjadi rambut boneka mainan anak-anak Jerman, kumpulan gigi yang dicabut begitu saja untuk menyiksa atau merampas gigi emas, tiang gantungan, ruang penyiksaan, ruang eksekusi mati, dan lain-lain.
Sesaat setelah merasa mual dengan lokasi tersebut, Rm. Agustinus menarik diri dari rombongan untuk merokok. Di luar ia bertemu dengan seorang kakek tua dan bertanya kepadanya, "Pak apakah saya boleh merokok?" Kakek itu menjawab, "Jika dapat, Anda janganlah merokok. Tempat ini adalah tempat suci bagi kami, dan kami mempunyai trauma, mempunyai ingatan yang pahit akan asap!" Pengalaman Rm. Agustinus Rachmat Widiyanto, OSC ini mengingatkan kita akan frasa Elie Wiesel dalam novelnya La Nuit, 'I will not forget':
Takkan pernah kulupakan malam itu, malam pertama dalam kamp yang telah menyebabkan seluruh hidupku menjelma menjadi suatu malam tak berkesudahan, tujuh kali terkutuk dan tujuh kali terkunci. Takkan pernah kulupakan asap itu. Takkan pernah kulupakan wajah-wajah mungil anak-anak itu, yang kulihat tubuh-tubuhnya menjelma bagaikan karangan bunga untuk orang mati; terdiri dari asap di bawah langit biru tak bersuara. Takkan pernah aku lupakan lidah api itu, yang membakar habis imanku untuk selama-lamanya. Takkan pernah aku lupakan kesunyian malam itu, yang merampas dariku untuk selama-lamanya, seluruh gelora hidupku. Takkan pernah kulupakan saat-saat itu, yang membunuh Allahku dan jiwaku dan menghancurkan semua cita-citaku. Takkan pernah kulupakan semua hal ini, biarpun hidupku akan serasa jadi terkutuk selama-lamanya.
La Nuit merupakan sebuah karya yang muncul kala bahasa dan pikiran manusia dilukai oleh penderitaan. Yang ada hanyalah takdir seorang manusia Yahudi yang lepas dari cengkeraman maut sembari meratapi jutaan orang yang mati di belakangnya, anak-anak yang dibuang ke perapian dan perempuan-perempuan yang mati ditembak tanpa mengenakan pakaian.
Bangsa Yahudi yang pengalaman akan Allah sejarah menamai diri sebagai bangsa pilihan, di Jerman mereka dituduh bukanlah manusia seutuhnya (geginrasse). Tidak heran usai Auschwitz baik Yahudi maupun non-Yahudi tidak bisa lagi mempercayai Allah sejarah Kitab Suci, "after Auschwitz what else can a Jew say about God?" Tidak ada arti sejarah lagi yang bisa diselamatkan tanpa Auschwitz, tidak ada kebenaran sejarah yang bisa dipertahankan dengan kembali ke Auschwitz, tidak ada Tuhan, yang mana seseorang dapat beribadah dengan punggungnya ke Auschwitz.
Hester panim, tulis Zvi Kolitz, penderitaan di Auschwitz adalah saat-saat Tuhan menyembunyikan wajah-Nya. Auschwitz menjadi kulminasi sebuah proses hubungan jangka panjang Allah dan manusia yang berangsur-angsur surut. Dalam suratnya yang ditulis di Buenos Aires (1945), Kolitz memberi sebuah frasa terkenalnya, "Saya percaya pada matahari, bahkan jika ia tidak bersinar. Saya percaya pada cinta, bahkan jika saya tidak merasakannya. Saya percaya pada Tuhan, bahkan jika Dia diam".
Tentu frasa ini tidak cukup memuaskan untuk menjawab pertanyaan, jika Yahudi adalah bangsa pilihan, mengapa Allah membiarkan holocaust terjadi? Sebagian orang Yahudi berupaya memahami kondisi mereka dengan merujuk pada Kiddush Hashem: pengudusan nama Tuhan.
Namun orang-orang Yahudi di Auschwitz yang meninggal, tidak punya pilihan untuk mati atau bertobat sebagai orang Yahudi. Tidak ada di Auschwitz apakah seorang Yahudi itu religius atau tidak. Theodor Adorno bahkan menyebut berpuisi bagi mereka setelah peristiwa tersebut adalah sebuah tindakan barbar. Bagaimanapun, adalah tidak sopan dan tidak dapat dipercaya untuk berbicara tentang cinta dan Tuhan yang peduli kepada kita di hadapan anak-anak yang sekarat dalam api.
Greenberg menambahkan, melompat dan mengambil anak dari lubang, membersihkan wajahnya dan menyembuhkan tubuhnya adalah satu-satunya hal yang diperhitungkan. Bagi mereka, kemanusiaan lebih berharga bahkan dari nyawa manusia. Prioritas pada kemanusiaan ini merupakan suatu loncatan dalam teologi Yahudi yang lalu menghubungkan penderitaan mereka dengan konsep Hamba Yahweh yang Menderita merujuk pada Yesaya 53. Ignaz Maybaum menyebutnya sebagai Martyrologi Yahudi, fungsi penyelamatan hamba Tuhan, yang mana dalam holocaust Israel adalah hamba Tuhan yang telah menanggung dosa-dosa seluruh dunia sebagai perwakilan.
Tidak hanya itu, pengalaman Auschwitz kemudian membuat orang Yahudi menafsir ulang teks-teks perjalanan sejarah bangsanya bersama Allah hingga tiba pada suatu kesadaran yang radikal, yakni Allah turut menderita bersama mereka di Auschwitz sebagaimana sewaktu di pembuangan, shekinah. Mengutip kembali apa yang ditulis Zvi Kolitz, "jika saya tidak percaya bahwa Allah telah menetapkan kita menjadi umat pilihan-Nya, saya akan percaya bahwa kita telah dipilih oleh penderitaan kita".
Bagaimana mungkin orang bertanya apakah Tuhan ada di antara mereka (orang Yahudi)? Kita mungkin tidak dapat memahami Auschwitz dengan Tuhan, tetapi kita tidak dapat memahami Auschwitz tanpa Tuhan. Gambaran Allah shekinah, Allah yang turut menderita ini secara tidak langsung namun disadari mengerucut pada seorang pribadi dari Nazaret yang wafat di Salib Golgota beribu tahun yang lalu. Dia adalah Yesus yang oleh iman kristen diimani sebagai Mesias atau Kristus. Maka teodise Auschwitz juga menuntut pertanggungjawaban dari teologi Kristiani.
Johann Baptist Metz, teolog Katolik dari Mnster yang dipengaruhi oleh Auschwitz dapat dijadikan representasi menjawab teodise Auschwitz. Ia mengatakan demikian "ask yourselves if the theology you are learning is such that it would remain unchanged before and after Auschwitz. If this is the case, be on your guard".
Aturan Metz harus dianggap serius karena dua ciri teologi Kristen tradisional sebetulnya melanggengkan gerakan antisemitisme. Pertama, klaimnya bahwa orang-orang Yahudi dikutuk oleh Tuhan. Kedua, ideologi supersessionist ini, menginspirasi dan memperkuat praktik anti-Yahudi yang diwujudkan dalam khotbah, pengajaran, dan pembentukan identitas.
Maka teologi setelah Auschwitz dari perspektif kristiani, juga merupakan pertanggungjawaban atas tragdi kemanusiaan ini. Dua frasa terkenal Metz, "Kita dapat berdoa kepada Auschwitz, karena juga di Auschwitz didoakan", dan "kami tidak pernah kembali ke belakang Auschwitz. Di luar Auschwitz kami tidak pernah datang sendirian, tetapi hanya dengan para korban Auschwitz", menjadi inspirasi dalam dialog Kristen-Yahudi sebagaimana yang termaktub dalam Nostra Aetate salah satu dokumen Konsili Vatikan II.
Metz menentang ideologi atau teologi apa pun dari Auschwitz. Tetapi Auschwitz dapat membawa kita kembali ke bahasa doa yang Alkitabiah hampir terkubur. Sebuah bahasa penderitaan seperti yang terdapat dalam Mazmur Ratapan yang menyimpan keluhan, tuduhan, bahkan pemberontakan melawan Allah.
Metz menyebut ini sebagai bahasa mistisisme penderitaan Allah (God-mysticism), pertanyaan-pertanyaan penderitaan yang lahir dari tengah-tengah penderitaan, dan bahasa tersebut ditujukkan kepada Allah. Metz tergerak oleh pertanyaan Ayub tentang keadilan bagi para penderita yang tidak bersalah. Pertanyaan teodise mengapa adalah pertanyaan utama dari teologi.
Metz berupaya menjawab tuduhan orang Yahudi atas kematian tak bersalah mereka di negara berbasis kristen dengan jawaban yang sangat frontal, "kami dulu berbicara tentang penderitaan yang tidak bersalah sama sekali". Oleh karena itu bagi Metz, Kristologi sebagai soteriologi membungkam pertanyaan teodise. Kita harus mengajukan pertanyaan mengapa dengan Kristus di kayu salib, mari kita akui pertama-tama.
Jika kita berbicara terlalu banyak dan terlalu cepat tentang peran keselamatan yang diduduki Kristus, dan bukan tentang mistisisme Tuhannya, bahkan mistisisme Tuhannya yang menderita, maka kita menjadi tidak peka terhadap penderitaan orang lain. Bukan pertanyaan Luther "bagaimana saya mendapatkan Tuhan yang ramah" adalah inti dari pemikiran teologis saat ini, tetapi pertanyaannya, mengapa gunung penderitaan ini?
Gunung-gunung penderitaan yang disebut Metz ini tidak boleh dijelaskan oleh Allah yang menderita secara kristologis, bahkan triniter. Dia berkata, "Tidak ada rekonsiliasi dengan Tuhan di belakang sejarah manusia tentang penderitaan". Tesis ini lebih pada ketakutan Metz bahwasannya estetika rahasia dari penderitaan menjadi sebuah pengabadian dari penderitaan umat manusia.
Duka tidak mengenal kedaulatan, penderitaan lebih tepatnya ingin diperjuangkan. Metz juga mengkritik pembicaraan singkat tentang kemahakuasaan Tuhan. Semua klaim tinggi tentang Tuhan dan Kristus harus diberikan janji akan masa depan: kami berharap Tuhan akan menunjukkan kemahakuasaan-Nya bahwa Yesus akan menjadi Mesias yang diharapkan, bahwa Tuhan akan menjadi Tuhan. Di sini dan hari ini kita hanya dapat berbicara tentang kuasa Allah. Hanya seruan apokaliptik yang tersisa bagi kita: Tuhan, di manakah Anda?
Demikianlah pertanyaan-pertanyaan Auschwitz yang kendati dijawab namun tetap menyisihkan pertanyaan yang lainnya. Diskusi pro dan kontra menggambarkan suatu kerprihatinan yang rill dan serius dari setiap orang yang mau bercerita termasuk merumuskan teologinya setelah Auschwitz. Bersama Auschwitz, jika ada teologi yang terpisah dari masyarakat dan kondisi mereka, maka sebaiknya teologi tersebut berhenti untuk ada.
Saya sendiri menyadari bahwa penggambaran mengenai Auschwitz dalam skripsi ini tidak mewakili tragedi Auschwitz karena terpisah jarak dan ruang serta waktu dari konteks tersebut. Namun pembacaan terhadap ragamnya teks yang kendati terbitan terkini, 'nafas penderitaan Auschwitz' masih berteriak, melahirkan suatu amarah dalam diri untuk terus menyuarakan tentang kemanusiaan yang terkadang menjadikan Allah tertuduh berulangkali dalam forum teodise.
Bagaimanapun itulah teologi, yang berusaha memahami Allah bahkan ketika penderitaan memaksa untuk menyangkali-Nya. Namun seperti apa yang dikatakan Metz, "dalam bahasa doa seseorang bisa mengatakan apa saja kepada Allah, termasuk tidak mempercayai-Nya. Asalkan katakanlah itu pada Allah. Karena ketika pertanyaan itu datang kepada Allah, selalu ada sesuatu yang masih terbuka".
Auschwitz kini bukan lagi nama sebuah tempat, melainkan sebuah termin teknis penderitaan abad XX. Maka benar bahwa memori akan Auschwitz tidak boleh berhenti. Ia harus selalu dikenang, tidak hanya dalam agama Yahudi atau Kristen, melainkan mencakup semua. Karena Auschwitz juga berarti guncangan yang paling dalam dan penolakan dari kepenuhan teologis apa pun.
Setelah Auschwitz teologi Kristen tidak lagi dapat menjadi penuh seperti sebelumnya. Teologi terkadang harus tetap diam. Ada kelemahan teologi yang mengetahui jawaban atas semua pertanyaan teodise. Lebih daripada itu, teologi setelah Auschwitz mengetahui tentang kesamaan harapan kita akan kerajaan Allah.
Baik orang Yahudi maupun Kristen memiliki "proyek Mesias" yang sama, seperti yang dikatakan Clemens Thoma, untuk bekerja menuju "keadilan, perdamaian, dan integritas ciptaan" di dunia kita yang menyedihkan. Semuanya itu dikerjakan hanya demi Dia yang mati di Golgota, dan yang mati di Auschwitz, Golgota di zaman Modern. Inilah perjuangan untuk keluar dari bayang-bayang kegelapan yang dipenuhi kekerasan dan perang yang besar.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI