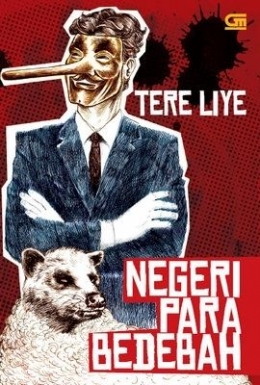Terlepas dari sikap santuy Tere Liye, persoalan "pengadilan buku" sesungguhnya memang masalah serius dan kronis sejak dahulu kala.
"Pengadilan buku" dengan prasangka berdasarkan bibliofobia (fobia terhadap buku) sejak era Sumeria kuno kerap melahirkan pelarangan buku serta pemusnahan dan pembakaran buku yang dianggap berbahaya atau setidaknya tidak sejalan dengan pemikiran atau kebijakan para rezim penguasa atau otoritas yang dianggap berwenang.
Bibliosida (bibliocyde, dari kata "bibliography" dan "genocide"), yakni pemusnahan buku, juga dialami para intelektual reformis Eropa di Abad Kegelapan (Dark Ages), seperti Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei, yang pemikiran mereka dianggap bertentangan dengan konsep sains yang diusung pihak Gereja sebagai otoritas yang berwenang atas segala hal saat itu.
Jangan dilupakan juga genosida buku besar-besaran yang dilakukan bala tentara Tartar dari Mongolia yang menginvasi khilafah Islam di Irak pada akhir masa kejayaannya. Pasukan Kuning yang dipimpin oleh Panglima Timur Leng itu memusnahkan jutaan buku dari berbagai perpustakaan publik yang banyak tersebar di negeri itu, terutama di kota-kota pusat intelektualisme, seperti Baghdad dan Basrah.
Konon air Sungai Tigris dan Eufrat di Irak yang kala itu jernih berubah menjadi berwarna hitam legam akibat tinta jutaan buku yang dilarung ke sungai.
Di Indonesia pun, dalam skala yang berbeda, sampai sekarang masih kerap terjadi pelarangan dan pembakaran buku, terutama buku-buku yang dianggap beraliran kiri atau sosialisme dan komunisme.
Padahal Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 telah menyatakan bahwa kewenangan pelarangan buku oleh Kejaksaan Agung sesuai pasal 1 ayat (1) UU No. 4/PNPS/1963 adalah bertentangan dengan konstitusi negara.
Hal ini berarti siapa pun boleh menerbitkan buku apa saja, sejauh itu didasari pada informasi yang sahih. Dan merupakan hak asasi manusia bagi siapa saja untuk boleh membaca buku apa saja sesuai keinginan dan kebutuhannya.
Tapi memang fakta hukum tidak senantiasa sejalan dengan kemauan rezim penguasa. Terlebih lagi jika rezim penguasa cenderung paranoid atau alergi terhadap ide-ide kritis serta perubahan, termasuk yang ada di media dan buku.
Benarlah apa yang dikatakan oleh Sayyid Quthb (1906-1966), sang sastrawan Mesir seangkatan Naghuib Machfoudz, yang juga penulis tafsir Al-Qur'an berjudul Fi Zilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an), bahwa "Satu peluru hanya mampu menembusi satu kepala namun satu tulisan bisa menembusi beribu kepala, malah jutaan."