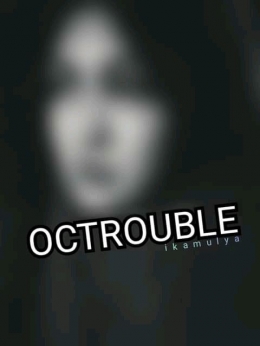Ya, Kinanti lantas pergi dari rumah seperti keluarnya upik abu dari neraka. Tidak ada dokumen penting dan barang berharga yang dia bawa. Hanya ada segenggam recehan untuk membayar angkot di kantung bajunya yang lusuh. Jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan sisa-sisa harapan.
Perempuan pecandu hujan ini menunda kepulangannya ke rumah orang tua demi menemuiku di kedai kopi seberang kantor lebih dulu. Tangan dan wajah Kinanti lebam-lebam. Entah bagian tubuh lain. Yang jelas, bercak darah masih tersisa di sudut kiri bibir. Sorot matanya sore itu menceritakan semua tentang pedih perih tanpa kata-kata.
"Wisnu ...."
"Ya."
"Kau ingat, berapa lama perjuanganku untuk sembuh dari semua trauma?"
"Tiga tahun."
"Bukankah itu lama?"
"Waktu yang lama dan sangat menyiksa."
Kinanti diam saja.
Aku menduga dia sedang teringat awal kebangkitannya. Momentum dia mampu keluar dari kehidupan yang hanya berputar-putar di ruang belajar dan setumpuk novel misteri. Fase di mana perempuan cantik ini bisa kembali tersenyum manis dan terbahak tanpa pura-pura.
"Kupikir, aku sudah mampu melindungi diri dari tipu daya cinta. Nyatanya ...."