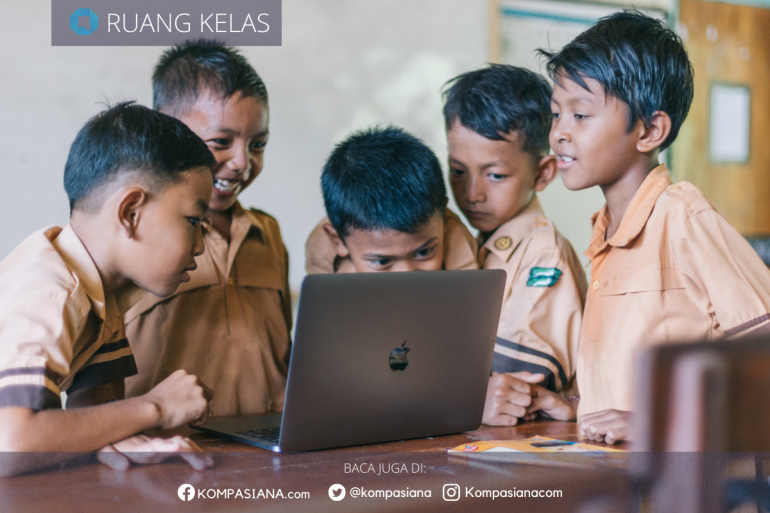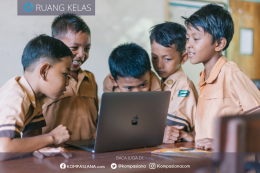Sesuai dengan ketentuan yang membahas tentang status anak diluar perkawinan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya," begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 yang berbunyi: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya," maka ketentuan pencatatan akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut telah benar.
Namun demikian, di dalam praktik yang dijumpai sebagian besar hakim di lingkungan Pengadilan Agama cenderung kepada dua hal dalam menangani perkara permohonan pengakuan anak dalam mana anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan: 1) apabila anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut sebagai akibat perkawinan siri kedua orang tuanya, maka akan dikabulkan; 2) apabila anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut sebagai akibat kumpul kebo kedua orang tuanya, maka akan ditolak.
Sebagian besar pertimbangan hukum yang mendasari penolakan terhadap permohonan pengakuan anak di luar perkawinan tersebut adalah pendapat bahwa anak zina tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologis anak tersebut.
Hukum Peradata Islam kontemporer juga membahas kerancuan istilah poligami. Istilah poligami terdiri dari kata poli yang berarti banyak, dan gami yang berarti perkawinan. Yang pertama disebut poligini, dan yang kedua disebut poliandri. Dalam hal ini, istilah yang tepat untuk menyebut perkawinan dalam mana seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang perempuan pada saat yang bersamaan adalah poligini, dan bukan poligami. Hukum positif di Indonesia memberikan izin poligini bagi seorang suami dengan alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan (UU No.1 tahun 1974, pasal 4 ayat 2; Kompilasi Hukum Islam pasal 57).
Hal lain yang dibahas dalam perkembangan hukum perdata islam adalah harta bersama. Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-istri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Hukum adat juga mengatur pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat kematian salah satu pihak atau akibat perceraian.
Tetapi, dalam hal sudah tersedia secara pantas sejumlah harta yang diambilkan dari harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya, maka kelebihannya dapat dibagi oleh ahli waris. Kalau terdapat anak, maka anak itulah yang menerima bagiannya sebagai barang asal. Kalau tidak ada anak, maka sesudah kematian suami atau istri yang hidup lebih lama, harta bersama tersebut harus dibagi antara kerabat suami dan kerabat istri menurut ukuran pembagian yang sama dengan ukuran pembagian yang digunakan suami istri seandainya mereka masih hidup serta membagi harta bersama tersebut. Sedangkan dalam hukum Positif, ada beberapa pasal yang membahas mengenai pembagian harta bersama, seperti; Pasal 35-37 Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991),
Itsbat pengangkatan anak juga dibahas dalam penerapan Hukum Perdata Islam kontemporer. Pengangkatan anak dalam istilah hukum perdata barat disebut adopsi. Sumber hukum adopsi adalah Staatsblad tahun 1917 No. 129 tanggal 29 Maret 1917. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan orang-orang islam dalam perkembangannya diatur alam perkara itsbat (pengesahan) pengangkatan anak dalam UU No.3 Tahun 2006.
Selanjutnya mengenai ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 adalah sebagai berikut: (1) Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
Pendekatan kontemporer terhadpa hukum islam juga membahas kerancuan Putusan Perceraian Pengadilan Agama. Di lingkungan Peradilan Agama, perkara perceraian dibedakan menjadi permohonan cerai talak, yaitu permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami, dan cerai gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Meski kedua perkara perceraian tersebut merupakan perkara contentious (sengketa), tetapi putusan atas keduanya berbeda. Yang pertama hakim hanya sebatas memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak kepada istri, dan yang kedua hakim menjatuhkan talak suami kepada istri.
Perbedaan putusan atas kedua perkara perceraian tersebut telah menimbulkan implikasi hukum acara yang berbeda dengan yang berlaku dalam perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum. Pencabutan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Prosedur pencabutan gugatan perceraian di Pengadilan Agama belum diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989. Jika merujuk pada Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, maka prosedur pencabutan gugatan yang berlaku mengikuti hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Rv. Persoalan yang muncul kemudian adalah apakah ketentuan Pasal 271 Rv dapat diterapkan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama?
Jika mengacu pada Pasal 271 Rv, maka hakim harus menolak permohonan pencabutan dan meneruskan pemeriksaan perkara tersebut secara tuntas. Untuk mengatasi kerancuan terhadap pasal tersebut, beberapa alternatif yang dapat digunakan: pertama, tidak perlu ada izin tergugat atau termohon dalam pencabutan perkara perceraian. Dengan dengan demikian, kapanpun penggugat mengajukan permohonan pencabutan perceraian, maka permohonan pencabutan perceraian harus dikabulkan tanpa perlu izin tergugat.