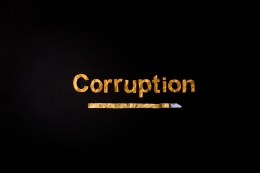Para koruptor sering beraksi dengan cara yang halus hingga membuat publik (nyaris) tidak menyadarinya. Mereka tampak tidak menyalahi segala hukum formal karena semua itu seolah memang dirancang untuk membenarkan tindakannya.
Meskipun dua tahun belakangan merupakan masa yang sulit, tindakan korupsi sama sekali tidak surut. Justru, keputusasaan dalam masa krisis dimanfaatkan untuk menghipnotis rakyat dengan sekelumit kisah heroik.
Mereka datang memberi paket bantuan bagaikan malaikat pelipur lara, tetapi pihak yang menerima kiranya tidak pernah tahu bahwa hak pribadinya telah dipangkas sepuluh ribu rupiah. Tampaknya Robin Hood dalam wujudnya yang lain telah muncul dengan mengejutkan.
Tindakan korupsi dianggap sebagai keputusan yang wajar mengingat betapa besarnya "biaya kampanye", dan semua kengerian tentangnya hampir dicabut oleh dogma yang semena-mena. Ironisnya, kejahatan korupsi tidak lagi menakutkan untuk dilakukan.
Korupsi menjadi sebentuk hegemoni yang dilihat sebagai sesuatu yang biasa, dan malahan dianggap wajar serta bernilai baik. Inilah yang kemudian disebut dengan banalitas kejahatan oleh Hannah Arendt.
Pada tahun 1961, Arendt melaporkan untuk The New Yorker tentang pengadilan kejahatan perang yang dilakukan Adolph Eichmann, seorang operator Nazi yang bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan jutaan orang Yahudi ke berbagai kamp konsentrasi.
Dalam laporannya, Arendt menganggap Eichmann sebagai seorang birokrat biasa, agak hambar, serta kata-katanya selalu berulang yang tidak terkesan sesat atau sadis dan justru terkesan begitu normal.
Eichmann bertindak tanpa motif apa pun selain mematuhi perintah otoritas dan memajukan kariernya di partai Nazi. Menurut Arendt, dia melakukan perbuatan jahat tanpa niat jahat; sebuah kesimpulan yang aneh mengingat kenyataan tindakan jahatnya yang begitu bengis.
Kasus Eichmann mengingatkan saya pada tokoh utama dalam novel Albert Camus, The Stranger (terj. Orang Asing), yang secara acak dan hampir tanpa kesadaran membunuh seorang pria di tepi pantai, tetapi kemudian setelah itu merasa tidak menyesal.
Tidak ada niat khusus atau motif jahat yang jelas: tragedi itu "terjadi" begitu saja.
Hemat saya, fenomena korupsi di Indonesia telah mencapai tahap banalitas yang mana kebiadaban semacam itu tidak lagi dianggap sebagai kejahatan, melainkan sesuatu yang lumrah dan malah merugikan bila tidak dilakukan.
Pada akhirnya, kita mendapati para koruptor tidak menyesali perbuatannya dan malah tetap mampu tersenyum (bahkan tertawa) di depan publik, seakan apa yang mereka lakukan merupakan suatu kebanggaan betapa mereka telah berani menerobos rambu-rambu konstitusi dan bahwa pihak-pihak fundamental ada dalam "kantong saku" mereka.
Ketika korupsi mencapai tahap banalitas, maka nilai baik dan buruk menjadi tiada bedanya.
Apa yang mungkin tidak kita sadari adalah, banalitas kejahatan dalam wujudnya yang sederhana kerap kali menjadi keseharian kita, bahkan beberapa di antaranya sering dilakukan sejak kecil.
Semasa sekolah, barangkali Anda lebih memilih menulis contekan daripada belajar giat dalam menghadapi ujian. Atau ketika Anda dikenai surat tilang, Anda bernegosiasi dengan petugas yang bersangkutan dan memberinya beberapa lembar uang.
Dalam dunia kepenulisan, kita melihat plagiarisme tumbuh subur seperti jamur di musim hujan. Bahkan di dunia akademik, "korupsi gagasan" juga sering terjadi, entah di tingkat menengah maupun tingkat tinggi.
Semua itu merupakan contoh banalitas kejahatan yang banyak terjadi di sekitar kita. Namun yang lebih ironisnya lagi adalah, mungkin kitalah pelakunya tanpa disadari.
Menilik kebiasaan tersebut yang nyaris sudah mengakar dalam masyarakat, mungkinkah korupsi juga menjadi semacam budaya? Itu adalah tesis yang menarik, tetapi dalam artikel ini, pertanyaan mendasar saya adalah, "Dari mana banalitas korupsi muncul?"
Kesenangan Destruktif
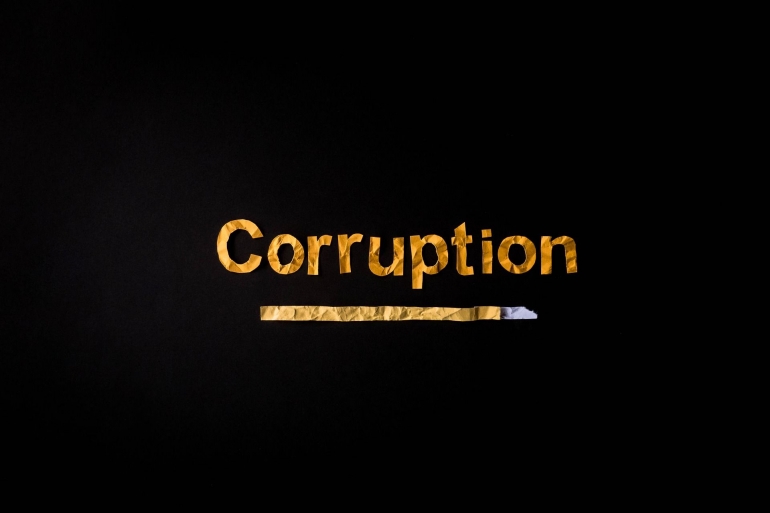
Manusia adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari kodrat hewaninya untuk mencari kenikmatan di dalam hidupnya. Ketika moralitas dalam diri seseorang telah "mati", maka saat itu pula dia tengah kembali menuju nilai terendahnya sebagai manusia.
Kecerdasan tanpa kepekaan moral hanyalah potensi untuk menjadi kejam tanpa merasa bersalah, pun moral tanpa pengetahuan bagaikan induk gajah yang memberi makan anaknya seekor kobra.
Seperti yang pernah ditanyakan oleh Elias Canetti, "Apa artinya menjadi manusia di tengah-tengah keniscayaan naluri rimbanya?"
Terkikisnya nilai-nilai moral dapat membuat seseorang terjebak dalam keabu-abuan antara apa yang baik dan apa yang benar. Koruptor bukan hanya merasionalisasi kejahatannya sebagai "benar", tetapi mereka juga menukar nilai "buruk" menjadi "baik" akibat defisitnya moralitas.
Padahal moralitas adalah kompas dalam diri manusia yang mengarahkannya pada kelembutan tata hidup bersama.
Dan tanpa kemampuan untuk membuat pertimbangan akan nilai-nilai, untuk membedakan mana yang baik di antara hal-hal yang buruk, tidak peduli seberapa cerdasnya seseorang, koruptor telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri.
Betapa pun mereka tahu bahwa korupsi itu termasuk kejahatan besar, tanpa pengendalian diri, mereka mengabaikan label "kejahatan" dan tetap melakukannya dengan sukaria.
Bengkoknya nilai-nilai pribadi dapat menggerus rasa empati mereka ke dalam kuburan jiwa yang hampa. Nurani mereka seakan beku dan tidak bisa lagi menyerap penderitaan orang lain.
Tidak adanya kepedulian dan pengertian terhadap penderitaan rakyat membuat koruptor dapat merasionalisasi kejahatannya.
Pemikiran mereka bekerja otomatis mencari kambing hitam atas perbuatannya, dan lalu merasa telah "bercuci tangan" tidak peduli seberapa besarnya kebengisan mereka.
Bagaimanapun juga, mereka mendistorsi persepsi realitas bahwa kesenangan berada di atas segala-galanya, sama seperti hewan yang tingkah lakunya (selalu) mengarah pada kenikmatan yang dangkal dan tanpa pertimbangan.
Pada titik ini, koruptor adalah manusia yang belum juga beranjak dari kodrat hewaninya yang sedemikian brutal dan merusak.
Friedrich Nietzsche percaya bahwa hakikat dari manusia adalah kehendak untuk berkuasa. Ketika dunia terdalam manusia dan dunia sosialnya berbenturan, maka muncullah kejahatan besar seperti korupsi.
Kebutuhan ego dituntut oleh kondisi eksternalnya, sebab manusia pun membutuhkan pengakuan, kehormatan, dan tepuk tangan yang meriah untuk dirinya.
Tetapi para koruptor adalah orang-orang yang secara keliru menukar kesejatian hidup demi beberapa kesenangan yang dangkal. Mereka menyingkirkan keindahan hidup oleh rayuan fatamorgana bagaikan pengembara gurun yang tertipu oleh bayang-bayang oase.
Inilah yang jarang dibahas oleh publik bahwa korupsi, jika ditilik secara mendalam, kerap berakar pada nihilisme yang amat halus dan tidak disadari, tapi cukup untuk menyetir kesadaran pelaku.
Diakui ataupun tidak, korupsi merupakan jalan instan dan nyaman menuju hedonisme selama perjalanan tersebut berlangsung senyap. Pengejaran akan kenikmatan terdengar mengagumkan, barangkali karena memang itulah sifat alamiah dari manusia.
Namun, gaya hidup hedonis yang ditempuh oleh koruptor adalah murni berkonotasi negatif, sebab mereka berusaha menggapai kebahagiaannya dengan mengorbankan pihak lain bagaikan menanam anggur di ladang yang bukan miliknya.
Hal ini senada dengan pemikiran Francois de Sade bahwa kenikmatan tertinggi kerap identik dengan penyimpangan dan kejahatan. Baginya, kenikmatan puncak adalah suatu kenikmatan yang menyimpang (perverse pleasure), atau kenikmatan yang gila (crazy pleasure).
Korupsi merujuk pada kesenangan yang lahir dari adanya kenestapaan di pihak rakyat.
Saya menyebutnya dengan "Kesenangan Destruktif", yaitu upaya mencapai kesenangan melalui penghancuran pada sesuatu di luar diri sendiri sehingga terjadi barter antara kegembiraan dan rasa sakit di pihak lain.
Korupsi adalah bentuk konkret dari perburuan kesenangan tanpa batas yang dilakukan manusia dengan selalu diselubungi oleh kemunafikan penampilan dan pencitraan.
Dengan kata lain, kecenderungan bersikap korup sudah tertanam di dalam hasrat manusia untuk merenggut kesenangan yang tanpa batas, dan sikap mendua atas kesenangan itu sendiri bahwa manusia selalu malu atas dorongan-dorongan perburuan kesenangan yang ada dalam dirinya, lantas mereka secara diam-diam menjadikannya sebagai bagian dari kesehariannya.
Selama ini kita selalu memaki para koruptor, namun sesekali kita perlu memahami mereka karena bagaimanapun juga, mereka meniti kehancurannya dengan berjalan menuju ngarai gelap yang dibuatnya sendiri lewat korupsi.
Hedonisme yang tanpa batas bukanlah jalan keluar yang kita maksudkan, sebab pengejaran semacam itu hanyalah cara berlari dari ketidakpuasan menuju ketidakpuasan lainnya sepanjang waktu.
Mereka seperti terjebak dalam labirin tanpa garis akhir, dan karenanya sedari awal mereka sudah memilih arena permainan yang keliru.
Jadi selamat datang di lingkaran setan: mereka berangkat dari kehampaan menuju kelimpahan dunia, tetapi nyatanya mereka hanya berputar-putar dan selalu kembali ke tempat yang sama di mana mereka memulai.
Psikolog menyebutnya sebagai "Hedonic Treadmill". Idenya adalah ke mana pun mereka berlari mengejar kebahagiaan, sesungguhnya mereka tidak beranjak sama sekali akibat pengejaran kenikmatan yang tiada akhir.
Manusia adalah makhluk pemburu segalanya dan acapkali tidak peduli dengan konsekuensi dari perburuannya. Para koruptor terbukti tidak berdaya dalam memproyeksikan masa depannya. Imajinasi mereka sudah "mati".
Mereka mengabaikan sesuatu yang belum ada, padahal mungkin saja sesuatu itu mengguncang mereka tanpa aba-aba. Dan kenyataannya memang demikian. Para koruptor terdampar pada pulau buatannya sendiri yang memerangkap dirinya dalam disposisi naif.
Sekarang kita tahu bahwa sebenarnya kita tidak kekurangan politisi ataupun orang yang ingin mengemban amanah publik.
Hanya saja, sedikit dari mereka yang menjangkau kiprahnya sampai pada wilayah makna, dan bahwa dedikasinya untuk menyumbangkan harapan pada sesama tampak kurang disadari.
Selama ini citra politik di masyarakat sudah "kotor", dan orang-orang yang masuk ke dalamnya (kebanyakan) malah semakin memperburuk paradigma tersebut. Korupsi menjadikan tata politik sekadar menjadi sekumpulan kisah buruk dari pertikaian antar elite.
Mereka kerap berakhir dalam drama kenaifan, sebab politik pun tidak dijadikan sebagai teater refleksif. Kemiskinan etika politik banyak tumpang-tindih dengan ambisi politik. Orang tidak lagi datang dengan visi yang mendalam, tetapi dengan uang yang banyak.
Pemberantasan korupsi melalui pendekatan normatif tampaknya tidak begitu efektif, sebab hingga sekarang pun (yang konon katanya dibangun dengan demokratis dan manusiawi) tetap menjamur kasus korupsi.
Partai politik sebagai penjaga gerbang demokrasi juga nyaris tiada bedanya di mana masing-masing dari mereka tetap mengutamakan kepentingannya sendiri. "Wasit" demokrasi banyak ditangkap, dilemahkan, bahkan dibeli untuk mengubah aturan permainan.
Kini waktunya kita menelusuri kedalaman manusia dan membenahinya dari sana. Satu keniscayaan umum yang berlaku di negara-negara demokrasi adalah membuka pintu terhadap orang-orang korup untuk memperoleh kursi kehormatan.
Karena demokrasi menjunjung elektabilitas dan bukannya intelektualitas, maka kita sering terpedaya untuk membiarkan mereka yang sedari awal sudah berniat korupsi.
Memang tidak demokratis jika kita mencabut hak politik seseorang, maka konsekuensinya kita mesti bisa menilai calon-calon penguasa dari kedalamannya dan bukannya dari kekayaan atau gelar akademik semata.
Kita mesti melampaui fenomena fisik dan mulai melihat sisi terdalam manusia; sesuatu yang tidak tampak oleh mata visual. Sekurang-kurangnya, kita mesti mampu mendeteksi orang-orang semacam Eichmann dalam panggung kekuasaan.
Banalitas kejahatan tampaknya bukan hanya terjadi pada diri koruptor. Ironisnya, kebanyakan dari kita juga mulai terbiasa dengan berita-berita korupsi sehingga tidak memedulikannya lebih jauh.
Situasi semacam itulah yang berbahaya, sebab jika kedua pihak saling membuang muka, maka kebatilan seperti korupsi tidak akan pernah terselesaikan. Idealnya adalah, pihak penguasa menyadari tanggung jawabnya dan selain dari mereka bertugas mengawasi kekuasaan.
Jika kita mendefinisikan ulang pejabat sebagai orang yang cakap berpikir, berbicara, dan bertindak tanpa mengabaikan etika perihal tata hidup bersama, pantaskah koruptor disebut sebagai (mantan) pejabat? Standarisasi itulah yang tidak kita miliki.
Mengingat semakin mudahnya melumpuhkan pihak oposisi, pendekatan normatif perlu didorong oleh pendekatan lain. Alternatif terbaik yang kita miliki adalah membangun jiwa bangsa yang mampu mengurai makna kebersamaan dan hadir lebih dekat dengan transedensi yang lebih agung daripada kita.
Menanamkan moralitas pada nurani manusia bukanlah pekerjaan mudah, namun dengan segala sarana yang kita miliki saat ini, semuanya begitu mungkin dan terbuka.
Siapa pun yang mengaku sebagai warga negara berkewajiban untuk menjadi penjaga gerbang demokrasi, sebab hanya dengan demikianlah, setiap orang dapat menjaga dirinya sendiri dari banalitas kejahatan.
Nilai kesejatian manusia tidak diukur dari derajat kehormatannya, melainkan dari derajat moralitasnya di hadapan kosmos yang memesona dan mengagumkan ini. Kita mesti menjadi manusia yang utuh di tengah dunia yang tampaknya akan runtuh.
Dan jujur saja, saya mulai kedinginan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H