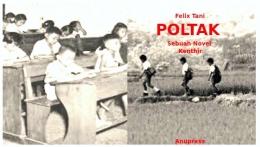Berta berlari ketakutan, menjemba Poltak. Tapi Poltak sudah lebih dulu menghindar, sambil berseru, "Kutipu kau!" Tergelak-gelak, senang, dia lari mendaki bukit.
"Poltak!" Berta mengejar, berteriak, sebal karena tertipu.
Bukit itu landai. Anak-anak Panatapan menamainya Dolok Haramonting. Banyak perdu keramunting tumbuh di situ. Poltak, Binsar, dan Bistok sering datang ke situ untuk sekadar memetik buahnya.
Berta, terengah, menyusul Poltak. Siap menggebuknya.
"Nah, ini untukmu. Sudah matang. Manis kali ini." Poltak mengangsurkan segenggam buah ranum keramunting yang baru di petiknya kepada Berta.
Aksi gebuk batal. Tersenyum, Berta menerima segenggam keramunting. Itu tanda maaf.
"Ih, enak. Manis kalipun." Berta menikmati sebuah keramunting merah ranum. Lalu sebuah lagi, dan sebuah lagi. Satu per satu sampai segenggam.
Pada sebuah gundukan tanah, di bawah naungan pohon tandiang, pakis raja, Poltak duduk menikmati buah keramunting. Berta merapat duduk di sisi kirinya. Berdua memandang ke timur, ke arah punuk-punuk biru punggung Bukit Barisan.
Di tengah padang sabana itu, Berta dan Poltak hadir sebagai keindahan kecil. Rok terusan merah muda Berta dan kemeja biru muda Poltak, di tengah hamparan hijau padang sabana, di bawah pohon tandiang, dengan latar punggung biru Bukit Barisan di kejauhan, adalah sebuah puisi alamiah. Indah, damai dan romantis.
"Itu, yang paling tinggi, gunung apa, Poltak?" Berta memecah keheningan. Menunjuk ke timur.