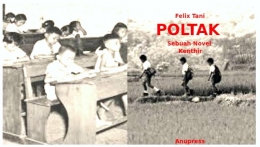Jarak antara suka dan duka rupanya hanya satu malam. Tak seorangpun pernah memberitahu Poltak hal itu. Andaikan ada yang mengingatkan, mungkin hatinya tak akan seluka dan seduka kini.
Di pucuk bukit Partalinsiran, Poltak duduk sendiri, sepi. Sepasang matanya menatap ke arah barat, ke ujung punggung sebuah bukit, yang terpenggal oleh jalan raya Trans-Sumatera. Di situ, di ujung punggung bukit, sebuah gundukan tanah merah mengunci tatapannya.
Seperti gambar hidup, terbayang pertemuan dengan kakeknya lima hari lalu di ruang rawat inap Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar. Kakeknya, neneknya, Parandum amangudanya, dan dirinya bahagia dalam senda-gurau.
"Kata dokter, tiga hari lagi ompung boleh pulang." Kakeknya meneruskan kabar gembira kepada Poltak.
"Ompung sudah sembuh?"
"Ompung merasa lebih sehat dari biasanya. Janji, ompung pulang tiga hari lagi."
Berempat mereka tertawa. Setiap orang yang dirawat di rumah sakit punya hanya satu harapan: sembuh lalu pulang ke rumah. Harapan itu tiga hari lagi akan menjadi kenyataan.
Tapi kenyataan lain datang sebelum harapan tiba. Sore hari Poltak dan neneknya tiba kembali di Panatapan. Besok harinya, pagi-pagi benar, seorang kerabat dari Siantar datang membawa kabar. "Ompu Poltak doli sudah dipanggil Tuhan. Beliau pulang ke rumah Panatapan siang ini."
Itulah petir terdahsyat di pagi hari untuk Poltak dan neneknya.
"Ompungni Poltak, kau jahat sekali. Janjimu, kau pulang tiga hari lagi. Kenapa kau pulang hari ini. Kau ingkar janji. Kau membohongi aku. Ompungni Poltak, siapalah nanti temanku mengolah sawah kita." Nenek Poltak memarahi kakek Poltak dalam ratap-tangis dukanya.
Poltak merasa kakinya hilang pijakan. Dia terduduk di teras rumah. Diam seribu bahasa. Wajahnya mendung, bingung. Tubuhnya mematung. Hanya air mata yang mengalir deras di kedua pipinya.
"Aku mau ompungku pulang. Tapi tidak seperti ini. Pulang tanpa nafas," ratap Poltak dalam hatinya yang terluka, sangat duka.
Suatu ketika, saat Misa hari Minggu di Gereja Katolik Aeknatio, pastor berkotbah, "Tuhan akan mengambil kembali jiwa kita pada waktu yang seorang pun tak pernah tahu. Karena itu setiap orang harus selalu menyiapkan hatinya."
Poltak sungguh tak paham makna kotbah itu. Tapi dia tahu, Tuhan telah mengambil nyawa kakeknya, seperti seorang pencuri di tengah malam. Saat dia terbangun di pagi hari, kakeknya sudah tiada. Kehilangan itu terjadi hanya selang satu malam.
Kematian kakek Poltak adalah misteri yang disederhanakan. Menurut Parandum, malam setelah Poltak dan neneknya kembali ke Panatapan, mendadak kakek Poltak berbatuk tanpa henti, hingga kepayahan, lalu tak sadarkan diri. Subuh hari, dokter memberitahu, kehendak Tuhan tidak dapat ditolak, kakek Poltak sudah pergi dalam damai.
Tonggoraja, rapat raja-raja adat, memutuskan kakek Poltak berpulang sari matua. Dua dari tiga orang anaknya, anak pertama Amani Poltak dan anak kedua Nai Rumiris, sudah berkeluarga dan memberinya cucu. Tinggal Parandum, anak bungsu, yang belum menikah.
Adat sarimatua dijalankan. Rangkaian upacara adat itu berlabgsung tiga hari dua malam. Seluruh unsur kerabat Dalihan na Tolu, yaitu hula-hula, dongantubu, dan boru harus lengkap hadir.
Parjambaron, pengakuan eksistensi dan hak adat setiap unsur kerabat, disimbolkan dengan penyerahan bagian-bagian tubuh ternak, wajib hukumnya dijalankan. Untuk itu disembelihlah seekor namanggagat, kerbau dan beberapa ekor pinahan lobu, babi.
Seluruh anggota kerabat luas kakek Poltak, sebagai suhut bolon, tuan rumah utama, hadir lengkap. Bagi Poltak, kehadiran kerabat luas itu, kakek-nenek buyutnya dan adik-adik kakeknya, seperti mengulang peristiwa adat manulangi, memberi makan kakek-nenek buyutnya dulu.
Tapi suasananya tidak seperti itu. Manulangi adalah peristiwa syukur, peristiwa gembira. Sarimatua adalah peristiwa sedih yang diberi makna syukur. Sebab mendiang telah pergi setelah menunaikan hampir seluruh kewajiban sosialnya sebagai orangtua.
"Poltak. Ke sini kau, amang," kakek buyutnya memanggil Poltak ke sisinya, di samping peti jenazah kakeknya, tepat di tengah halaman rumah. Poltak beringsut merapat.
"Kau cucu laki pertama dalam keluarga. Kau harus bantu bapakmu memikul sisa tanggungjawab yang ditinggalkan kakekmu." Kakek buyutnya memberi pesan. Suaranya pelan, tegas, tapi nadanya tak bisa menutupi rasa duka.
Tidak ada yang lebih menyedihkan bagi orangtua, selain didahului darah-dagingnya menghadap Yang Maha Kuasa. Ada perasaan gagal, sekaligus perasaan tak diberi kepercayaan oleh Tuhan, sebagai orangtua.
"Harusnya, aku dulu yang mati, amang. Bukan kakekmu itu." Kakek buyut Poltak menggumam. Seolah bicara kepada dirinya sendiri. Setelah menerima adat manulangi, dia udah siap setiap saat dipanggil Tuhan.
Matahari sore sudah jauh condong ke barat. Tatapan Poltak masih lekat pada gundukan tanah merah di ujung punggung bukit. Gundukan itu berundak setingkat. Di atasnya ditanam sebatang beringin.
Itulah makam orangtua yang sarimatua. Makam kakek Poltak sendiri. Undakan satu tingkat itu pertanda mendiang sudah bercucu.
Upacara adat pemakaman telah usai sehari yang lalu. Kerabat jauh sudah pulang ke kampung atau kotanya. Tinggal kerabat dekat, adik-adik kandung kakek Poltak. Mereka masih menemani nenek Poltak, menghibur, dan menguatkan jiwanya. Tidak mudah menerima kenyataan menjanda di hari tua.
Kenangan indah bersama kakeknya bersiliweran di kepala Poltak. Belajar naik sepeda, minum teh manis di kedai, menghalau burung pipit, memanen padi, mengurus kerbau, memerah susu kerbau, memancing ikan di tebat, dan menghadiri pesta adat. Semua itu indah. Tak akan pernah terjadi lagi.
"Ompung,'' bisik Poltak, memanggil kakeknya yang terbaring di bawah pusara, jauh di sana, di punggung bukit. Tak sadar, kedua pipinya terasa hangat. Ada air mata mengalir di situ.
Tak sengaja, Poltak merogoh saku celananya. Jemarinya menyentuh sesuatu berupa kertas. Poltak menggenggam dan mengeluarkannya dari saku celana.
"Ah, uang," gumam Poltak. Di genggamannya bergulung sejumlah lembaran uang pecahan serupiah, seringgit, lima rupiah, dan sepuluh rupiah.
Itu uang pemberian para kakek-neneknya, serta dari beberapa orang amanguda dan namborunya. Sebagai simbol penghiburan dan penguatan untuk jiwa Poltak.
"Tujupuluh ribu rupiah." Poltak membatin setelah menghitung jumlah uang pemberian kerabatnya itu.
"Oi, Poltak! Banyak kalilah uangmu itu! Bagi-bagilah!"
Poltak tersentak berdiri, kaget diteriaki Binsar yang, tanpa disadarinya, sudah berada di belakangnya bersama Bistok.
"Bah, puang. Beruntung kalilah kau, Poltak, punya kakek. Dapat uang kau." Bistok seakan iri.
"Kalau kakekmu meninggal berkali-kali, bisa dapat duit lebih banyak lagi kau." Binsar menambahkan, tanpa tenggang rasa.
Hati Poltak mendadak palak. "Aku mau kakekku meninggal sekali saja! Tapi bukan sekarang!" teriaknya. Emosinya meledak.
"Kalian berdua! Babi!" Poltak meraih potongan batang daun enau, bekas kereta luncur, yang tergeletak dekat kakinya. Naik pitam, ditebaskannya batang itu ke arah kepala Binsar dan Bistok. (Bersambung)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H