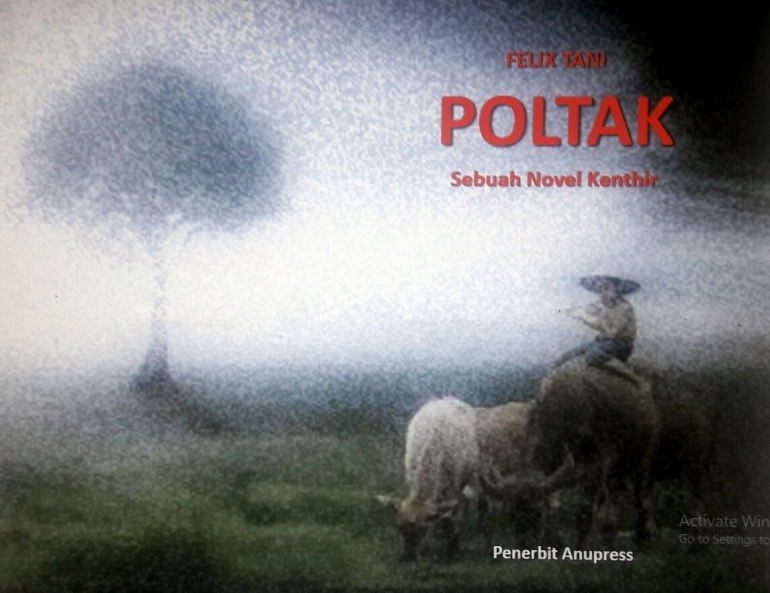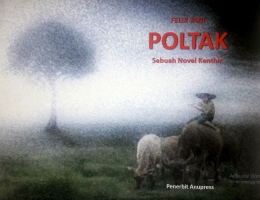"Banyak kalilah uangmu, Poltak." Kakek Poltak nomor dua, bapak Si Binsar, menyanjung. "Ini, Ompung tambah serupiah. Nah, kaya raya kayu sekarang." Poltak menerima dengan gembira, "Mauliate, Ompung."
Kekayaan Poltak kini membengkak menjadi enam rupiah. Luar biasa. Dia percaya kata-kata kakeknya. Dirinya kaya raya kini. Mendadak.
Kakek nomor dua itu, walau tetangga rumah di Panatapan, baru kali ini memberi uang kepada Poltak. Tak mau kalah pamor dia dari adik-adiknya yang datang dari Sumatera Timur itu. Begitulah cara para kakek bersaing mengasihi cucunya.
Sebagai cicit sulung buyutnya, status Poltak memang istimewa. Sama seperti status bapaknya, cucu pertama untuk buyutnya. Mereka adalah penerus pertama garis darah keluarga. Karena itu namanya akan selalu disebut.
Terlebih dalam adat manulangi. Poltak dan bapaknya wajib hadir. Anak pertama, cucu pertama, dan cicit pertama adalah penanda hagabeon, keturunan yang besar, dan hasangapon, kemuliaan.
Malam cepat tiba di Hutabolon. Lampu petromaks dinyalakan. Memberi terang, juga kehangatan di tengah kepungan dingin udara malam.
Semua orang siap dengan sarung dan selimut. Perlengkapan wajib untuk tidur di kampung pengunungan.
"Poltak, sini ompung simpan uangmu. Biar tak hilang." Nenek Poltak menawarkan jasa simpan duit.
"Tidak, Ompung. Aku kantongi saja." Poltak menolak. Enam lembaran merah mata uang serupiahan itu dilipat dan disimpannya di saku baju.
Melihat uang merah di dalam saku, meraba dan merasakan tekstur kertasnya, adalah kenikmatan tersendiri. Takada anak kecil yang bisa merasakan itu di Panatapan dan Hutabolon. Hanya Poltak.
"Ya, sudah. Jangan menangis kalau uangmu hilang." Nenek Poltak mengingatkan. Seolah sudah tahu apa yang akan terjadi.