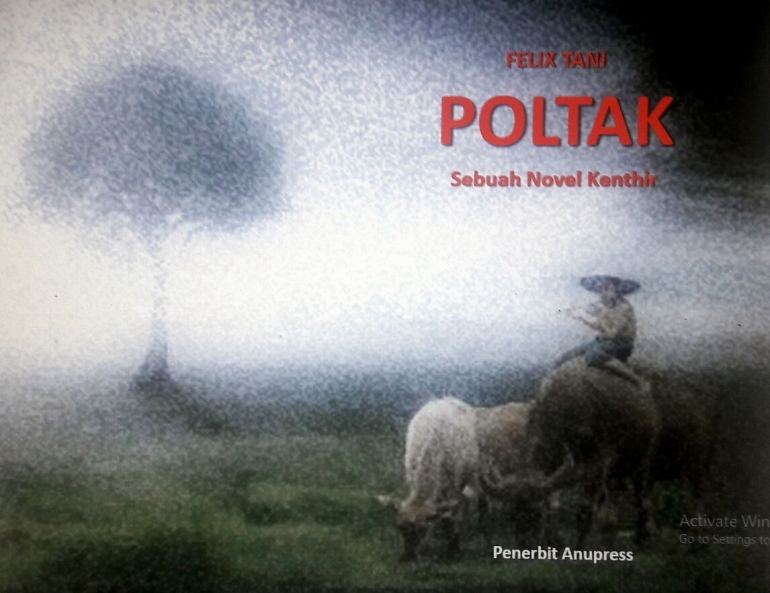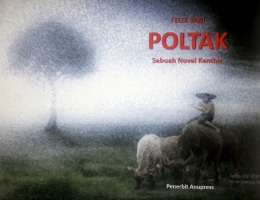Tiap-tiap celaka ada faedahnya. Pepatah Melayu itu ada benarnya. Setidaknya bagi Poltak, dalam peristiwa kecelakaan gula tarik di Hutabolon, kampung buyutnya. Kecelakaan itu sukses mencabut gigi serinya yang goyah.
"Lain kali, kalau gigimu goyah, cabut pakai gula tarik saja." Kakeknya menyarankan solusi gigi goyah. "Jangan rintik kau!" sergah neneknya, mengatai suaminya rintik, sinting. Kemesraan a'la kakek-nenek.
Tapi, sebesar-besarnya faedah celaka, mustahillah melebihi berkah. Karena itu, dalam doa kepada Debata Mulajadi Nabolon, orang Batak selalu memohon berkah, bukan celaka.
Berkah Mulajadi Nabolon diyakini mengalir dari hula-hula, leluhur, kakek-nenek, dan orangtua. Hukumnya, angin menyongsong hujan, kebaikan menjemput berkah. Perbuatan baik kepada mereka akan diganjar berkah berlipat-ganda.
"Poltak, besok kita panen di sawah. Pergilah, beritahu bapak dan ibumu di Robean. Mereka harus ikut panen besok." Kakek Poltak memberi amanat.
"Iya, Ompung!" Poltak segera berlari menuju Robean. Tidak ada pikiran lain di kepalanya, kecuali kenikmatan gulai ayam esok hari. Ya, gulai ayam.
Tradisi di Panatapan, kegiatan panen padi, juga saat tanam, dilakukan secara marsiadapari, tolong-menolong bergilir dari satu ke lain sawah warga. Kelazimannya, pemilik sawah memotong seekor ayam untuk lauk makan bersama di sawah.
Esok tiba. Matahari pagi mengintip dari balik gunung Simanukmanuk. Kakek-nenek Poltak, ayah-ibunya, Parandum, sejumlah warga Panatapan, serta Poltak sendiri, sudah berkumpul di sawah. Suasana gembira, penuh canda dan tawa.
"Amani Poltak, Nai Poltak, dan kau Poltak, cucuku. Aku mau menyampaikan satu hal penting. Kalian dengarlah baik-baik." Kakek Poltak memutus canda-tawa.
"Kalian lihatlah sawah di atas sana," Kakek Poltak menunjuk ke arah utara. Persisnya ke bagian sawah yang berada di hulu, tepat di bawah pintu masuk air irigasi. Itu bidang sawah terbaik.
Padi sawah di situ tumbuh lebih subur karena cukup air. Malainya panjang, bulirnya kuning bernas. Berkilauan ditimpa sinar matahari pagi, lsksana hamparan butiran emas.
"Sawah itu, pada hari ini, kami berikan kepada Poltak, cucu pertama dari anak sulung kami, sebagai dondon tua. Semua yang hadir di sini menjadi saksi."
Suasana hening. Penyampaian dondon tua, limpahan berkah untuk cucu pertama, itu terasa dramatis ketika dilakukan di tengah hamparan padi menguning. Tidak ada suara. Tapi semua wajah tersenyum. Gembira atas limpahan berkah untuk Poltak.
Pemberian sawah dondon tua adalah kelaziman adat Batak. Melalui pemberian itu, Poltak diharapkan mewarisi wibawa, keutamaan, dan rejeki kakeknya. Sehingga langkahnya ke depan tiada halangan dan hidupnya kelak tiada kekurangan.
Itulah keistimewaan cucu tersulung dalam keluarga Batak. Keistimewaan Poltak pula. Kini dia satu-satunya anak kecil yang punya sebidang sawah di Panatapan. Binsar tidak, Bistok juga tidak.
"Poltak! Kau ke sanalah. Berjalanlah mengelilingi sawahmu itu," perintah kakeknya. Poltak segera berlari cepat meniti pematang.
"Mulai dari pematang kelima dari atas!" kakeknya memberi petunjuk. Poltak mengayunkan langkahnya dengan cepat di atas pematang, mengitari bidang sawah dondon tua itu.
"Nah, selesai. Sah, itu sawahmu, Poltak, cucuku!" teriak kakeknya lagi, setelah Poltak selesai memutari areal sawah itu. Kira-kira seperempat hektar luasnya.
Kini berlakulah hukum adat paruma tano paruma gogo atas sebidang sawah dondon tua itu. Poltak adalah paruma tano, pemilik tanah sawah. Sedangkan kakek-neneknya adalah paruma gogo, pemilik padi hasil sawah itu, sepanjang sisa usia mereka.
"Terimakasih banyak, Ompung, atas pemberian ini. Semoga menjadi berkah untuk kita sekeluarga." Poltak tak perlu diajari untuk berterimakasih. Kata dan kalimat adat sudah tertanam dalam benaknya.
Kakek dan neneknya tersenyum bahagia sambil mengelus-elus kepala Poltak. Ayah dan ibunya tampak haru campur bangga. Berkah anak adalah karunia orangtua.
"Nah, Poltak. Sawah itu, kan, sekarang milikmu. Kau panen sendirilah sana. Nanti hasilnya kau angkutlah ke rumah Ompung," goda kakeknya.
"Hah! Matilah aku!" Poltak membelalak, disambut gelak-gelak tawa semua orang.
"Ayo. Kita mulai panen," aba-aba dari kakek Poltak. "Amani Poltak, Parandum dan kau Poltak, ayo kita mendirikan bantingan padi."
Teknologi bantingan padi itu dipelajari kakek Poltak dari kerabatnya yang tinggal di Sumatera Timur. Sebelumnya, perontokan gabah di Panatapan menggunakan teknik mardege, menginjak-injak malai padi. Risikonya, telapak kaki bisa tertusuk ekor gabah.
Teknologi bantingan memudahkan kerja perontokan padi. Malai padi cukup dibantingkan ke dasor bantingan, butir-butir gabah langsung rontok.
Tak perlu waktu lama untuk mendirikan kerangka bantingan itu. Komponen-komponennya sudah disiapkan: empat tiang, empat pasak pendek, empat pasak panjang, dan satu dasor -- papan bantingan. Tinggal dirakit, beres.
"Poltak, kau naiklah ke atas bantingan. Kita mau pasang tirai," perintah ayah Poltak.
Soal panjat-memanjat, Poltak hanya kalah dari tupai. Itu keahliannya. Dengan cepat dia memanjat tiang kerangka bantingan untuk naik ke atas.
Tapi, belum juga Poltak tiba di atas, mendadak kerangka bantingan itu bergerak hendak rubuh.
"Poltak! Awas!" Bapaknya berteriak mengingatkan. Sambil mencoba menahan tiang bantingan agar tidak sampai rubuh.
Yah, seperti sudah dikatakan, soal panjat-memanjat, Poltak hanya kalah dari tupai. Tapi bahkan seekor tupai pun sesekali jatuh juga karena salah hitung gravitasi. Jadi, adilkah menuntut Poltak untuk jangan sekali-kali jatuh? (Bersambung)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H