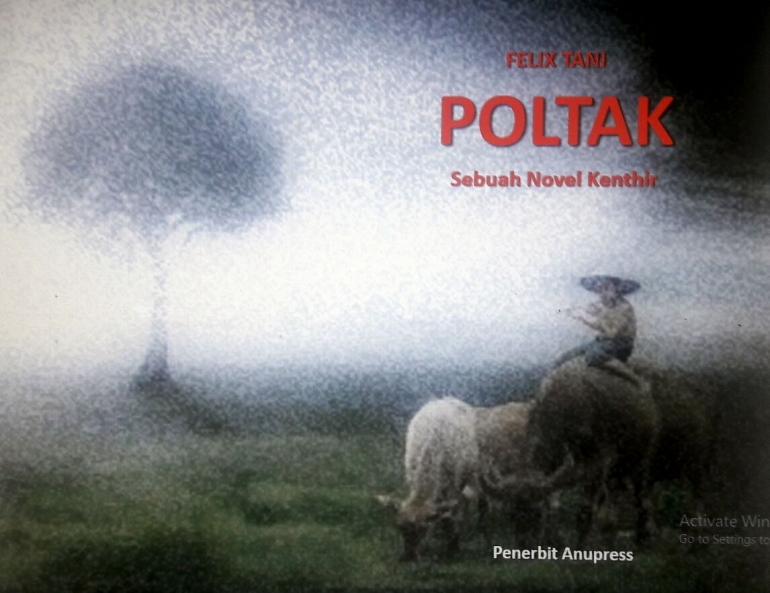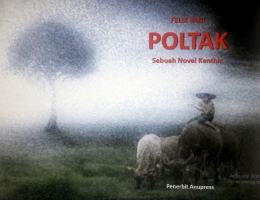Tuhan hadir dalam rupa langit biru, siang itu, di Panatapan. Bukan lantaran hari itu hari Minggu. Bukan. Tapi karena malam sebelumnya Tuhan telah hadir dalam rupa hujan lebat. Dia mencuci bersih awan di atas kampung.
Inilah dosa besar bagi anak-anak Panatapan: tidur siang di saat langit cerah. Sebab itu berarti menolak ajakan Tuhan untuk bermain. Tuhan berduka bila ditolak anak-anak, pemilik Kerajaan Surga itu.
"Poltak! Ayo, martalinsir!" Nyaring, teriakan Binsar mengajak Poltak martalinsir, main kereta luncur. Binsar, bersama Bistok, berdiri menunggu di halaman rumah Ompung Poltak, siap dengan kereta luncur masing-masing.
"Ayo! Sebentar, ya!" Poltak menyahut. Suaranya terdengar jauh di kebun belakang rumah.
Seperti biasa, dia sedang nangkring makan buah langsung di atas pohonnya. Kali ini pohon jeruk manis yang, entah kenapa, rasa buahnya selalu masam.
Di Panatapan, buah tidak disajikan di atas meja makan. Sebab keluarga-keluarga di sana tak satu pun punya meja makan. Mereka makan duduk meriung di lantai, beralaskan tikar mendong.
Lagi pula takada tradisi makan buah selepas makan siang atau malam di Panatapan. Karena itu, jika seorang anak ingin makan buah maka, seperti Poltak, dia harus cari sendiri di kebun. Selalu ada pisang, jambu air, nenas, jambu klutuk, terung Belanda, markisa atau pun jeruk di situ.
"Ini ada jeruk untuk kalian. Sebuah seorang." Poltak mengangsurkan jeruk kepada Binsar dan Bistok, sedetik setelah datang bergabung dengan kereta luncur di tangan.
Binsar dan Bistok segera mengupas dan melahap jeruk pemberian Poltak. Mereka sangat nenikmatinya, sekali pun harus dengan dahi mengerut dan mata mengerinyit. Sebab jeruk yang paling manis adalah pemberian tulus sahabat karib, semasam apa pun rasanya.
Beriringan, sambil berceloteh, tiga sekawan itu mendaki bukit Partalinsiran di utara kampung. Masing-masing memanggul kereta luncur di bahunya.
Kereta luncur itu asli mereka bikin sendiri. Dibuat dari batang daun enau. Dua potongan batang, masing-masing sepanjang satu meter, dijadikan sasis ganda bersenjang 40 sentimeter. Kedua ujung depannya dilancipkan. Di ujung depan sasis itu dipakukan melintang satu potongan untuk pijakan kaki. Lalu di bagian belakang dipakukan melintang empat potongan untuk dudukan pantat.
Remnya adalah tongkat kayu. Tongkat itu harus ditancapkan ke tanah, di antara selangkangan, untuk menghentikan laju kereta luncur.
Begitulah, anak-anak Panatapan harus kreatif menciptakan mainan sendiri. Alam menyediakan apa saja yang mereka perlukan. Tuhan mengaruniai mereka akal budi untuk berkreasi. Orangtua memberikan waktu untuk bermain. Sempurna.
Tiba di puncak bukit Partalinsiran, tiga sekawan itu bergabung dengan anak-anak lain yang lebih tua tiga empat tahun. Mereka sudah bermain lebih dulu di situ.
Kemiringan lereng bukit Partalinsiran, yang dijadikan lintasan seluncuran, itu kurang lebih 45 derajat. Jarak lintasan dari puncak ke kaki bukit kurang lebih 75 meter. Lumayan menantang untuk anak kecil.
"Ayo, Poltak! Giliranmu!" Binsar dan Bistok, yang sudah meluncur duluan, menyemangati Poltak.
Poltak bersiap. Kereta luncur diposisikan tepat di bibir lereng. Poltak duduk tegak di atasnya. Tongkat kayu, rem, digenggam erat di tangan kanan. Konsentrasi.
"Satu, dua, tiga!" Tepat pada hitungan ketiga, Bistok mendorong kereta Poltak.
Wush. Poltak, di atas keretanya, meluncur deras ke bawah. Entah berapa kilometer per jam kecepatannya.
Poltak merasa keretanya meluncur terlalu cepat. Layaknya batu jatuh bebas ke jurang. Semakin lama semakin cepat. Diputuskannya untuk mengerem.
Krak! Derak keras kayu patah. Poltak terkesiap. Tongkat remnya patah. Cilaka!
Kereta ngepot tanpa kendali. Poltak terlempar. Jatuh berguling-guling ke kaki bukit. Dunia berpusing cepat di kepala Poltak.
"Amangoi!" Poltak meraung, sesaat setelah berdiri, pusing. Pantat kanannya terasa kaku dan sangat nyeri. Sesuatu telah tertancap di sana, entah apa.
Poltak meraba pantatnya. Celananya sudah bolong. Jarinya menyentuh cairan. Darah.
"Ompung ....!" Poltak meraung sejadinya. Lalu berlari terjingkang-jingkang menuruni sisa lereng bukit, pulang menuju rumah neneknya. Pertolongan pertama pada kecelakaan ada di sana.
"Kenapa kau!" Kakek Poltak yang sedang menganyam keranjang rotan di teras rumah terheran-geran. Tak biasa dia melihat cucunya datang dengan gaya anjing kencing berlari.
"Ei, ompung ni Poltak! Lihat dulu cucu kita ini. Kenapa dia!" Kakek memanggil istrinya, nenek Poltak. Begitulah, suami Batak selalu menyerahkan urusan tangis anak-cucu kepada isterinya.
Nenek Poltak memburu dari dapur ke teras. Memeriksa kondisi Poltak, selayaknya seorang mantri kesehatan.
"Bah! Bagaimana bisa begini?" Gumam nenek Poltak sejurus setelah tahu apa yang terjadi dengan pantat cucunya itu.
Ada serpihan kayu seukuran biji sawo tertancap di sana. Itu patahan ujung tongkat rem yang melesat seperti pelor menembus sasaran empuk itu.
Nenek Poltak segera menyiapkan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan. Minyak kelapa, daun tekelan, minyak tanah, korek api, mendong dan gegep kakaktua.
"Sini kau! Lepas celana! Nungging!" Perintah nenek Poltak kepada cucunya.
"Bah! Kau mau kebiri juga cucu kita?" Kakek Poltak tiba-tiba bertanya menyela. Sebab dia seperti melihat seekor burung kecil dan dua butir telur di bokong cucunya.
"Amangoi. Jangan kebiri aku! Ompung, jangan!" Poltak meraung hebat mendengar pertanyaan kakeknya. Kebiri, ngeri.
Di benaknya, bayangan babi malang yang baru dikebiri neneknya tiba-tiba datang menyeringai, lalu terbahak puas.
"Tidaklah, dongok!" Nenek Poltak memarahi cucunya. "Kau juga. Diam saja kau di situ! Tak usahlah menakut-nakuti!" Suaminya tak luput dari semburan.
"Aku cuma bertanya saja. Marah pula kau." Kakek Poltak menggerutu.
Poltak pasrah, membiarkan neneknya beraksi. Mula-mula kulit pantat di sekeliling potongan kayu tertancap itu diolesi dengan minyak tanah. Kemudian disundut-sundut dengan mendong menyala. Terasa panas. Bagian yang tertusuk dipencet. Terdengar denting gegep. Besi dingin menyentuh kulit pantat. Lalu, plop.
Ajaib. Rasa pegal dan nyeri di pantat Poltak mendadak hilang. Pasti neneknya punya mantra penawar sakit.
Sentuhan terakhir. Daun tekelan ditetesi minyak kelapa, lalu dilumat dengan kedua telapak tangan. Setekah itu ditemplokkan pada luka di pantat Poltak.
"Beres. Sana, main seluncuran lagi! Pantat kirimu belum bocor, kan!" Begitu cara nenek Poltak melarang cucunya.
Tapi dasar Poltak, ketika neneknya beranjak ke dapur, dan kakeknya larut lagi menganyam keranjang, dia berjinjit hendak naik lagi ke bukit Partalinsiran.
"Poltak! Mau kemana kau! Sini!" Tiba-tiba neneknya berteriak dari dapur.
"Matilah aku," desis Poltak dalam hati. Dia tak habis pikir, bagaimana mungkin neneknya bisa tahu tentang sesuatu yang tak terlihat matanya.
"Iya, ompung." Poltak melangkah ke dapur. Di sana neneknya sedang berdiri tegak. Tangan kanannya menggenggam sebilah belati yang tak asing lagi bagi Poltak. Itu belati khusus untuk mengebiri babi jantan.
"Apa pula ini. Tuhan, tolonglah aku." Poltak mendadak lemas. (Bersambung)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H