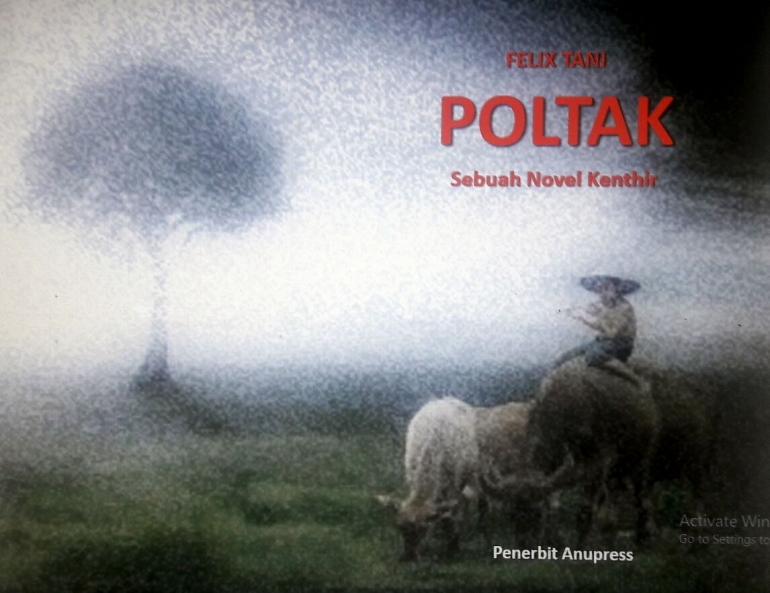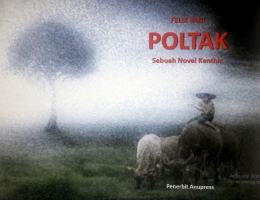"Amangoi!" Poltak meraung, sesaat setelah berdiri, pusing. Pantat kanannya terasa kaku dan sangat nyeri. Sesuatu telah tertancap di sana, entah apa.
Poltak meraba pantatnya. Celananya sudah bolong. Jarinya menyentuh cairan. Darah.
"Ompung ....!" Poltak meraung sejadinya. Lalu berlari terjingkang-jingkang menuruni sisa lereng bukit, pulang menuju rumah neneknya. Pertolongan pertama pada kecelakaan ada di sana.
"Kenapa kau!" Kakek Poltak yang sedang menganyam keranjang rotan di teras rumah terheran-geran. Tak biasa dia melihat cucunya datang dengan gaya anjing kencing berlari.
"Ei, ompung ni Poltak! Lihat dulu cucu kita ini. Kenapa dia!" Kakek memanggil istrinya, nenek Poltak. Begitulah, suami Batak selalu menyerahkan urusan tangis anak-cucu kepada isterinya.
Nenek Poltak memburu dari dapur ke teras. Memeriksa kondisi Poltak, selayaknya seorang mantri kesehatan.
"Bah! Bagaimana bisa begini?" Gumam nenek Poltak sejurus setelah tahu apa yang terjadi dengan pantat cucunya itu.
Ada serpihan kayu seukuran biji sawo tertancap di sana. Itu patahan ujung tongkat rem yang melesat seperti pelor menembus sasaran empuk itu.
Nenek Poltak segera menyiapkan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan. Minyak kelapa, daun tekelan, minyak tanah, korek api, mendong dan gegep kakaktua.
"Sini kau! Lepas celana! Nungging!" Perintah nenek Poltak kepada cucunya.
"Bah! Kau mau kebiri juga cucu kita?" Kakek Poltak tiba-tiba bertanya menyela. Sebab dia seperti melihat seekor burung kecil dan dua butir telur di bokong cucunya.
"Amangoi. Jangan kebiri aku! Ompung, jangan!" Poltak meraung hebat mendengar pertanyaan kakeknya. Kebiri, ngeri.