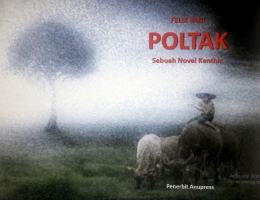Di benaknya, bayangan babi malang yang baru dikebiri neneknya tiba-tiba datang menyeringai, lalu terbahak puas.
"Tidaklah, dongok!" Nenek Poltak memarahi cucunya. "Kau juga. Diam saja kau di situ! Tak usahlah menakut-nakuti!" Suaminya tak luput dari semburan.
"Aku cuma bertanya saja. Marah pula kau." Kakek Poltak menggerutu.
Poltak pasrah, membiarkan neneknya beraksi. Mula-mula kulit pantat di sekeliling potongan kayu tertancap itu diolesi dengan minyak tanah. Kemudian disundut-sundut dengan mendong menyala. Terasa panas. Bagian yang tertusuk dipencet. Terdengar denting gegep. Besi dingin menyentuh kulit pantat. Lalu, plop.
Ajaib. Rasa pegal dan nyeri di pantat Poltak mendadak hilang. Pasti neneknya punya mantra penawar sakit.
Sentuhan terakhir. Daun tekelan ditetesi minyak kelapa, lalu dilumat dengan kedua telapak tangan. Setekah itu ditemplokkan pada luka di pantat Poltak.
"Beres. Sana, main seluncuran lagi! Pantat kirimu belum bocor, kan!" Begitu cara nenek Poltak melarang cucunya.
Tapi dasar Poltak, ketika neneknya beranjak ke dapur, dan kakeknya larut lagi menganyam keranjang, dia berjinjit hendak naik lagi ke bukit Partalinsiran.
"Poltak! Mau kemana kau! Sini!" Tiba-tiba neneknya berteriak dari dapur.
"Matilah aku," desis Poltak dalam hati. Dia tak habis pikir, bagaimana mungkin neneknya bisa tahu tentang sesuatu yang tak terlihat matanya.
"Iya, ompung." Poltak melangkah ke dapur. Di sana neneknya sedang berdiri tegak. Tangan kanannya menggenggam sebilah belati yang tak asing lagi bagi Poltak. Itu belati khusus untuk mengebiri babi jantan.