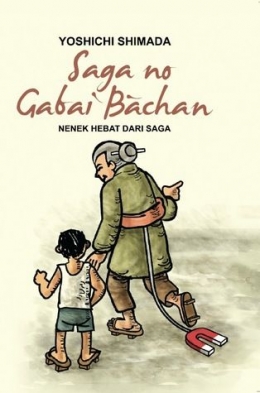Ada salah satu kisah favorit yang pernah saya dengat saat masa kuliah. Seorang pemilik perpustakaan yang kemudian juga induk semang saya, pernah diundang ke Festifal Buku Frankfurt tahun 2015.
Di sana, ia bertemu penulis anak yang memintanya untuk menulis kesan atau quote. Ia bilang, saat itu ia bingung mau menuliskan ungkapan bijak apa.
Meskipun ia-- induk semang saya ini bukan penulis, ia tentu banyak membaca buku atau setidaknya tahu banyak tentang isi-isi buku.
Mengejutkan, di antara ribuan buku miliknya, ia memilih kutipan dari salah satu buku yang pernah saya pinjam. Isinya "Jangan terlalu rajin belajar, bisa-bisa nanti jadi kebiasaan." Begitu kurang lebih ia menulis untuk penulis cilik tersebut. Saat mendengar cerita itu, saya tertawa dan tak habis pikir.
Pasti ada yang merasa quote itu aneh, konyol, atau tidak baik, dan itu wajar. Saya tak tahu bagaimana persisnya motif si Abang (begitu ia dipanggil), tapi mungkin buku atau kutipan itu punya kesan tersendiri baginya.
Namun yang jelas, ia yang hidupnya mengabdi untuk literasi tak mungkin hanya untuk memadamkan jiwa belajar si anak. Buku ini pun punya kesan khusus, setidaknya bagi saya yang punya memori jelek. Buku itu salah-satu yang saya ingat ketika melihat persoalan mengenai pendidikan yang saya jumpai.
Quote ini diambil dari buku "Saga no Gabai Bachan" yang jika diterjemahkan artinya "Nenek Hebat dari Saga". Buku ini ditulis oleh komedian Jepang, Yoshichi Shimada.
Diceritakan, kehidupan di Hirosima setelah Perang Dunia II membawa kesusahan bagi seorang ibu tunggal. Maka, ia terpaksa mengirim anaknya, Akhihiro Tokunaga kepada ibunya, Osana di kampung halaman.
Saat si anak yang diantar bibinya baru sampai di rumah nenek, neneknya langsung memintanya melakukan pekerjaan rumah, menanak nasi dengan kayu bakar karena ia harus bekerja.
Dari sana, saya mengira bahwa si nenek orang yang dingin atau justru cerita akan berbalik menjadi mengharukan. Namun, ternyata tak ada plot twist macam itu, watak si nenek memanglah nyentrik.
Ia tinggal di rumah yang jelek dekat sungai. Baginya ia memang orang miskin, tapi orang miskin ceria.
Ia sudah biasa miskin dan tak ada yang harus diratapi. Ia juga bukan tipe yang suka keras atau suka memanjakan cucunya. Ia mengajari Akhihiro dengan sewajarnya.
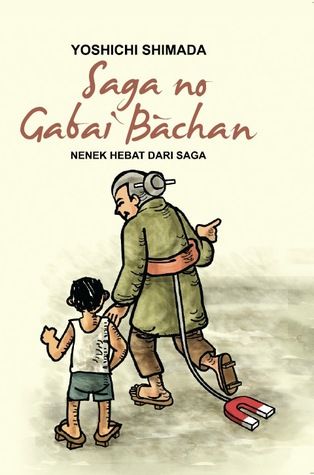
Selesai pulang dari bekerja, ia mengambil barang-barang kecil dari besi semisal paku yang tertarik oleh magnet untuk dijual. Selain itu, tiap hari, ia pun menyaring sayuran, udang karang, atau benda lain yang terjaring di sungai di dekat rumahnya.
Sayuran itu kebanyakan dianggap jelek bukan karena busuk, tapi karena bentuknya kecil, bengkok, atau bercabang. Ia selalu memanfaatkan hal yang orang lain anggap tak berguna.
Pada hari raya, ia pun mendapat persembahan/sesajen yang juga tersangkut di magnet. Ketika Akhihiro bertanya, "Apakah dewa tidak marah?" Neneknya justru bilang kalau dewa mungkin justru akan senang karena makanan itu dimanfaatkan dengan baik.
Meskipun kehidupan si nenek sangat sederhana, sebetulnya ia tak miskin. Akhihiro melihat neneknya meminjamkan uang pada orang-orang yang membutuhkan.
Si nenek pun membelikan sepatu mahal saat Akhihiro akan menjadi kapten bisbol di pertandingan sekolah. Baginya, pelit itu payah, hemat itu jenius.
Selain mengenai gaya hidup, si nenek pun punya pandangan unik mengenai pendidikan. Bagian ini menjadi bagian favorit saya dalam buku ini karena sebelumnya saya selalu terbayangi untuk selalu mendapat nilai bagus, yang kemudian menghilangkan esensi saya belajar.
Kutipan "Jangan terlalu rajin belajar" ini pun sebaiknya dipahami dulu konteksnya sebelum memutuskan benar atau salahnya. Tokoh nenek tidak pernah memaksa Akhihiro untuk belajar, juga sebaliknya.
Bagi saya, tokoh nenek hanya tidak ingin membebani cucunya untuk belajar hal-hal yang tak ia sanggupi.
Si nenek mengesankan bahwa Akhihiro bisa belajar di luar pelajaran sekolah yang mana juga sama-sama penting untuk kehidupan. Semisal dengan bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada sekaligus mencari bakat yang ada dari pada memaksakan diri.
Nenek pun membuktikan bahwa mendukung bakat cucunya meski bukan di bidang pelajaran, seperti saat ia membelikan sepatu yang harganya mahal karena Akhihiro besoknya menjadi kapten pertandingan bisbol. Ia pun selalu menyarankan Akhihiro menjawab jawaban yang ia tak mengerti dengan cara unik.
Seperti saat ia tak bisa mejawab sejarah, neneknya dengan enteng bilang, jawab, "Saya tak suka masa lalu". Tentu konyol, tapi mungkin si nenek pun tak tahu jawabannya, dan akhirnya ia memberi alternatif yang mungkin tak orang lain pikirkan. Kreatif juga termasuk hal yang tak mudah.
Saya selalu teringat cerita ini ketika melihat realita pendidikan yang sering saya alami atau dengarkan. Terkadang orang-orang terlalu ambisius untuk hanya mengejar nilai tinggi dan melupakan minat dan bakat yang sesungguhnya.
Saya paham jika memang orang itu memiliki ambisi kuat dalam akademik. Namun, kadang orang jadi lupa untuk melihat substansi belajar, yang bukan hanya untuk nilai semata. Apalagi, ketika yang ambisius bukanlah anaknya melainkan orangtuanya.
Bagi saya yang selalu jadi medioker dalam masalah ranking dan tidak ditekan orangtua, tidak dapat 10 besar dan masuk kuliah jalur undangan bukanlah masalah besar. Kecewa iya, tapi masih ada jalan lain menuju Roma kalau kata Idrus.
Bagi teman SMA yang saya kagumi tersebut karena prestasinya, nilai adalah beban. Setidaknya begitu saat ia tidak mengikuti ekspektasi orangtuanya.
Ia pun pernah cerita dimarahi saat nilai salah satu ulangannya mendapat nilai 80-an, padahal ia salah satu dari segelintir yang punya nilai tinggi, sedang yang lain jeblok pada saat itu.
Saya yang range nilainya 70-an ke bawah tentu terkejut, mungkin jika rata-rata nilai saya segitu, orangtua saya sudah pamer ke tetangga. Dan lucunya, saat itu saya masih saja iri karena nilainya selalu tinggi walaupun jelas effort-nya pun beda jauh.
Lebih lanjut, bukan hanya ambisi terhadap nilai yang selalu dipermasalahkan hingga kini. Sampai sekarang, masih ada pandangan bahwa pelajaran ilmu sosial tak sederajat dengan ilmu alam. Bahkan stigma jurusan IPA-IPS pun masih dilestarikan.
Dulu, saya masuk IPA karena takut ikutan nakal, yang selalu menjadi stereotip buruk anak IPS. Padahal, kawan-kawan saya terbukti tidak menjadi nakal walaupun masuk IPS.
Jadilah saya mengap-mengap masuk IPA karena tidak cocok. Saya selalu suka sejarah dan geografi dibanding geng sains. Mungkin itulah penyesalan besar saya saat SMA saya karena terpengaruh asumsi tak berdasar. Sayangnya, pengalaman yang hampir sedekade lalu ini kenyataannya masih saja terpelihara.
Kembali ke novel "Saga no Gabai Bachan", walaupun sebetulnya cara si nenek dalam novel ini tak perlu dituruti, tapi setidaknya kita disadarkan bahwa kita ahrus mampu mencari alternatif saat menghadapi kesulitan daripada berkutat dalam kesulitan tanpa adanya solusi. Salah dalam proses belajar bukan suatu aib.
Hal terakhir mengingatkan saya pada kejadian yang dialami oleh teman saya yang kerja sebagai honorer.
Ia "diteror" orangtua/wali karena nilai anak-anaknya jelek, dan mungkin juga memarahi si anak karena ini. Padahal soal-soal ujian itu sudah diberi banyak keringanan dan teman saya ini baru mengajar satu semester.
Mungkin memang harus ada evaluasi tentang caranya bagaimana ia harus mengajar ke depan, tetapi tetap tak bisa membenarkan bagaimana orangtua melihat nilai dan prestasi ini. Apalagi di masa ini, kegiatan belajar mengajar luring (offline) ini sedang tidak kondusif dilakukan.
Sekali lagi, nilai jelek bukanlah akhir dari segalanya. Lagi pula, dibanding menyalahkan guru, orangtua/wali pun memiliki tugas yang tak kalah penting dalam mengajar anak.
Dan yang terpenting, jangan sampai potensi anak yang lain mati karena hanya dibebani untuk mahir di bukan bidangnya. Mungkin itu pula alasan mengapa penulis, Yoshichi Shimada menulis cerita yang didasarkan atas pengalaman bersama neneknya di Saga ini. Ia membuktikan bahwa ia bisa menjadi sukses walaupun neneknya tak pernah menuntutnya hanya untuk mengejar sebuah angka.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H