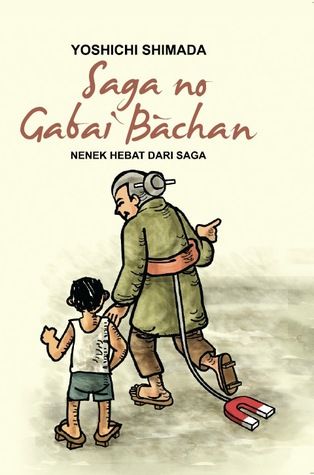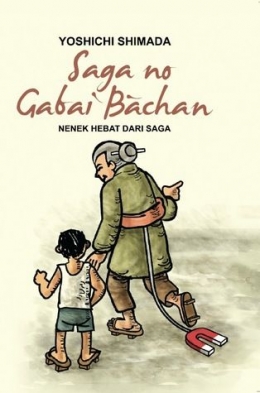Nenek pun membuktikan bahwa mendukung bakat cucunya meski bukan di bidang pelajaran, seperti saat ia membelikan sepatu yang harganya mahal karena Akhihiro besoknya menjadi kapten pertandingan bisbol. Ia pun selalu menyarankan Akhihiro menjawab jawaban yang ia tak mengerti dengan cara unik.
Seperti saat ia tak bisa mejawab sejarah, neneknya dengan enteng bilang, jawab, "Saya tak suka masa lalu". Tentu konyol, tapi mungkin si nenek pun tak tahu jawabannya, dan akhirnya ia memberi alternatif yang mungkin tak orang lain pikirkan. Kreatif juga termasuk hal yang tak mudah.
Saya selalu teringat cerita ini ketika melihat realita pendidikan yang sering saya alami atau dengarkan. Terkadang orang-orang terlalu ambisius untuk hanya mengejar nilai tinggi dan melupakan minat dan bakat yang sesungguhnya.
Saya paham jika memang orang itu memiliki ambisi kuat dalam akademik. Namun, kadang orang jadi lupa untuk melihat substansi belajar, yang bukan hanya untuk nilai semata. Apalagi, ketika yang ambisius bukanlah anaknya melainkan orangtuanya.
Bagi saya yang selalu jadi medioker dalam masalah ranking dan tidak ditekan orangtua, tidak dapat 10 besar dan masuk kuliah jalur undangan bukanlah masalah besar. Kecewa iya, tapi masih ada jalan lain menuju Roma kalau kata Idrus.
Bagi teman SMA yang saya kagumi tersebut karena prestasinya, nilai adalah beban. Setidaknya begitu saat ia tidak mengikuti ekspektasi orangtuanya.
Ia pun pernah cerita dimarahi saat nilai salah satu ulangannya mendapat nilai 80-an, padahal ia salah satu dari segelintir yang punya nilai tinggi, sedang yang lain jeblok pada saat itu.
Saya yang range nilainya 70-an ke bawah tentu terkejut, mungkin jika rata-rata nilai saya segitu, orangtua saya sudah pamer ke tetangga. Dan lucunya, saat itu saya masih saja iri karena nilainya selalu tinggi walaupun jelas effort-nya pun beda jauh.
Lebih lanjut, bukan hanya ambisi terhadap nilai yang selalu dipermasalahkan hingga kini. Sampai sekarang, masih ada pandangan bahwa pelajaran ilmu sosial tak sederajat dengan ilmu alam. Bahkan stigma jurusan IPA-IPS pun masih dilestarikan.
Dulu, saya masuk IPA karena takut ikutan nakal, yang selalu menjadi stereotip buruk anak IPS. Padahal, kawan-kawan saya terbukti tidak menjadi nakal walaupun masuk IPS.
Jadilah saya mengap-mengap masuk IPA karena tidak cocok. Saya selalu suka sejarah dan geografi dibanding geng sains. Mungkin itulah penyesalan besar saya saat SMA saya karena terpengaruh asumsi tak berdasar. Sayangnya, pengalaman yang hampir sedekade lalu ini kenyataannya masih saja terpelihara.