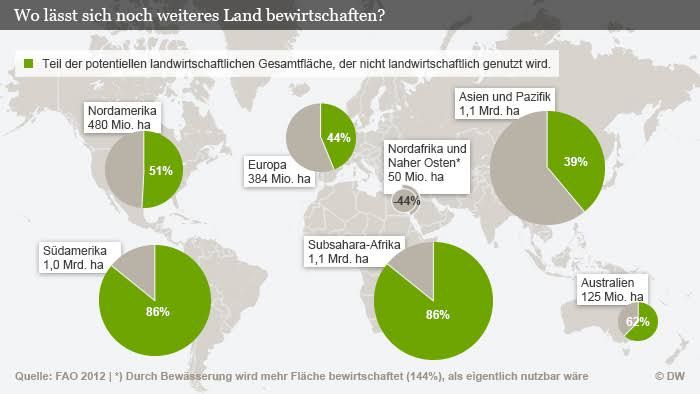Tak pelak, banyak keluarga yang dihadapkan pada keputusan sulit di tengah kondisi rawan pangan ini. Banyak dari mereka yang terpaksa melewatkan makan, makan makanan yang kurang bergizi, memprioritaskan anak-anak daripada orang dewasa untuk makan, berutang untuk membeli makanan, atau sampai menjual aset rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan. Ada hari-hari ketika mereka hanya makan satu kali sehari mereka, bahkan ada yang tidak punya apa-apa untuk dimakan.
Untuk Indonesia sendiri, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi terkait pangan. Berdasarkan Food Sustainability Index 2020, Indonesia menempati peringkat ke-60 dan 67 negara dalam hal keberlanjutan pangan menurut tiga indikator, yakni pemenuhan gizi, penerapan pertanian berkelanjutan, dan limbah makanan. Terkait limbah makanan, jumlah limbah makanan di Indonesia yang mencapai 23-48 juta ton per tahun. Jumlah itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-2 negara pembuang makanan di dunia.
Namun mirisnya, untuk Indonesia sendiri, jumlah orang dewasa yang obesitas meningkat dua kali lipat selama dua dekade terakhir. Satu dari tiga orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas. Sementara, 40% orang Indonesia mengalami kekurangan gizi mikro yang berarti kekurangan asupan vitamin dan mineral dari makanan yang diasupnya.
Seiring dengan itu, obesitas pada anak juga meningkat. Padahal di sisi lain, 27,67% anak di Indonesia di bawah usia 5 tahun mengalami stunting, atau terlalu pendek untuk usia mereka. Satu dari tiga anak di Indonesia menderita stunting. Angka stunting ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka rata-rata di kawasan Asia.
Secara umum dapat dianalisis bahwa Indonesia memiliki sistem pertanian pangan dari hulu hingga hilir yang belum terpecahkan. Hal ini diantaranya karena Indonesia menghadapi situasi menurunnya luasan lahan berkualitas dan mandegnya regenerasi petani. Kombinasi situasi ini membuat posisi Indonesia sulit. Bayangkan saja, negara agraris tetapi mengimpor banyak produk pangan dari luar negeri. Tidak masuk akal, bukan?
Mencermati hal ini, tampaknya tak sepenuhnya benar jika menjadikan momentum pandemi Covid-19 sebagai kambing hitam peningkatan skor kelaparan global. Meski mungkin ada benarnya jika kondisi pandemi menyebabkan sejumlah roda ekonomi manusia, bahkan global, melambat. Namun secara realitas, pandemi lebih tepat disebut hanya sebatas memperburuk skor kelaparan global itu.
Juli 2021 lalu, WFP menyatakan angka kelaparan global melonjak 40% akibat kenaikan harga pangan. Jelas sekali, harga pangan yang tinggi adalah sahabat baru kelaparan. WFP menyatakan rata-rata harga tepung terigu di Lebanon telah meningkat 219% tahun-ke-tahun di tengah percepatan gejolak ekonomi. Sementara harga minyak goreng telah melonjak 440% dibandingkan tahun lalu di Suriah yang dilanda perang. Sementara menurut indeks harga FAO, di pasar perdagangan internasional, harga pangan dunia memang naik 33,9% dari tahun ke tahun.
Di Indonesia sendiri, fluktuasi harga bahan pangan juga tak terhindarkan. Dari yang sebelumnya inflasi sebagaimana kasus harga cabai dan minyak goreng, hingga harus anjlok menjadi deflasi sebagaimana yang menimpa harga telur dan daging ayam. Mencermati hal ini, mungkin benar bahwa negeri kita memerlukan perbaikan sistem pertanian pangan. Namun, haruskah disolusi dengan penambahan lembaga baru seperti Badan Pangan Nasional (BPN)?
Mengutip pernyataan pemerhati kebijakan pertanian dan pangan, Emilda Tanjung, M.Si di muslimahnews.com, kelahiran BPN akhir Juli lalu seakan menjadi angin segar. Harapannya, badan ini mampu mengurai benang kusut masalah pangan dengan mengintegrasikan pengaturan sektor pangan yang selama ini tersebar di berbagai lembaga pemerintahan yang membuahkan kebijakan tumpang tindih. BPN juga ditargetkan bisa mengatasi karut-marut tata kelola pangan, khususnya impor pangan yang selama ini merajalela dan menjadi celah bagi pemburu rente.
Namun apalah daya, disinkronisasi kebijakan dalam negara demokrasi neoliberal sudah bukan rahasia. Demokrasi menganut konsep desentralisasi kekuasaan dan pembatasan peran negara sebatas regulator, dan hal ini juga terjadi di negeri kita.
Apalagi, ternyata pembentukan BPN ternyata tak dapat dilepaskan dari Omnibus Law UU Cipta Kerja No. 11/2020. Padahal, UU Omnibus Law ini nyata-nyata berpihak pada oligarki daripada rakyat, serta mengakomodasi investasi dan kepentingan pasar. UU ini juga jauh dari cita-cita kedaulatan pangan dengan makin memperlonggar kebijakan impor pangan. Implementasi UU ini justru menguatkan arus liberalisasi sektor pangan. Alih-alih fokus pada kesejahteraan rakyat, BPN dipastikan berjalan mengikuti mandat UU tersebut.