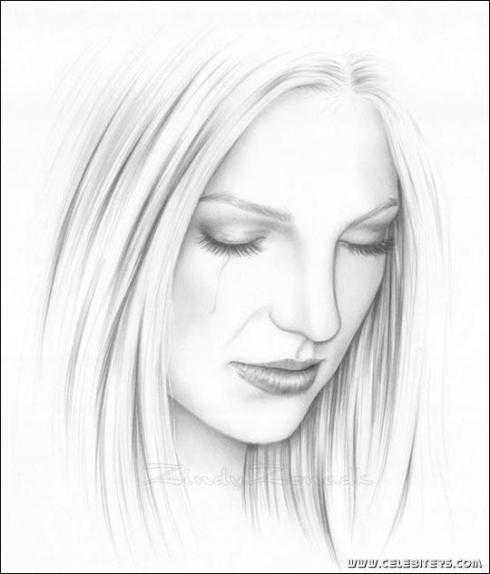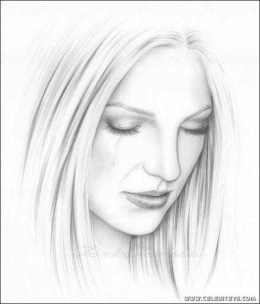"Kau gila! Teman paling gila yang pernah saya punya!" teman terdekat saya mencaci ketika siang panas menyengat itu kami tidur telentang di lantai kamar pribadinya. Saya hanya memiliki satu teman dekat : Judith, lain tidak. Banyak orang menjauhi saya, mereka bilang saya aneh, juga tak tersentuh. Saya hanya tidak suka keramaian, termasuk basa-basi.
Untuk pertamakalinya saya mencoba bicara tentang cinta pada Judith. Sebagaimana cinta yang dimiliki para remaja pada umumnya, cinta yang membutuhkan kedekatan dan hubungan lebih dari sekedar teman. Mula-mula dia tersenyum lebar mendengar pengakuan saya, lalu bertanya lebih jauh tentang sosok lelaki yang tengah menjadi idaman saya. Dia bersyukur saya adalah perempuan normal dan bukan lesbian yang tengah mengancam kehormatannya. Saya menimpuknya dengan bantal, Judith berpikir terlalu jauh.
Merasa aman, Judith terus mengulik cerita yang tak henti mengalir dari bibir saya. Dia terkikik geli, kadang juga melotot tajam. Tapi setelah semua mencapai selesai, pada akhirnya dia memilih menghujankan sumpah serapah pada saya.
Kami amat dekat -- saya dengan lelaki itu. Bertemu setiap hari, bercengkerama setiap kali. Intensitas pertemuan yang begitu selalu, perlahan menumbukan perasaan lain dalam hati saya. Terlebih saya memahami dengan jelas setiap lekuk pribadinya. Perangai halusnya, sikap melindungi, kekuatannya mendengarkan saya bicara (sesuatu yang tak satupun laki-laki lain lakukan), juga kesabarannya menghadapi tingkah kanak saya. Semua hal itu membuat saya ingin lebih dari sekedar dekat dengannya.
"Dan kau menyimpannya sejak lama secara diam-diam?" yang meski tak henti mengutuk saya sepanjang cerita, Judith tetap mendengar dan menanggapi dengan antusias.
"Ya, bahkan setiap hari ulang tahunnya tiba saya tak pernah terlambat memberi kejutan, ucapan, juga kata-kata cinta."
Lelaki itu memang tak pernah (atau tak ingin?) hirau pada perasaan saya. Setidaknya itu yang saya rasa, meski ia tetap bersikap baik. Saya pikir dengan semua yang saya lakukan untuknya seharusnya ia mengerti. Tapi, ah, dunia lelaki memang selalu pelik, juga rumit. Lagipula saya sudah sering mendengar, makhluk bernama laki-laki sungguh tidak peka, apalagi jika itu tentang perasaan wanita.
"Menurutmu apa sebenarnya dia mengerti isi hati saya?"
Judith menggeleng. Tidak tahu, saya bukan laki-laki itu, jawabnya.
"Suatu hari nanti mungkin saya akan mengungkapkan semuanya." saya berujar sembari mengemasi barang-barang, bersiap pulang.
"Maksudmu kau akan mengatakan bahwa kau mencintainya?"
Saya mengangguk, lalu tersenyum. Judith tak memberi tanggapan apapun lagi kecuali menggeleng, sorot matanya abu-abu. Saya bergegas pulang.
Setiap hari saya memikirkan cara yang tepat untuk bicara dengan lelaki itu. Saya menimbang, apakah perlu membawakannya bunga? Kebanyakan cerita romantis begitu. Atau mempersiapkan tempat manis dan mewah? Ia suka makan bersama. Kepala saya masih sibuk dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain saat Ibu memanggil saya dari balik pintu kamar.
"Saya ingin ceritakan sesuatu." Segera saya bicara sesaat setelah mendengar suara Judith di seberang telepon.
"Apakah ini berita baik tentang kewarasanmu yang sudah kembali?"
Judith meledek saya. Dia memang pernah mengatakan bahwa saya bahkan jauh lebih buruk dari pagar yang makan tanaman. Saya tidak peduli. Makian Judith tidak pernah menyakiti saya. Justru dia tetap bertahan,mendengar apa yang saya ingin dia dengar, seburuk apapun.
"Saya punya seorang penghalang."
"Siapa?"
"Ibu."
Telepon hening. Tak berapa lama terdengar napas berat Judith di seberang.
Buku catatan harian saya menceritakan semuanya pada Ibu, dan itu membuat ia terkejut. Saya merasa seharusnya sayalah yang terkejut, juga marah. Ibu membaca buku saya tanpa izin. Kami saling tegang untuk beberapa waktu, hingga saya berhasil mendapatkan buku saya kembali.
"Ini semua bukan urusan Ibu!" saya sedikit memekik.
"Joanna, apa yang salah denganmu?"
Saya tidak mengerti maksud dari tatap putus asa yang Ibu beri pada saya.
"Tidak seharusnya Ibu membaca buku saya tanpa izin."
"Mengapa tidak kau ceritakan pada Ibu terlebih dahulu?"
Apa yang salah? Saya hanya jatuh cinta, sama seperti orang lain kebanyakan. Mengapa Ibu membuat semua jadi tampak begitu suram? Tak bisakah ia perlakukan semua dengan normal saja?
"Joan, bukankah sudah saya katakan sejak semula? Ini tak semestinya."
"Jadi benar, jatuh cinta hanya boleh bagi orang-orang tertentu saja?"
Kembali Judith menghela napas, lalu telepon sunyi.
Tiba-tiba saya merasa Judith bukanlah teman yang saya kenal. Bicara dengannya tidak lagi nyaman. Setelah sambungan telepon terputus, berminggu berikutnya saya tidak ingin menghubungi atau dihubungi olehnya. Kami tak lagi bertemu karena saya tidak pernah pergi ke sekolah. Tak ada lagi yang menarik di sana setelah teman terdekat saya pun berubah.
Tapi siang itu Judith datang, kulit putihnya menyala dibalut kemeja hitam pekat. Dia masuk, dan satu-satunya yang saya izinkan, ke kamar saya yang sepi saat seisi rumah tengah hingar oleh duka.
"Joanna?" dia mendekati saya yang duduk menghadap jendela. Saya mengerti nada tanya Judith juga jawaban apa yang dia inginkan.
"Saya sudah bicara pada lelaki itu, dan ia berkata setiap anak memang harus mencintai Ayahnya," saya menatap mata cemas Judith, "saya juga sudah menambahkan bahwa saya tidak mencintainya seperti itu."
Judith tak menanggapi apa yang saya katakan.
"Ayah menolak saya. Tapi bukan itu yang membuat saya bersedih."
Dia masih menatap saya sedang bibirnya telah lama beku.
"Ayah mengatakan bahwa dia teramat mencintai Ibu saya. Sedang saya hanya berpikir sederhana, dan melakukan hal-hal sederhana. Sesederhana ketika ada yang membuat cinta saya gerhana, ia harus disingkirkan. Siapapun itu. Lalu apa yang salah?"
Perlahan kepala Judith menggeleng. Dan setelah tak puas, baru bibir pucatnya mengucap sesuatu,
"Joanna, saya tidak tahu harus bersedih untuk siapa. Untukmu atau untuk Ibumu."
[-]
XM, Dec 16, '17
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H