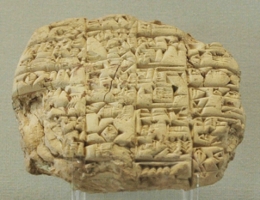Dan, kita memasuki era pasca Millenium, atau sering disebut sebagai era Generasi Z. Generasi ini mencakup generasi yang lahir setelah 1995 sampai 2009. Dalam cakupan pendidikan, generasi ini saat ini berusia antar 6 sampai 21 tahun. Mereka pada umumnya memiliki orang tua yang lebih berpendidikan dibandingkan dengan era generasi sebelumnya. Mereka juga disebut generasi ‘digital native’ karena mereka lahir pada saat teknologi digital ada. Generasi ini lahir ketika akses adalah serba mudah. Karenanya, terdapat kecenderungan bahwa generasi ini mencari pengetahuan sendiri melalui ‘gadget’nya. Bukan berarti mereka tidak merasa perlu pendidikan formal lanjutan.

Sebagian dari anak yang terlahir pada era ini dengan mudah memikirkan lapangan kerja setelah lulus sekolah. Oleh karenanya, ciri dari generasi yang sangat akrab dengan wirausaha ini menjadi nyata. Oleh karenanya, pendekatan magang adalah pilihan populer.

Suatu studi yang dibuat oleh Lowy Institute (2018) mencatat bahwa persoalan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan PR besar. Walaupun pemerintah Indonesia mencanangkan target untuk memiliki sistem pendidikan berkelas dunia pada 2025, perjalanan menuju ke cita cita itu masih cukup panjang. Persoalan persoalan kualitas berkaitan dengan kualitas guru, ketrampilan pedagogi, dan materi dan bahan ajar dinilai masih memiliki persoalan. Ini mengakibatkan hasil belajar murid masih kurang. Relevansi antara bidang studi dan ketrampilan yang dibutuhkan dunia kerja juga masih senjang. Pengelolaan pendidikan juga ada catatan.
Namun saya melihat persoalannya tidak sesederhana itu. Memang isu kualitas mengemuka, tetapi masalah keadilan akses mengganjal. Di wilayah terpencil di Kalimantan, Sulawsi, NTT dan Papua, misalnya, isu akses masih ada. Hal ini berkaitan dengan jarak dan biaya transportasi. Relevansi yang kurans sesuai dengan lapangan kerja membuat insentif untuk bersekolah kurang memadai.
Kurikulum yang berat dan memakan energi siswa dan guru tidak sesuai dengan alokasi waktu belajar . Murid dan Guru kelelahan untuk menyelesaikan ketuntasan. Ujian yang dilakukan dengan pilihan berganda dan banyak mendaur ulang soal soal yang telah melahirkan generasi penghapa. Soal gaji guru masih persoalan. Walaupun gaji guru sudah dinaikkan, namun ini masih belum memadai. Apalagi bila kita membincang keberadaan guru yang paruh waktu atau honorer. Pertanyannya, bagaimana mungkin seorang guru masih berada dalam status honorer selama lebih dari sepuluh tahun masa kerjanya? Bagaimana mungkin seorang guru honorer seperti Ibu Mus hanya menerimagaji Rp 500.000 untuk masa kerja 3 bulan? Ini di luar akal kita.
Persoalan masuknya paham paham yang tidak menghargai keberbagaian adalah tantangan berikutnya. Kekerasaan, termasuk kekerasan fisik, psikhis, 'bullying', dan bahkan kekerasan seksual juga membayangi pendidikan kita.
Memberikan otonomi penuh kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola pendidikan adalah berisiko tinggi. Dan kita alami itu. Sementara itu, tarik ulur kewenangan pemerintah propinsi menjadikan peran supervisi dan koordinasinya mandul.
Meski pemerintah di tingkat nasional mendorong implementasi pendidikan dengan target tertentu, adalah pemerintah kabupaten/kota dan propinsi yang pada akhirnya menentukan. Ini persoalan serius.
Ajakan agar kita semua bertanggung jawab pada pendidikan anak adalah suatu yang baik. Kerjasama di antara pemerintah, sektor swasta dan para pihak perlu menjadi realita. Aparat pemerintah perlu mendefinisikan ulang makna koordinasi yang semula lebih pada pemantauan dan pelaporan. Koordinasi hendaknya dimaknai sebagai strategi bersama dari para pihak untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan memberikan pendidikan berkualitas bagi semua.