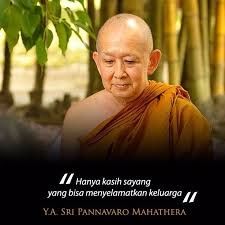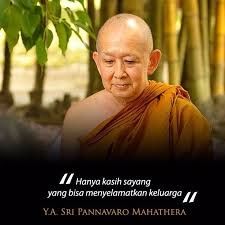Sebuah Kisah dari YM. Bhante Sri Pannavaro Mahathera. (**)
Di negara yang mayoritas beragama Buddha, sangat umum ditemukan arca Buddha yang berada dimana-mana. Alkisah di suatu hari pada saat hujan sedang datang mengguyur, ada seorang warga desa yang berjalan dan mendapatkan sebuah patung Buddha yang sedang kehujananan.
Merasa tidak pantas, sang warga kemudian berniat baik untuk melindungi patung Buddha tersebut dari guyuran hujan. Namun pada saat itu ia tidak membawa payung dan pakaiannya basah. Patungnya hendak diangkat, namun sudah direkatkan dengan semen di alasnya.
Bingung, sang warga pun melihat disekelilingnya. Dilihatnya sebuah sepatu butut, bentuknya sudah robek tidak karuan sehingga menyerupai lembaran kulit, baunya tidak karu-karuan sehingga pantas untuk menutup hidung. Sepatu butut itu diambil, diletakkan di atas patung Buddha, agar tidak kehujanan. Diapun berlalu pergi.
Tidak lama hujan pun berhenti, dan ada warga lain yang melewati jalan yang sama. Dia kemudian melihat patung Buddha yang bertopikan sepatu butut yang bau.
Dengan perasaan tidak nyaman, warga kedua pun membuang sepatu butut itu sambil mengumpat kepada siapapun yang telah berperilaku tidak sopan kepada patung sang Buddha.
Dari sini kita dapat melihat bahwa dua warga desa sama-sama memiliki kehendak baik, sama-sama telah melakukan tindakan baik, menghormati sesuatu yang harus dihormati menurut keyakinan mereka.
Namun dengan patung dan sepatu yang sama, tindakan mereka berbeda. Yang membedakan adalah pola pikir yang berasal dari situasi yang berbeda. Warga kedua tidak memahami maksud warga pertama, dan tentu tidak memahami kondisi yang telah terjadi. Mereka melakukan sesuatu berdasarkan pikiran yang berasal dari pengalaman yang dimiliki.
Jika ingin ditelaah secara logika, maka seharusnya;
Menutup kepala patung Buddha agar tidak kehujanan tidak akan membuat patungnya merasa hangat. Patung Buddha adalah benda mati.
Menaruh sepatu butut diatas kepala patung Buddha, juga tidak akan membuat patungnya merasa mual. Patung Buddha adalah benda mati.
Meskipun kedua warga sama-sama telah berbuat baik, namun tidak memberikan pengaruh fisik kepada patung Buddha. Bahwa perbuatan mereka hanyalah sebuah pola pikir bahwa patung tersebut adalah benda hidup.
Pola pikir terbentuk dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, namun sayangnya tidak semua pengetahuan dan pengalaman adalah benar adanya. Kita sering merasa sudah mengetahui banyak hal, namun ternyata pemahaman kita sering berasal dari:
1) Ketidaktahuan dan akhirnya menggeneralisasikannya dengan hal yang lain. 2) Berita bohong atau yang tidak benar 3) Mitos yang melekat akibat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan 4) Melihat sesuatu berdasarkan perasaan nyaman atau tidak nyaman.
Keempat hal tersebut diatas disebut dengan pikiran yang terdistorsi, sehingga output yang dikeluarkan dalam bentuk sikap, cara pandang, keputusan, dan ribuan jenis produk pikiran lainnya menjadi tidak sepenuhnya benar.
Hal ini disebut dengan STIGMA, atau menilai segala sesuatu yang berasal dari pikiran yang terdistorsi.
Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kita merasa jijik melihat kecoak, padahal kecoak tidak melakukan apa-apa. Kita merasa mual melihat sampah yang berserakan, padahal sampah memang ada dimana-mana, kita takut melihat mayat, padahal suatu saat kita akan menjadi mayat juga.
Saat ini Indonesia dan dunia sedang berperang melawan pandemi Covid-19. Terlepas dari bahaya penularan, menyebabkan sakit, dan juga merenggut nyawa, ancaman yang lebih berbahaya adalah stigma yang datang menghampiri.
Penolakan warga terhadap pemakaman jenasah pasien Covid-19 di Banyumas disebabkan oleh stigma. Penolakan tenaga medis oleh para tetangga di Jakarta Timur, disebabkan oleh stigma.
Pengusiran satu keluarga hingga mengungsi ke hutan di Minahasa Utara disebabkan oleh stigma, dan tindakan diskriminasi bagi para PDP dan ODP di berbagai daerah di Indonesia juga disebabkan oleh stigma.
Dampak yang lebih buruk dari penumbuhan stigma ini, adalah masyarakat yang tidak mau terhakimi akhirnya menyembunyikan diri. Dengan demikian bahaya penyebaran akan menjadi sangat laten. Akan semakin banyak silent carrier yang kemudian berubah menjadi silent killer (baca artikel penulis lainnya).
Dan stigma ini tidak saja terjadi di Indonesia, namun juga di seluruh dunia! Betapa menakutkan menerima kenyataan bahwa stigma yang terjadi dapat merubah tatanan hidup dalam sekejap.
WHO menyadari bahaya ini dan telah memberikan beberapa saran untuk meredam tumbuh suburnya stigma di tengah masyarakat.
Bersikap empati kepada mereka yang terkena dampak, dengan tidak menyebutkan penderita sebagai kasus covid-19 atau korban, namun menggunakan istilah "orang yang sedang dirawat".
Menghindari berita yang belum tentu benar dan mencari fakta bukan rumor.
Bagi petugas medis yang bertugas atau mereka yang sedang berada dalam karantina, tetap melakukan kontak dengan keluarga dan para sahabat dan menjelaskan mengenai kondisi yang sedang mereka alami melalui telpon atau media sosial.
Menyebarkan berita positif terkait perkembangan pandemi.
Stigma berkembang seiring dengan rasa kecemasan dan ketakutan. Tidak banyak hal yang dapat dilakukan.
Kita cemas...
Apakah Corona ini? Mengapa ia ada? Mengapa penyebarannya begitu cepat? mengapa belum ada obatnya? Mengapa harus sekarang? Mengapa belum akhir? Mengapa aku tidak dapat memeluk sang buah hati? Mengapa orang yang aku cintai harus meninggalkanku? Mengapa aku, bukan kamu?
Kita takut...
Sehingga menolak jenasah Corona, mendiskriminasikan petugas medis, mengucilkan tetangga, memandang sinis yang sakit, memandang jijik mahluk yang bernama manusia, padahal kita adalah manusia.
Tiba saatnya hujan datang mengguyur, dan sang patung tetap berada di sana. Tidak lekang oleh hujan, tidak tergoyahkan oleh badai.
Hingga warga desa yang baik hati datang menghampiri, memberikannya sepatu butut sebagai topi pelindung sakratul maut. Namun, kebaikan hati tidak membuat sang patung menjadi hidup.
Hingga warga desa lainnya yang baik hati datang bersungut, membuang sepatu butut dan meminta hukuman dari malaikat maut. Namun kemarahan tidak membuat sang patung menjadi hidup.
Sang patung akan terus berada disana, diam melekat tidak bergeming. Tidak cemas dengan pandemi, tidak takut dengan kematian.
Hingga akhirnya, menjadi satu-satunya saksi bisu kehidupan setelah pandemi.
(**) Bhikkhu Sangha Theravada Indonesia.
SalamAngka
Rudy Gunawan, B.A., CPS
Numerolog Pertama di Indonesia -- versi Rekor MURI
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H