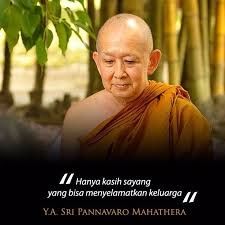Stigma berkembang seiring dengan rasa kecemasan dan ketakutan. Tidak banyak hal yang dapat dilakukan.
Kita cemas...
Apakah Corona ini? Mengapa ia ada? Mengapa penyebarannya begitu cepat? mengapa belum ada obatnya? Mengapa harus sekarang? Mengapa belum akhir? Mengapa aku tidak dapat memeluk sang buah hati? Mengapa orang yang aku cintai harus meninggalkanku? Mengapa aku, bukan kamu?
Kita takut...
Sehingga menolak jenasah Corona, mendiskriminasikan petugas medis, mengucilkan tetangga, memandang sinis yang sakit, memandang jijik mahluk yang bernama manusia, padahal kita adalah manusia.
Tiba saatnya hujan datang mengguyur, dan sang patung tetap berada di sana. Tidak lekang oleh hujan, tidak tergoyahkan oleh badai.
Hingga warga desa yang baik hati datang menghampiri, memberikannya sepatu butut sebagai topi pelindung sakratul maut. Namun, kebaikan hati tidak membuat sang patung menjadi hidup.
Hingga warga desa lainnya yang baik hati datang bersungut, membuang sepatu butut dan meminta hukuman dari malaikat maut. Namun kemarahan tidak membuat sang patung menjadi hidup.
Sang patung akan terus berada disana, diam melekat tidak bergeming. Tidak cemas dengan pandemi, tidak takut dengan kematian.
Hingga akhirnya, menjadi satu-satunya saksi bisu kehidupan setelah pandemi.
(**) Bhikkhu Sangha Theravada Indonesia.