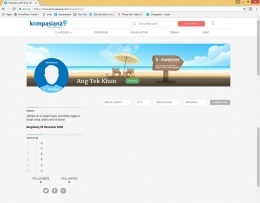Yang terberat dalam setangkup pergulatan hidup saya bukanlah membuka akun dan mulai menulis di Kompasiana. Bukan pula upaya meredam emosi tinggi karena rewel mesin Kompasiana kerap menguapkan semangat dan membubarkan ide-ide untuk menulis blog. Yang tersulit untuk saya lalui bukanlah itu, melainkan kegagalan, berulang-ulang, untuk meninggalkannya.
Di derap minggu yang baru saja berlalu, sebagai misal, saya dihempas dan tiba di tubir keputusan untuk membuka akun di sebuah platform prospektif relatif baru yang memadukan konten news dan blog kuratif. Namun, lagi-lagi, untuk kesekian kalinya, saya kembali terpekur gagal. Memilih terdiam, dan tidak melanjutkan klak-klik untuk Sign up.
15 Agustus 2013 adalah titimangsa akun ini. Namun sejatinya, ini bukanlah akun pertama saya di Kompasiana. Beberapa hari ini saya mencoba membidak akun lawas saya di sini dan mencoba melakukan beberapa upaya pemulihan. Menempuh beberapa upaya ke satu-dua pihak. Namun saya harus berbesar hati dan membiarkan akun www.kompasiana.com/angtekkhun berlalu dari jangkauan.
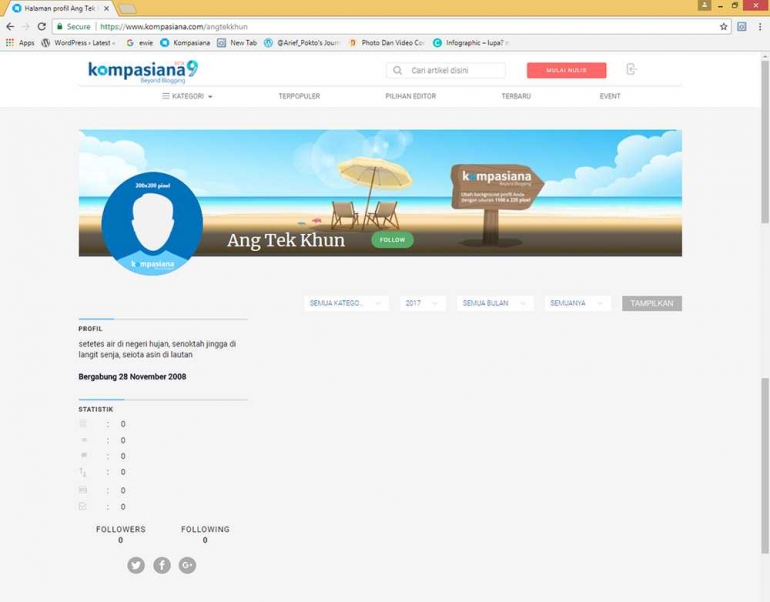
Alkisah, cerita tentang akun lawas ini bisa dimulai denan menyebut nama Apollo Lase. Dia seorang kawan daring yang bekerja sebagai editor di harian Kompas. Dia pula yang memperkenalkan nama "Kompasiana" dan melakukan beberapa pendekatan lihai untuk "menghasut" saya membuka akun serta menulis di sana.
Seperti pepatah mengatakan "seribu sahabat tak pernah berlebih, seorang musuh sudah terlalu banyak", dan keyakinan bahwa "kawan sejalan tak akan pernah menjerumuskan sesenti pun tapak jalan", saya pun manut dan dengan wajah culun segera mengklak-klik di sana-sini. Hasilnya? Saya punya akun Kompasiana!
Waktu bergerak dan di hari senggang ketika saya tidak dikejar tenggat, saya mencoba membuka dan membaca Kompasiana. Di menit-manit awal, laman-laman di muka, saya telah dibuat terhenyak. Nama-nama beken dan keren yang saya kenali tercetak di harian Kompas, ada di sini. Karya tulis mereka, yang bagi otak cupet saya yang unyu, terbaca sebagai narasi-narasi besar yang tak sebanding dengan kompetensi dan kemampuan pikir atau pengalaman saya.
Perlu diberi latar di sini bahwa kala itu, dunia blogging sedang ngehits. Bukan sebagai "tokoh" di layar pertama, namun senyampang menunaikan pekerjaan sebagai editor, saya (ehem!) cukup terkenal di dunia ini. Ini sebagai konsekuensi dari saya bergabung di Komunitas Bloger bernama Blogfam, yang di era itu sangat terkenal---di dalamnya bergabung orang-orang penting di negeri ini sebagai "batu penjuru" dalam merebakkan dan memekarkan kehidupan berblog di tanah air.

Blog pribadi pertama saya di Wordpress, turut hadir di keriuhan tersebut. Isinya? Jurnal kehidupan sehari-hari dengan narasi-narasi kecil, ngepop, sesuka hati, dan "menye-menye". Sebagai catatan penting nih, pada era yesterday itu, menulis ala "menye-menye" adalah cara menulis terpopuler dan favorit yang menonjol.
Kini, kiranya Anda telah tertolong untuk membangun imajinasi, bagaimana mungkin seorang bloger "menye-menye" bersanding topik, narasi, dan cara menulis di tataran yang sama dengan para jurnalis Kompas?
Namun sebagai seseorang yang merasa (dan cukup ge-er) diberi karunia kreativitas, secara naluriah saya melakukan pencarian sudut pandang, sesuatu yang kini disebut dengan nama keren: Branding. Melalui proses ini, saya menemukan, bahwa satu-satunya cara tampil agar tak minder dengan jurnalis kawakan itu, saya akan mengisi akun Kompasiana ini dengan puisi-puisi. Oya, sebagai catatan, di masa itu nama saya mulai menanjak sebagai salah satu penyair newbie potensial Indonesia. [Ehem! Kala itu Jokpin ada di mana, ya?]
Harapan dan impian yang membubung selalu seharga dengan biaya jatuhnya! Itu yang saya alami dan rasakan, tatkala menemukan poin aturan main bahwa Kompasiana tidak menerima konten berupa puisi dan fiksi (?). [Maaf bila ingatan ini mengandung buram keliru tafsir.] Maka, di sinilah titik tumpu riwayat akun lawas Kompasiana saya ini kemudian tak pernah berpenghuni.

Ada proses panjang dan nelangsa dalam batin, hingga saya memilih mlipir dan menemukan keasyikan ngeblog di Instagram---alih-alih mengucapkan selamat berpisah atau mendua hati. Seiring dengan membaiknya kinerja mesin Kompasiana kini, saya sedang menapakkan kaki di jalan kembali. Bukankah orang bijak berucap, "rindu selalu menemukan jalan untuk pulang."
Di masa-masa sulit berkompasiana itu, banyak pertanyaan dan kegelisahan yang menggaung. Beberapa orang tak mengerti mengapa saya enggan berpindah ke "lain hati". Ada yang bertanya, mengapa saya tidak membangun dan membesarkan blog pribadi saja. Beberapa orang lagi, "mem-bully" di sisi loyalitas.
Kesempatan ini tampaknya adalah waktu terbaik bagi saya untuk memberi tahu secara lugas bahwa inilah cara saya membalas utang budi. Di masa saya merantau ke Pulau Jawa dan kuliah di Surabaya, honor-honor dari koran dan majalah Kelompok Kompas Gramedia turut membiayai kuliah saya. Meringankan dompet saya untuk membeli ini dan itu dalam keperluan sesehari. Melalui media-media Kelompok Kompas Gramedia ini pula saya banyak belajar ilmu menulis, langsung maupun tidak langsung. Beberapa sosok, seperti Arswendo Atmowiloto saat membina banyak newbie melalui Majalah Hai, menjadi guru tanpa kelas. Bahkan hingga kini, saya belum berhenti belajar menulis feature yang kental dan bernas melalui beberapa nama jurnalis di edisi Kompas Minggu.
Ini juga adalah cara "kecil" saya memberi tahu semesta bahwa "tidak semua kacang lupa akan kulitnya".
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H