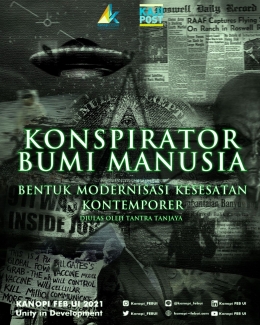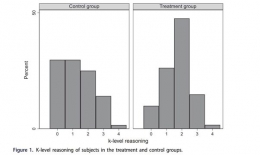Contoh dunia nyata dari hal ini adalah mereka yang melakukan penolakan terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia dengan alasan kepercayaan mereka bahwa COVID-19 tidak nyata.
Hal ini bukan terjadi karena mereka percaya terhadap teori konspirasi dengan sendirinya, melainkan karena dorongan naluriah atas kebutuhan bertahan hidup sehingga mereka merasionalisasi hal ini melalui teori konspirasi yang terdengar kompleks dan memiliki dasar kuat.
Sehingga, di masa kini, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami kompleksitas dari perilaku manusia agar dampak yang dirasakan bukan hanya secara material tetapi juga secara psikologis.
Dapatkah orang buta menuntun orang buta?
Sangat keliru bagi mereka yang menggambarkan perilaku para penikmat konspirasi sebagai hal yang tidak jelas dan tanpa dasar. Alasan kepercayaan mereka telah tertanam dalam struktur sosial-ekonomi yang mereka hadapi dan psikologis diri mereka. Kita telah melihat berbagai contoh konspirasi yang merugikan masyarakat di masa kini.
Namun, perilaku masyarakat yang selama ini hanya menganggap mereka sebagai orang aneh sangat kontraproduktif dari hal yang harus kita lakukan untuk membimbing mereka ke pemikiran empiris yang lebih berdasar.
Membiarkan mereka untuk terus berinteraksi dengan sesamanya juga bukan solusi. Pada akhirnya, dapatkah orang buta menuntun sesama orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lobang?
Referensi:
1. D. K. Chu et al., Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Lancet 395, P1973--P1987 (2020). Google Scholar
2. Franks B, Bangerter A, Bauer MW, Hall M, Noort MC. Beyond "monologicality"? exploring conspiracist worldviews. Frontiers in psychology. 2017; 8, 861. PMID: 28676768
3. Sumber 3