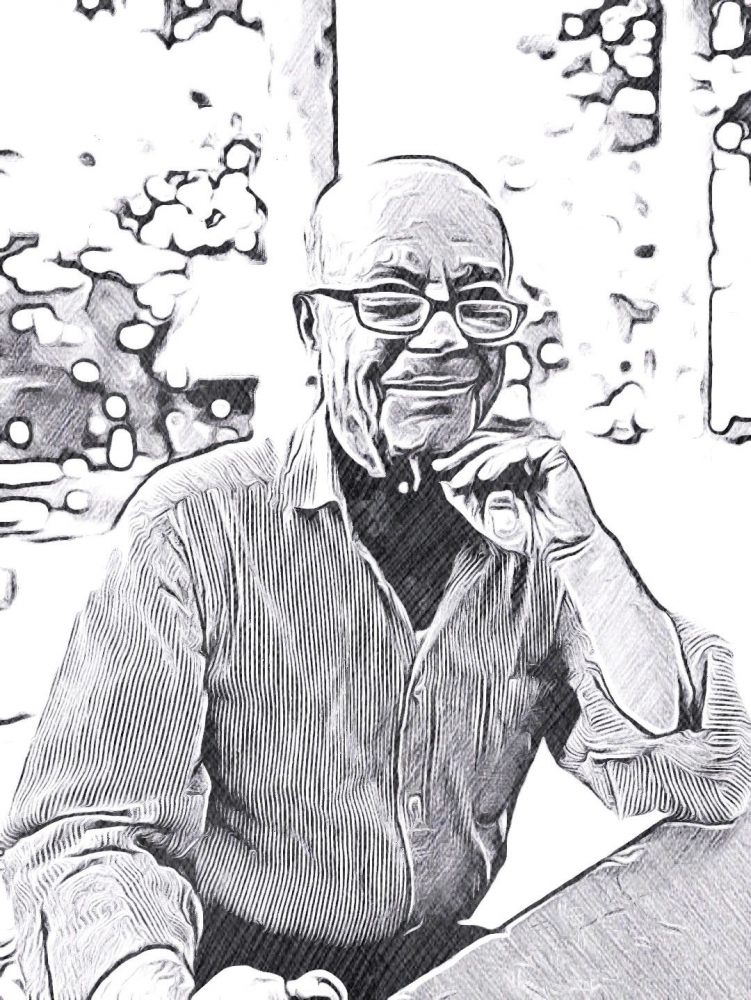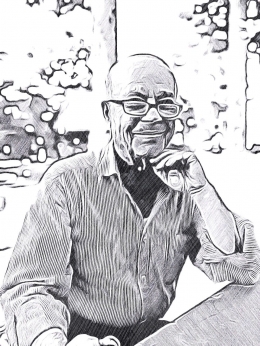Dulu, sekitar tahun 2008, sewaktu saya masih kuliah di UIN Maliki Malang, saya biasa mengerjakan tugas kelompok di salah satu kosan teman saya.
Alasan saya memilih kosan itu adalah selain tersedianya ruang tamu di teras rumah yang cocok untuk tempat ngumpul, pemilik kosnya pun selalu menyediakan harian koran Kompas teranyar di sana.
Sungguh tempat yang menurut saya sangat ideal untuk cangkrukan sembari berdiskusi dan membagi tugas makalah. Dan mungkin saja kondisinya akan bertambah lengkap manakala tersedia suguhan secangkir kopi hitam di atas meja.
Seraya menunggu teman-teman saya datang ke kosan ini, biasanya saya membolak-balik beberapa halaman koran Kompas yang tampak menganggur di atas meja itu. Saya berharap barangkali ada isu terkini yang bisa diangkat untuk diskusi nanti.
Ketika sedang asyik-asyiknya membaca, biasanya saya didatangi oleh bapak pemilik kosan yang sekaligus empunya koran yang saya baca itu.
Saat beliau telah duduk di samping saya, saya pun tak lupa menyampaikan maksud kedatangan saya di kos miliknya untuk menghindari salah sangka sekaligus mohon izin untuk membaca koran miliknya. Sebuah permohonan izin yang mungkin saja akan ia anggap sebagai basa-basi yang termaklumi.
Sembari menunggu teman saya datang [sampai saat ini saya kurang terang, kenapa diantara mereka seringkali terlambat; apakah ini sebab mereka memang lama dalam menyiapkan materi diskusi, atau sengaja mengulur waktu sambil menunggu selesainya perbincangan saya dengan sang pemilik kosan], beliau pun biasanya mengajak saya ngobrol.
Nah, salah satu tema obrolan itulah yang hendak saya ceritakan dalam tulisan ini. Berikut adalah salah satu isi percakapan diantara kami.
"Mas, kalau menurut Sampeyan, dalam hidup ini enak yang mana antara 'me' dan 'di'?" tanya bapak kos itu membuka percakapan.
"Wah. Itu tergantung Pak. Harus melihat dulu kata apa yang menyambungnya." jawab saya setelah merenung sejenak. Saya membayangkan perbandingan katanya bisa digambarkan seperti: dirayu-merayu, disuap-menyuap, disakiti-menyakiti, dibunuh-membunuh, dan seterusnya.
"Kalau menurut saya pribadi, dalam hidup ini, lebih enak pilih yang 'di'" ujar pria paruh baya itu tiba-tiba menyimpulkan.
"Sekarang, coba Sampeyan renungkan saja, enak yang mana antara dicari pekerjaan ataukah mencari pekerjaan?!" bapak itu mengetes saya.
Ndilalah kok yang dijadikan contoh adalah kata ini. Maka saya pun menjawab spontan pertanyaan yang bisa dinalar oleh anak tingkat sekolah dasar ini, "Yah, kalau yang ini enak yang 'di' Pak."
"Namun, kalau mau pilih yang itu ada tapinya Mas. Untuk sampai pada tahap yang 'di' ini, kita harus memiliki bekal tersendiri sehingga kita memang pantas untuk dicari." terangnya sambil mengulum senyum.
"Mohon maaf. Saya mencontohkannya dari pengalaman saya pribadi saja ya, Mas. Dulu, setelah saya selesai kuliah di tingkat doktoral, saya tidak sempat mencari pekerjaan, sebab saya langsung ditawari pihak kampus untuk membantu mengajar di sana." lanjut bapak itu.
Wah ini! Rasanya penuturan kisah pribadi beliau ini bakal bisa jadi inspirasi tersendiri buat saya. Barangkali dengan mengikuti tips beliau saya pun bisa tertular kesuksesannya kelak; Dicari-cari oleh pekerjaan. Dan selain itu, beliau masih punya usaha kosan. Ibaratnya dari arah kanan-kiri penghasilannya akan selalu bisa mengalir. Jika masa pensiunnya tiba, mungkin saja beliau hanya tinggal ongkang-ongkang sambil menunggu datangnya cuan. Begitulah gumam saya waktu itu.
"Saya itu Mas, sedari dulu fokusnya hanya belajar dan belajar saja. Tidak pernah ada niat sedikit pun untuk pacaran. Jika saya memang harus terpaksa pacaran, pacar saya ya buku-buku itu." Bapak itu menuturi saya secara perlahan.
Penuturan bapak ini pun kian saya simak dalam-dalam agar tidak ada satu pun yang terlewat dari pemahaman saya.
"Selain itu, jadi orang itu sebaiknya jangan 3L. Mas tahu apa itu 3L?" bapak itu tiba-tiba bertanya.
"Belum tahu Pak." jawab saya seadanya.
"3L itu adalah singkatan dari lumuh (malas), lolak-lolok (bodoh), dan lontang-lantung (menganggurkan diri). Kalau siapa saja ingin sukses, ya harus menghindari sifat 3L ini. Terutama bagi para mahasiswa, seringkali setelah mereka lulus jadinya bingung mau kerja apa. Barangkali dengan mencermati penyakit 3L ini, mereka pun tak akan mendapati kegalauan yang semakin bertambah selepas lulus nanti."
"Penyakit 3L inilah yang harus selalu mereka lawan sejak masih berada di bangku kuliah agar tidak mengakar ketika telah menjadi sarjana. Jika mereka tak sanggup melawannya, besar kemungkinan penyakit ini pun akan terus menghinggap saat mereka terjun di tengah-tengah masyarakat."
Saya pun menyimak dengan khidmat pesan demi pesan yang disampaikan oleh pria yang menjelang sepuh itu. Barangkali dengan menilik nasehat-nasehat darinya akan membawa kebaikan tersendiri bagi saya di masa kelak.
Usai pembicaraan yang singkat ini, sang bapak pemilik kosan pun bangkit perlahan dari kursinya, isyarat ia lekas mengakhiri percakapan. Sambil membuka pintu rumahnya beliau pun mohon diri dari saya.
Saya benar-benar bersyukur dapat berada di kosan ini. Sebab, selain tempatnya yang nyaman, ia pun masih dilengkapi dengan keramahan sang pemiliknya yang gemar berbagi hikmah seputar kehidupan.
Dengan segala kelengkapannya ini, rasa-rasanya tanpa ditemani secangkir kopi pun sudah cukup alasan bagi saya untuk terus menyinggahinya. [mam]
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H