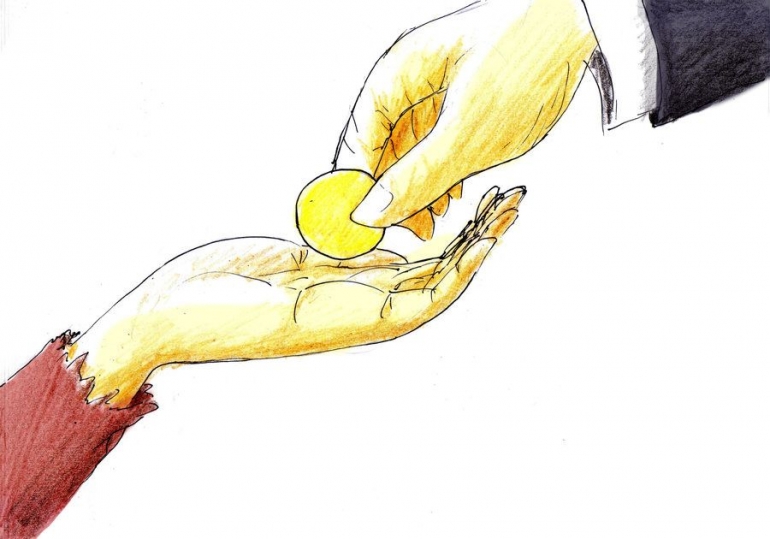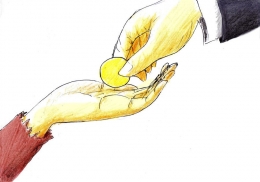Korban dan kurban adalah dua hal yang berbeda, tapi sebetulnya masih "bersaudara". Istilah kurban biasanya mengemuka pada Hari Raya Idul Adha, yang sering juga disebut Hari Raya Haji atau Hari Raya Kurban.
Kenapa dinamakan seperti itu, tentu karena pada hari raya tersebut, di tanah suci lagi berlangsung pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, di berbagai penjuru dunia yang dihuni umat Islam, bagi yang mampu, akan menyembelih hewan kurban.
Hewan kurban, yang di negara kita kebanyakan berupa kambing dan sapi, akan dibagikan kepada warga yang kurang beruntung secara ekonomi.
Pada saat itulah, mereka yang selama ini jarang menikmati makanan yang diolah dari daging, akan bersukacita, sejenak bisa melupakan penderitaan hidupnya.
Adapun istilah "korban", relatif sering kita dengar, apalagi sejak pandemi Covid-19 melanda negara kita. Hingga tulisan ini ditulis, sudah 74.920 orang yang berkorban nyawa.
Sedangkan korban yang terpapar virus tercatat 2,91 juta kasus, meskipun 2,29 juta di antaranya sudah dinyatakan sembuh.
Jangan mengira, masyarakat yang tidak terpapar, tidak menjadi korban. Bukankah banyak yang berkorban secara ekonomi karena kehilangan mata pencaharian atau menurunnya penghasilan?
Berita bagusnya, sejak pandemi, banyak terlihat gerakan spontan angota masyarakat untuk mengumpulkan donasi dan memberikannya pada warga yang membutuhkan.
Di samping itu, sebelum ada pandemi pun, sudah banyak pula berdiri yayasan atau lembaga yang bergerak di bidang sosial. Dalam konteks ajaran agama Islam, yang dimaksud adalah Badan Amil Zakat atau sejenis itu.
Saya pernah beradu argumen dengan seorang teman yang kebetulan menjadi pengurus sebuah yayasan yang mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah, serta mendistribusikannya kepada yang berhak.
Bahwa yayasan tersebut punya tugas yang mulia, dan otomatis tugas teman itu juga mulia, jelas sesuatu yang tak perlu diperdebatkan.
Tapi, pernyataan si teman bahwa hanya (sekali lagi, saya ingin menekankan pada kata "hanya"), melalui lembaga resmi (termasuk yayasan tempat ia bekerja), yang paling efektif bila masyarakat ingin berbagi kepada kaum duafa, perlu saya kritisi.
Saya sebetulnya juga menggunakan lembaga resmi seperti itu, tapi bukan 100 persen, ketika saya ingin berbagi. Sebagian (yang jumlahnya cukup signifikan menurut ukuran kantong saya), justru dengan sengaja saya berikan secara langsung.
Pengertian langsung di sini, bisa saya berikan dalam bentuk tunai kepada orang yang menurut saya layak menerima, atau melalui transfer ke rekening, bila si penerima domisilinya jauh dari tempat saya.
Sekarang, boleh dikatakan semua orang sudah punya rekening di bank, dan itu tidak berarti ia punya saldo yang cukup. Banyak juga yang membuka rekening dengan tujuan memudahkan orang lain yang akan mengirimkan donasi pada mereka.
Bukannya saya tak percaya dengan yayasan atau lembaga penyalur zakat. Bahkan, banyak yang mempublikasikan laporan keuangannya di media massa sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabannya kepada publik.
Masalahnya, saya punya orang-orang yang dekat dengan saya yang saya tahu persis kehidupannya, untuk sekadar menutupi makan sehari-hari saja, relatif susah.
Orang dekat tersebut contohnya beberapa orang sepupu saya sendiri. Ada yang berjualan kecil-kecilan, tapi dengan hasil yang tidak bisa menutupi kebutuhan keluarganya.
Ada pula yang menderita penyakit kronis, sehingga tidak bisa bekerja dan lebih banyak mengharapkan bantuan dari sanak famili.
Ada pula beberapa keluarga yang menjadi tetangga saya dan mantan tetangga yang pada waktu-waktu tertentu datang ke rumah dengan tujuan meminta bantuan.
Selain itu, seperti yang telah disinggung di atas, ada gerakan spontan dari anggota masyarakat untuk menggalang bantuan, antara lain dengan mengontak teman-temannya melalui media sosial.
Maka, saya juga perlu merespon pecakapan di grup media sosial untuk program "Jumat Barokah" yang diinisiasi teman saya. Bagi yang ingin menyumbang, bisa mentransfer uang, yang nantinya akan dibelikan nasi kotak seharga Rp 20.000 per kotak.
Di grup media sosial para perantau dari nagari (desa) kelahiran ibu saya (orang Minang marganya atau sukunya ikut suku ibu), ada juga pengumpulan dana seperti itu, tapi untuk membiayai pengobatan kerabat yang sakit.
Masih ada lagi bebarapa grup media sosial lainnya, yang punya inisiatif seperti itu, yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu.
Nah, maksud saya, upaya yang bersifat spontan dan informal tidak berarti kurang efektif ketimbang berdonasi melalui lembaga resmi yang terorganisir.
Menurut saya, semua bagus-bagus saja, asal semua bantuan yang terkumpul bisa secepatnya dibagikan kepada warga yang membutuhkan.
Bagi saya pribadi, jelas tidak mungkin mengabaikan sanak famili dan kerabat meski tinggal berbeda kota. Apalagi terhadap tetangga yang hampir setiap hari bertemu.
Tapi, menyisihkan rezeki untuk sebagian disalurkan melalui lembaga amil zakat, juga perlu, mengingat lembaga itu biasanya punya program yang terencana dengan manajemen yang lebih baik.
Kembali ke suasana Idul Adha, mudah-mudahan semangat berkurban tidak terhenti hingga di sini, tapi dikonversikan menjadi aksi berbagi secara terus menerus yang dilakukan secara tulus.
Kenapa faktor konsistensi dianggap penting? Karena pandemi yang melanda negara kita bisa jadi masih membutuhkan waktu yang relatif lama, hingga betul-betul hilang.
Bahkan, ada pula pendapat bahwa kita harus mampu hidup bersama pandemi, dalam arti bisa beradaptasi dan menjadikan kepatuhan atas protokol kesehatan sebagai gaya hidup dalam keseharian kita.
Soal apakah pakai metode langsung atau tidak langsung, diserahkan pada pilihan masing-masing orang. Yang penting itu tadi, aksi berbagi itu dilakukan secara tulus dan konsisten.
Tak perlu pula kita berdebat soal apa yang kita bagi. Kata orang bijak, berilah kail bukan ikan. Dengan kail, pihak yang dibantu bisa mencari ikan.
Tapi, jika kita baru bisa memberi ikan, ya tidak masalah juga, meskipun idealnya memang memberi kail.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H