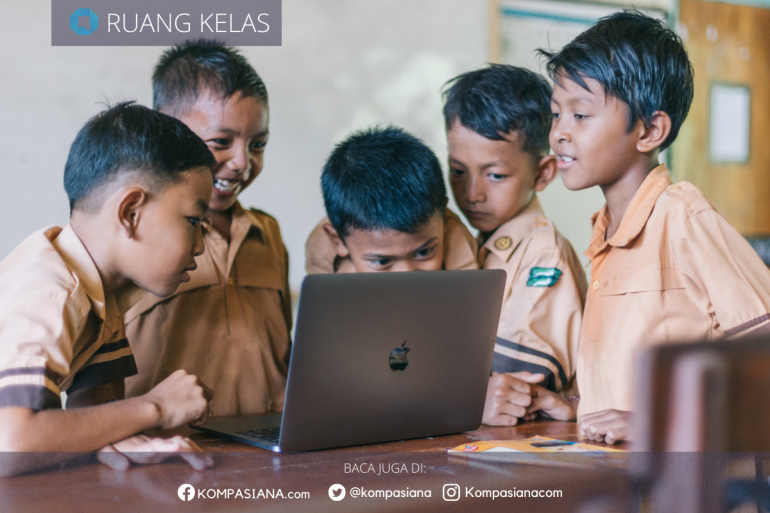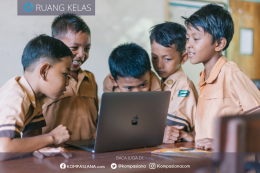Masyarakat Plural
Masyarakat sulit menerima hal baru yang kehadirannya tidak disesuaikan dengan pendekatan kulturalistik lokal. Pluralitas masyarakat seringkali menimbulkan konflik dan mengganggu harmoni sosial. Pluralitas tersebut mencakup banyak aspek, mulai dari budaya, agama, bahasa, dan suku serta ras. Maka tentu tantangan untuk menjaga integrasi pun menjadi penting untuk disosialisasikan. Meskipun teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx mengatakan bahwa masyarakat tidak bisa lepas dari konflik, tetap saja perlu ada pendekatan untuk meminimalisir frekuensi konflik itu terjadi.
Indonesia adalah negara dengan banyak sekali keberagaman. Semua keberagaman ini muncul setelah melalui sejarah yang panjang. Salah satunya adalah sejarah keberadaan agama di Indonesia. Pernahkan terpikirkan di benak kalian, mengapa negara yang sangat jauh letaknya dari timur tengah ini bisa menjadi negara kedua dengan populasi muslim paling banyak di dunia setelah pakistan dengan total 238 juta muslim? Ada banyak strategi yang dilakukan para tokoh besar agama Islam dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Tapi apakah semudah itu menyebarkan ajaran islam di negara ini?
Menyebarkan ajaran agama baru di sebuah bangsa yang semula mayoritas beragama Hindu dan Budha tentu sangat sulit dilakukan. Lalu bagaimana bisa Islam menyeruak sebesar ini di Indonesia? Dalam hal ini, pendekatan moderasi adalah jawabanya. Indonesia yang sejak dahulu dikenal sangat kental akan kebudayaan lokalnya, tentu saja menolak terlebih dahulu masuknya ajaran agama Islam. Masyarakat saat itu lebih menyukai tradisi dan adat kemasyarakatan ketimbang agama. Maka satu-satunya cara agar agama Islam diterima di Indonesia adalah dengan mengadakan akulturasi.
Akulturasi sendiri adalah upaya untuk menggabungkan dua kebudayaan, biasanya salah-satu kebudayaan tersebut merupakan kebudayaan lokal sedangkan kebudayaan lainnya adalah kebudayaan asing yang masih sulit diterima di lingkungan sosial. Akulturasi merupakan salah satu dari produk moderasi dalam hal beragama. Sedangkan moderasi beragama itu sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah konsep pendekatan yang berfokus kepada pengurangan konflik, pengelolaan dan pengenalan nilai-nilai agama dengan tujuan mempromosikan kerukunan antar keyakinan agama di suatu negara.
Moderasi beragama memiliki beberapa cakupan, diantaranya;
- Penghormatan terhadap kebebasan beragama.
- Promosi antar agama dan kerjasama antar umat.
- Pendekatan yang lebih inklusif, seperti pembuatan kebijakan yang condong kepada pembangunan sosial.
Moderasi beragama bukan berarti menghapus keseluruhan perbedaan yang ada dan meleburkannya menjadi satu. Moderasi juga bukan dimaksudkan untuk menghilangkan identitas dalam suatu kelompok masyarakat. Sebaliknya, moderasi beragama hadir untuk bisa memberikan pengakuan dan penghargaan satu sama lain antar umat beragama di dalam suatu negara.
Negara juga memiliki peran penting untuk mensosialisasikan hal ini, salah satunya adalah dengan membuat kebijakan yang dapat mempromosikan nilai-nilai keagamaan baik secara nasional maupun internasional. Selain intervensi dari pemerintah, masyarakat itu sendiri juga memiliki peran dalam menerima, mensosialisasikan, dan juga ikut membudayakan akulturasi antara kebudayaan lokal dan ajaran agama. Sehingga tercapailah tujuan awal dari 'Moderasi Beragama' tersebut.
Moderasi beragama di Indonesia juga dapat dicontohkan melalui sejarah, ketokohan dan strategi Walisongo dalam menyebarkan Islam di tanah nusantara. Seperti yang telah diketahui banyak orang, bahwasanya Walisongo memiliki strategi yang unik dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Strategi yang mereka lakukan juga tidak sekedar memberikan dampak kepada meluasnya ajaran Islam, namun juga berkontribusi dalam pengembangan dan pembangunan sosial masyarakat Indonesia. Keterkaitan antara budaya, agama, dan teori pengembangan masyarakat berdasarkan perspektif sosiologi akan kami jelaskan secara lebih lanjut sebagai berikut.
Konsep Budaya
Pertama-tama, kebudayaan secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta. Dari akar kata tunggal 'Buddhi' dan jamaknya adalah 'buddhayah' yang dapat diartikan menjadi 'akal budi' atau 'pikiran'. Adapun istilah culture yang merupakan istilah bahasa asing sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata Latin yaitu, 'colere'. Artinya mengolah atau mengajarkan, khususnya mengajarkan cara mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu colere dan culture, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam.
Pengertian lain juga dikemukakan oleh Gillin, ia berpendapat bahwa kebudayaan adalah sebuah konsep kehidupan yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan yang terstruktur yang dimiliki individu tertentu yang membentuk grup atau kategori sosial tertentu. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan elemen sosial yang juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial yang terikat dengan aspek pembangunan masyarakat dan menjadi nilai yang sulit untuk diubah.
Konsep Agama
Agama itu sendiri diyakini sebagai sebuah keyakinan yang mengatur manusia berdasarkan nilai dan praktik keagamaan dengan tujuan memperbaiki segala sikap dan tingkah laku manusia, baik terhadap hubungannya dengan tuhan, hubungannya dengan sesama manusia dan juga hubungannya dengan alam serta makhluk hidup lainnya. Agama seringkali berbicara tentang moralitas, tata cara beribadah, ritual ataupun aturan-aturan kehidupan. Beberapa orang juga mendefinisikan agama sebagai sebuah doktrin spiritual yang mempengaruhi seseorang dalam bertindak, khususnya dalam lingkup transenden (religius) dan sosial.
Agama tercipta dan terbagi menjadi beberapa dimensi. Setiap agama memiliki karakteristiknya masing-masing. Perbedaan paling significant terlihat dari kitab suci dari masing-masing agama. Selain itu, tokoh agama juga menjadi perbedaan terbesarnya. Dalam hal ini, Walisongo adalah contoh dari tokoh-tokoh agama yang berasal dari agama Islam.
Sejarah Penolakan Walisongo
Walisongo mulai menyebarkan ajaran Islam pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Mereka aktif menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa dan sekitarnya. Wilayah tersebut dahulu menjadi pusat pemerintahan di Nusantara, sehingga Walisongo merasa perlu untuk menyebarkan ajaran Islam di pusat kota. Namun, perjuangan itu tidak mudah untuk dilewati. Selama berjuang menyebarkan ajaran agama Islam, Walisongo sering sekali mendapat sikap defensifitas dari berbagai kalangan. Alasan penolakan tersebut datang adalah karena masyarakat Indonesia telah tumbuh erat bersama dengan kebudayaan daerahnya, mulai dari tata krama, gaya bahasa, kesenian dan lain sebagainya, hampir semua disosialisasikan berdasarkan pertimbangan kebiasaan dan kebudayaan masyarakat setempat. Sehingga sulit dan sangat wajar jika dipertentangkan. Beberapa pihak yang menolak kehadiran Walisongo saat itu, diantaranya:
- Masyarakat Adat
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya masyarakat Indonesia sebelum ajaran Islam datang adalah masyarakat yang lebih menjunjung tinggi adat dan tradisi. Yang mana beberapa adat dan tradisi tersebut memiliki nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya seperti praktik dukun yang seringkali menggunakan sesajen, dimana sesajen dinilai bertentangan dengan prinsip Islam. Ajaran Islam menganggap sesajen sebagai hal 'musyrik' yang menyekutukan kuasa Tuhan.
- Para Penguasa
Para penguasa pada saat itu beragama Hindu-Budha. Serupa dengan apa yang terjadi di Prancis era pra-revolusi dimana negara dapat dengan leluasa memanipulasi gereja. Masyarakat pun hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh gereja. Di Indonesia, hubungan antar negara dan agama juga sama seperti di Prancis.
Namun, setelah Islam mulai disebarkan ada banyak perubahan moral di kalangan masyarakat, yang membuat para penguasa takut dan merasa terancam sebab kehilangan kekuasaannya. Ini terjadi karena ajaran agama selalu mementingkan tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Penguasa yang saat itu haus akan rasa takut rakyat dan memiliki hasrat untuk menaklukan atau membuat tunduk rakyatnya jelas tidak senang dengan keberadaan ajaran agama Islam.
- Pemuka agama tradisional
Pihak selanjutnya yang juga menolak ajaran agama Islam datang dari pada pemuka agama tradisional. Mereka tentu saja akan menolak ajaran baru yang bernuansa sangat berbeda dari apa yang selama ini mereka imani. Selain takut tersingkir, mereka juga merasa bahwa ajaran agama merekalah yang paling benar, dan yang lainnya salah. Maka jika ajaran tersebut adalah ajaran yang salah, jelas tidak boleh disebarluaskan kembali.
Tokoh dan Strategi Walisongo
Meskipun dihadang dengan berbagai ujian dan penolakan, Walisongo tidak goyah begitu saja. Mereka tetap teguh dalam visinya untuk menegakkan ajaran Islam di Indonesia. "Walisongo" sendiri terdiri dari dua kata, yaitu "wali" yang berarti "orang suci" atau "wali Allah", dan "songo" yang berarti "sembilan". Jadi, secara harfiah, "Walisongo" berarti "sembilan wali Allah". Istilah ini digunakan untuk menghormati dan mengenang jasa para tokoh ulama tersebut dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut.
Sembilan orang Walisongo ini menyebarkan ajaran agama Islam di berbeda-beda wilayah. Berikut adalah persebaran wilayah dakwah Walisongo, yaitu:
- Sunan Gresik (atau Maulana Malik Ibrahim): Berdakwah di Gresik, Jawa Timur.
- Sunan Ampel (atau Raden Rakhmat): Berdakwah di Surabaya, Jawa Timur.
- Sunan Giri (atau Raden Paku): Berdakwah di Bukit Giri, Jawa Timur.
- Sunan Drajat (atau Raden Qosim): Berdakwah di Tuban, Jawa Timur.
- Sunan Kudus (atau Ja'far Shodiq): Berdakwah di Kudus, Jawa Tengah.
- Sunan Kalijaga (atau Raden Said): Berdakwah di Demak, Jawa Tengah.
- Sunan Muria (atau Raden Umar Said): Berdakwah di Jepara, Jawa Tengah.
- Sunan Gunung Jati (atau Syarif Hidayatullah): Berdakwah di Cirebon, Jawa Barat.
Seperti yang sudah dijelaskan, eratnya hubungan masyarakat Indonesia dengan budaya serta kebiasaan setempat, membuat Walisongo harus memutar otak dan menciptakan strategi secerdas dan sekreatif mungkin dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan meng-akulturasi kebudayaan Indonesia dengan ajaran agama. Berikut beberapa ciri strategi dakwah atau pendekatan atau metode yang dilakukan oleh Walisongo.
- Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim): Salah satu ciri khas dakwahnya adalah melalui pendekatan kultural dan pemberdayaan ekonomi. Beliau dikenal aktif dalam perdagangan dan pengembangan pertanian, serta membangun pesantren yang menjadi pusat pendidikan agama dan penyebaran Islam di wilayah Gresik.
- Sunan Ampel (Raden Rakhmat): Sunan Ampel dikenal dengan pendekatan tasawuf atau mistisisme dalam dakwahnya. Beliau menekankan pentingnya pengalaman spiritual dan kesederhanaan dalam mencapai kedekatan dengan Allah.
- Sunan Bonang (Raden Makdum Ibrahim): Ciri khas dakwah Sunan Bonang adalah melalui seni dan kesenian, terutama dalam bentuk tari, nyanyian, dan pentas wayang. Pendekatannya yang kreatif ini membantu menyebarkan ajaran Islam secara lebih luas di masyarakat Jawa.
- Sunan Drajat (Raden Qosim): Salah satu ciri khas Sunan Drajat adalah kesederhanaan dalam gaya hidup dan pendekatan yang ramah terhadap masyarakat setempat. Beliau terkenal dengan ketaatannya pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
- Sunan Kudus (Ja'far Shodiq): Sunan Kudus dikenal dengan pendekatannya yang berorientasi pada pendidikan dan pembinaan masyarakat. Beliau mendirikan pesantren dan mempromosikan pendidikan agama Islam sebagai sarana untuk membangun moralitas dan kepatuhan terhadap ajaran Islam.
- Sunan Giri (Raden Paku): Ciri khas dakwah sunan Giri adalah pendekatannya cenderung kearah peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Beliau mendorong umat Islam untuk berkontribusi dalam membangun komunitas yang lebih baik, melalui berbagai upaya seperti pengembangan ekonomi lokal, bantuan kepada yang membutuhkan, dan pengorganisasian kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat.
- Sunan Kalijaga (Raden Said): Ciri khas dakwah Sunan Kalijaga adalah pendekatannya yang inklusif dan toleran terhadap kepercayaan dan budaya lokal. Beliau menggunakan bahasa dan simbol-simbol yang dikenal oleh masyarakat Jawa untuk menyampaikan ajaran Islam.
- Sunan Muria (Raden Umar Said): Salah satu ciri khas Sunan Muria adalah fokusnya pada pengembangan pertanian dan pertanian terpadu. Beliau dikenal aktif dalam membantu masyarakat setempat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan ekonomi.
- Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah): Sunan Gunung Jati dikenal dengan kebijaksanaannya dalam diplomasi dan politik. Beliau berhasil membangun hubungan baik dengan penguasa setempat dan memperluas pengaruh Islam di wilayah Cirebon.
Dengan berbagai ciri khas ini, para Walisongo berhasil menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa dan sekitarnya dengan metode yang beragam dan efektif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Strategi Walisongo dan Perspektif Sosiologi
Di dalam perspektif sosiologi, ada sebuah konsep yang dinamakan dengan konsep pembangunan sosial. Dimana dalan konsep tersebut dijelaskan bahwa pembangunan sosial memerlukan setidaknya 4 strategi dalam pelaksanaanya.
- Strategi Pembangunan (growth strategy)
Strategi pertumbuhan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi secara cepat melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas pertanian, permodalan, dan perdagangan, serta kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
- Strategi Kesejahteraan (welfare strategy).
Strategi kesejahteraan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan budaya dan kultur untuk menghindari ketergantungan pada pemerintah.
- Strategi Yang Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat (responsive strategy)
Dengan membeli teknologi dan sumber daya yang sesuai untuk kebutuhan proses pembangunan, strategi ini bertujuan untuk menanggapi kebutuhan yang dibuat oleh masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (self need and assistance).
- Strategi Terpadu Atau Strategi Yang Menyeluruh (integrated or holistic strategy)
Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan semua elemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan pertumbuhan berkelanjutan, persamaan, kesejahteraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan masyarakat.
Strategi yang diadakan oleh Walisongo ternyata dapat dijelaskan secara sosiologis. Dimana tak hanya meningkatkan jumlah muslim di Indonesia strategi yang dilakukan oleh walisongo juga telah ikut serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan sosial masyarakat. Fakta bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Walisongo merupakan penerapan konsep sosiologis, juga memberikan informasi tambahan bahwa tak hanya sebagai pemuka agama, para tokoh Walisongo juga merupakan seorang sosiolog sejati.
Beberapa keterkaitan antara apa yang dilakukan oleh Walisongo dan apa yang menjadi teori sosiologi, dijelaskan sebagai berikut.
- Sunan Gresik dan Sunan Muria, merupakan dua tokoh yang sama-sama menerapkan Growth Strategy. Kedua tokoh ini berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat.
- Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri dan Sunan Kalijaga serta Sunan Kudus menerapkan Welfare Strategy. Beberapa tokoh ini berkontribusi dalam pembangunan sosial yang lebih luas, ada yang berfokus kepada pendidikan, kesenian, partisipasi masyarakat dan juga kegiatan sosial.
- Sunan Kudus juga termasuk tokoh yang menerapkan sistem responsive strategy. Sunan Kudus memilih jalan pendidikan, dengan harapan agar manusia Indonesia menjadi individu yang cerdas sehingga tidak lagi mudah ditipu dan bergantung kepada orang lain.
- Terakhir, Sunan Ampel, Sunan Drajat, merupakan tokoh-tokoh yang menerapkan integrated or holistic strategy. Para ahli tasawuf ini tentu memahami berbagai cara baim sosial maupun kesenian dalam upaya oengembangan masyarakat. Namun, mereka juga tidak lupa mengajarkan ilmu tasawuf, sehingga segala macam ilmu yang telah diajarkan kepada tiap-tiap individu tidak digunakan untuk ham hak buruk. Dengan menyatukan keseluruhan ilmu, tasawuf dalam dijadikan pegangan agar selalu ingat pada nilai-nilai moral yang ada, dan terhindarkan dari ambisi fana yang akan merugikan manusia.
Maka dari sini, kami dapat menyimpulkan bahwa ada korelasi antara strategi penyebaran ajaran Islam di Indonesia yang dilakukan oleh Walisongo dengan perspektif sosiologi tentang konsep pembangunan sosial. Hubungan antara strategi Walisongo dalam menyebarkan Islam dengan pembangunan sosial dapat menjadi point-point seperti dibawah ini:
- Inklusifitas dan Toleransi: Strategi Walisongo yang inklusif dan toleran terhadap keberagaman budaya dan agama membantu membangun hubungan yang harmonis antara umat Islam dengan masyarakat lokal. Hal ini mendorong pembangunan sosial yang inklusif, dimana berbagai kelompok masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai tanpa adanya konflik agama atau budaya.
- Pendidikan dan Pemberdayaan: Walisongo sangat menekankan pentingnya pendidikan dalam menyebarkan Islam. Dengan mendirikan pesantren dan madrasah, mereka tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pendidikan.
- Pembangunan Ekonomi Lokal: Beberapa Walisongo juga terlibat dalam pembangunan ekonomi lokal dengan mempromosikan perdagangan, pertanian, dan pengembangan ekonomi lainnya.
Secara keseluruhan, strategi Walisongo dalam menyebarkan Islam tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Hal ini membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif, berpendidikan, dan sejahtera secara sosial.
Penulis: Intan Dwi Rahmawati -Universitas Negeri Jakarta
Daftar Pustaka
Mahdayeni., Alhaddad Roihan, M., & Saleh Syukri, A. (2019). MANUSIA DAN KEBUDAYAAN (MANUSIA DAN SEJARAH KEBUDAYAAN, MANUSIA DALAM KEANEKARAGAMAN BUDAYA DAN PERADABAN, MANUSIA DAN SUMBER PENGHIDUPAN). _TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 7(2). Halm: 157.
Mahendra, A. (2013). PENDEKATAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI INDONESIA. JMS: Jurnal Multi Sains. 4(4). Halm: 35-36.
Syalafiyah, N., & Budi, H. (2020). Walisongo: Strategi Dakwah Islam di Nusantara. J-KIS: Jurnal Komunikasi Islam. 1(2). Halm: 169-175.
Masyitoh, R. (2022). STRATEGI DAKWAH WALISONGO DI NUSANTARA. Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman. 5(2). Halm: 112-122.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI