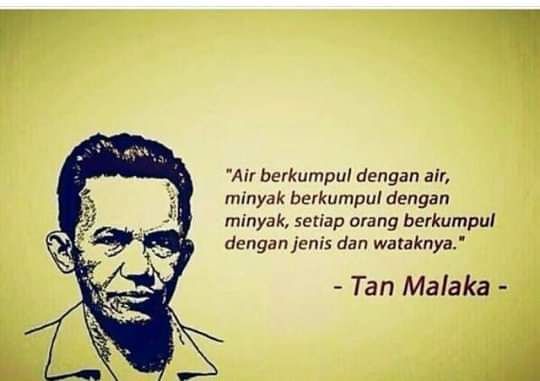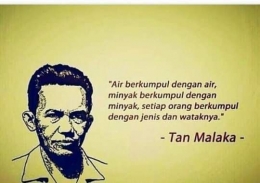Banyak masyarakat Indonesia telah mengidap sebuah penyakit bernama cebong-kampret. Kalau diurut, penyakit ini dimulai dari Pilpres 2014, lalu kambuh pada Pilkada DKI, dan semakin parah pada Pilpres 2019 serta kembali menggema saat pengesahan RUU Omnibus Law kemarin.
Pola dari penyakit ini selalu sama, yaitu saat kita mengkritik pemerintah, kita akan dituduh sebagai kampret. Tapi kalau memuji kerja pemerintah, maka kita akan dianggap anggap sebagai cebong.
Penyakit ini, jika dihitung dari 2014-2020, maka sudah berlangsung selama 7 tahun. Melihat hal itu, saya lantas bertanya-tanya: apa penyebap dari penyakit cebong-kampret ini?
Setelah merenung beberapa saat, saya mendapatkan jawabannya. Setidaknya, menurut saya, ada dua penyebab orang bisa mengidap penyakit: "bangga jadi cebong dan bahagia jadi kampret."
Penyebab yang pertama adalah kesempitan berpikir. Kesempitan berpikir adalah kecenderungan orang untuk memutlakan pandangan sendiri, dan menolak untuk melihat dari sudut pandang orang lain.
Kesempitan berpikir semacam ini sering ditandai dengan kurangnya empati, yakni kemampuan untuk merasakan apa yang mungkin dirasakan orang lain.
Akibatnya, orang tersebut tidak mampu mempertimbangkan pandangan orang lain. Ia lalu merasa paling benar, walaupun tak sungguh berpijak pada akal sehat, ataupun kenyataan yang ada.
Kesempitan berpikir semacam ini terlihat dalam narasi-narasi yang sering dibangun oleh kelompok cebong dan kampret. Yang kubu cebong merasa bahwa pemerintah Jokowi tak pernah salah, sedangkan yang kubu kampret merasa pemerintah tak pernah benar.
Jika kita membiarkan kesempitan berpikir semacam ini terus dibiarkan, orang akan jatuh pada penyakit selanjutnya, yaitu fanatisme buta.
Penyebab kedua adalah fanatisme buta. Fanatisme semacam ini tidak tiba-tiba muncul. Ia adalah hasil dari kesempitan berpikir. Fanatisme buta yang saya maksud adalah suatu sikap ekstrem di dalam memeluk pandangan tertentu, serta bersedia melakukan apapun atas nama pandangan yang dianut tersebut.
Seseorang yang sudah jatuh pada fanatisme buta, akan selalu melihat manusia lain tidak sebagai manusia, melainkan sebagai sesuatu yang harus disingkirkan.
Tak heran, kubu cebong-kampret selalu mengucapkan kalimat-kalimat seperti: Tembak saja kelompok radikal, bunuh saja orang itu, dasar kafir, dasar komunis, dan lain sebagainya.
Orang-orang itu, meskipun mengaku beragama, mereka sesungguhnya sedang kehilangan sisi kemanusiaannya. Lantas, dari mana cara pandang semacam itu lahir?
Cara pandang semacam itu sebetulnya dibentuk oleh prasangka yang lahir dari dendam dan trauma atas kejadian negatif yang pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, penutupan gereja, bom gereja, pembubaran organisasi HTI, dan lain sebagainya.
Karena telah dibayang-bayangi oleh prasangka dan dendam, mereka akhirnya tidak lagi melihat dunia secara jernih, melainkan secara hitam-putih. Bagi mereka, siapa pun yang berada di luar kelompoknya wajib dibasmi atau dimusnahkan.
Kesempitan berpikir dan fanatisme buta ini sering kali terjadi pada banyak hal. Dalam konteks Indonesia, yang paling menguat dan menonjol adalah fanatisme buta pada tokoh politik dan agama.
Sadar atapun tidak, fanatisme semacam itu telah menghambat dan membelah masyarakat Indonesia yang terkenal majemuk ini.
Kesempitan berpikir dan fanatisme buta itu kemudian seakan mendapatkan pembenaran ketika kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik membuahkan begitu banyak masalah di tengah masyarakat.
Pembelahan masyarakat menjadi dua kubu seperti cebong-kampret menghasilkan banyak sekali kerusakan sosial yang sulit diperbaiki. Hal itu tentu berbahaya bagi bangsa Indonesia yang majemuk ini.
Sayangnya, banyak pihak justru mempertahankan hal tersebut untuk meraub keuntungan. Baik keuntungan berupa dukungan politik, materi, dan lain sebagainya.
Hal-hal itu bisa terlihat dari sejumlah kasus intoleransi dan kriminalisasi yang selama ini terjadi. Kasus-kasus intoleransi dan deskriminasi terkesan disepelekan. Tak heran, dalam proses penyelesaiannya selalu lamban.
Akibat dari lambannya merespons hal-hal semacam itu, kita akhirnya terperosok ke dalam "lingkaran setan" yang makin berdampak pada kerusakan sosial yang makin parah.
Kita tahu, lambannya merespons hal-hal semacam itu disebab karena adanya kalkulasi politik dari para pemangku kebijakan dan penegak hukum. Artinya, pemerintah bertindak bukan atas dasar perintah undang-undang, melainkan hitung-hitungan politik.
Dalam kebikan publik kita pun demikian. Banyak sekali kebijakan publik yang justru menghasilkan ketidakadilan. Sering kali, para pemangku kebijakan lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi daripada manusia itu sendiri. Penggusuran terhadap masyarakat adat Besipae di NTT dan Kanipan di Kalimantan adalah contohnya.
Apakah hanya itu? Tidak. Sistem demokrasi yang sering diagungkan oleh pemerintah hanya berhenti pada demokrasi prosedural. Melaksanakan Pilkada di tengah pandemi adalah contoh paling faktual.
Banyak orang sudah mengajukan kritik pada masalah-masalah semacam itu, tapi seperti biasa, mereka justru diserang oleh para buzeer dan "relawan kekuasaan" yang berpikiran sempit serta fanatisk buta.
Hal-hal itu terlihat jelas pada beberapa hari lalu, ketika RUU Omnisbus Law disahkan oleh DPR. Banyak orang tahu bahwa RUU Omnibus Law itu disahkan lewat prosedur yang cacat hukum.
Akan tetapi, banyak orang kembali dibungkam oleh para relawan kekuasaan yang berpikiran sempit dan fanatisme buta. Mereka lalu menuduh orang-orang yang mengajukan kritik tersebut sebagai kampret, atau orang-orang yang ingin menggulingkan pemerintahan Jokowi dan sebagainya.
Tuduhan-tuduhan semacam itu juga berlaku sebaliknya. Saat kita mengkritisi orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik, kita sering dituduh sebagai cebong yang suka menjilat. Padahal, kita tak masuk dalam kelompok mana pun. Yang kita tahu, jika salah, ya perlu dikoreksi atau dikritisi.
Melihat tuduhan-tuduhan dari kubu cebong-kampret, saya akhirnya berkesimpulan bahwa kubu cebong-kampret itu ibarat pinang dibelah dua.
Kedua kelompok itu, sepintas kelihatan berbeda dan berlawanan, tapi sesungguhnya sama saja. Mereka adalah orang-orang yang berpikiran sempit dan fanatik buta pada kelompok, agama, maupun tokoh tertentu.
Oleh karena itu, tak heran bila kedua kubu tersebut selalu termakan hoaks dari kubu pemerintah yang sering disebar oleh para buzzer, maupun kubu yang selalu menggunakan agama untuk kepentingan politik.
Sekali lagi, melihat kejadian demi kejadian serta narasi cebong dan kampret; saya akhirnya berkesimpulan bahwa kedua kubu tersebut sesungguhnya bukan lagi dua, melainkan satu.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H