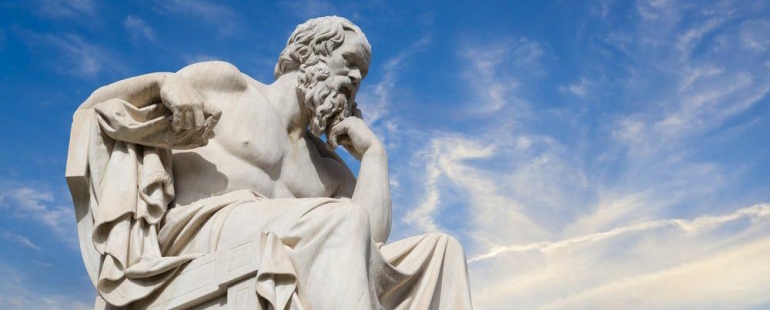“Apakah kau tidak setuju bahwa dalam diriku, aku mempunyai semangat nubuat sebesar semangat yang dimiliki angsa-angsa? Karena angsa-angsa itu, ketika memersepsi bahwa mereka pasti akan mati, setelah bernyanyi sepanjang hayatnya, lantas mereka bernyanyi lebih riang lagi dari sebelumnya, bergembira karena akan segera pergi menuju Tuhan yang para menterinya adalah mereka sendiri. Tetapi manusia, karena mereka sendiri takut akan kematian, mulai menebarkan fitnah bahwa angsa-angsa menyanyikan ratapan menjelang akhir hidupnya. “
Tuturan bernada nubuat di atas, diungkapkan Socrates menjelang kematiannya—ia harus minum racun sebagai hukuman atas perbuatannya mengajarkan filsafat. Si lebah penyengat kuda-kuda malas Yunani ini, tanpa gentar sedikit pun menghadapi kematian. Karena, sang filsuf sejati—seperti tercatat dalam Dialog Phaedo karya Plato, sang murid terkasihnya—adalah mereka yang justru gembira dengan kematian. Melalui kematianlah Sang filsuf bisa dengan lebih leluasa membebaskan jiwanya dari pengaruh ragawi, kejahatan dan nafsu tubuh. Kerena berfilsafat, kata Socarets, adalah melatih diri untuk mati.
Gajah mati meningalkan gading, Socrates mati meninggalkan inspirasi. Memang benar, kematiannya memberi inspirasi bagi para muridnya. Sistem pemerintahan demokrasi adalah penyebab Socrates harus menjalani hukuman tersebut. Dengan suara terbanyak dari anggota Dewan Polis Yunani yang sakit hati akibat ulahnya, sudah cukup untuk membuat Socrates bungkam selamanya. Tapi ternyata orang bisa saja membungkam kata-kata yang keluar dari mulutnya , tapi tak pernah bisa menghentikan aliran ide-idenya. Ajaran Socrates terlanjur dikenal banyak orang, mengalir deras kepada mereka yang terbuka akal budinya.
Dan ajaran Socrates, sampai jaman ini, tetap abadi, bisa kita baca melalui tulisan tangan Plato. Kematiannya sendiri bukanlah suatu hal yang sia-sia, cukup membuat banyak orang tersentakkan kesadarannya. Cukup untuk membuat orang-orang bertanya secara lebih mendasar, gerangan kehidupan seperti apakah yang layak dilakoninya. Karena—lagi-lagi merujuk kata-kata Socrates—hidup yang tak terperiksa tak layak dilakoni.
Perasaan apakah yang hinggap merayap manakala seseorang dihentakkan begitu saja dari alunan kesehariannya? Manakala tiang sandaran diri dan penyangga hidupnya terlepas tiba-tiba, dengan sebab kematian seseorang yang dicintai, kehilangan mata pencaharian, atau keruntuhan ideologi yang dianutnya. Cemas, terasing dan takut. Perasaan-perasaan yang paling dasar pada diri manusia. Saat perasaan ini muncul, saat itu juga momen yang tepat bagi manusia untuk sejenak menyembul dari ketenggalam rutinitasnya, inilah saat yang tepat untuk bertanya dengan lebih mendasar, menengok ke palung paling dalam dirinya sendiri.
Ada sekian peristiwa besar dunia, yang membawa hembusan angin kematian. Bencana alam, perang dunia, wabah penyakit, setidaknya telah mengguncangkan kesadaran manusia terkait eksistensi dirinya. Pertanyaan eksistensial, adalah nama bagi aneka ragam lintasan teka-teki yang ingin dijawab terhadap apa dan bagaimana kehidupan yang harus dilakoninya. Pergulatan akan pertanyaan eksistensial ini, melahirkan sekian banyak filsuf, baik yang profan maupun yang profetik. Bukankah mereka yang disebut para filsuf, adalah mereka yang tanpa mengenal lelah bergulat dengan pertanyaan eksistensial ini.
Bolehlah kita beranggapan, tanpa kematian Socrates, guru terkasihnya, Plato tak mungkin menggubah sekian banyak dialog filosofis yang membongkar seluk beluk diri, keluarga, pengetahuan, kebenaran, kehidupan setelah mati, yang semunya diharapkan menjadi pegangan bagi manusia di masanya. Peristiwa kematian sang Guru, bagi Plato adalah palu godam yang menggedor kesadaran dirinya, hinga ia bisa mempunyai daya tahan untuk menyibak dan menelisik ragam pertanyaan ini.
Peperangan, adalah salah satunya. Kematian masal yang diakibatkannya, kengerian yang timbul, penderitaan dan rasa sakit, kehilangan dan ketercerabutan, setidaknya membuat orang-orang mulai memikirkan keberadaan, eksistensi dirinya di dunia ini. Ada sekian filsuf yang terlahir dari pengalaman genuine dirinya menghadapi peperangan, akrab dengan kematian demi kematian orang-orang disekitarnya. Descartes, umpamanya, sebagian besar masa hidupnya berada pada masa perang Bavaria.
Socrates, sudah dipastikan adalah seorang prajurit yang berani di peperangan Athena dan Sparta. Wittgenstein, menyusun filsafatnya dalam buku Tractatus-Logico-Philosophicus di parit-parit perlindungan pada kecamuk Perang Dunia I. Bertrand Russel, Sartre, dan bahkan para filsuf awal posmodernisme, adalah mereka yang menolak peperangan, mencoba mengadili para penjahatnya, kalaupun tidak, mereka adalah para demonstran yang gigih.
Setelah Perang Dunia II, di daratan Eropa sebagai arena peperangan, tempat adu jotos ideologi, pertarungan kebesaran rasial, dan nasionalisme yang cupet, bekembang dua aliran filsafat. Kedua aliran ini bersepakat untuk menggempur irasionalitas manusia yang telah menyebabkan kejahatan, peperangan dan penderitaan berkepanjangan.
Tapi keduanya berada pada jalur yang berseberangan. Pertama, aliran positivisme logis, yang mendasarkan diri pada filsafat awal Wittgenstein, yang bisa dilacak terus pada David Hume dan para penganut empirisme khas Inggris. Aliran ini membanggakan diri karena bijaksana dan praktis, ilmiah dan tidak mentolerir segala omong kosong. Aliran kedua adalah eksistensialisme, yang berakar pada Kierkgaard dan Nietzcshe, dan fenomenologi Husserl sebagai metodologinya.