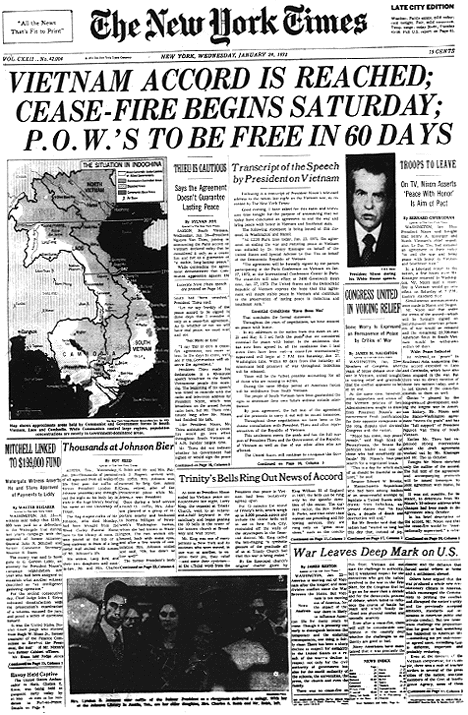[caption caption="Tolikara dari udara (Okezone)"][/caption]
"Kalau judul seperti itu besok naik cetak, saya berhenti dari sini."
Di suatu sore di tahun 2008 saya menegaskan kalimat itu dalam rapat bujet di perusahaan surat kabar harian di Kalimantan Timur (Kaltim) tempat saya bekerja sampai sekarang. Rapat bujet adalah pertemuan petinggi operasional setiap sore untuk menentukan bersama-sama topik atau berita apa yang akan diterbitkan di edisi besok berdasarkan berita yang telah terkumpul dari para reporter hari itu. Di hadapan saya ada pemimpin redaksi, direktur operasional, manajer pemasaran, manajer iklan, manajer sirkulasi dan para redaktur kompartemen. Saat itu saya masih menjabat sebagai redaktur pelaksana atau managing editor.
Menjelang Pilkada Kaltim 2008 situasi sosial politik di Kaltim memanas. Situasi makin ruwet ketika percaturan politik ini diwarnai dengan sentimen etnis. Baik dari para calon, parpol, pendukung sampai ke penyelenggara. Beberapa kelompok etnis yang berbeda sempat head to head di jalan raya siap bentrok. Isu akan terjadinya serangan ke kawasan yang didominasi etnis tertentu bergulir hampir setiap hari.
Tapi, seringkali 'memanas' artinya uang tambahan buat media. Ketika situasi tak menentu masyarakat akan mencari asupan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, atau setidaknya referensi untuk bertindak. Kebutuhan ini membuat pembeli koran makin banyak. Otomatis jumlah oplah meningkat. Oplah naik artinya uang pemasukan dan iklan bertambah. Tak ada perusahaan media yang tak butuh uang.
Sore itu redaktur melaporkan situasi sosial politik terkini yang didapatkan reporternya di lapangan. Ketegangan dua etnis besar di Kaltim nyaris pada puncaknya. Bahkan sudah ada kubu yang menyeret isu agama. Para petinggi koran yang berurusan dengan omzet, oplah dan uang berpendapat ini adalah saat paling tepat mengambil momen. Momen adalah kata lain dari uang dan oplah.
Mereka minta berita ditulis dengan judul yang 'eye catching' dan konten yang -- mereka sebut -- bisa bikin merinding. Karena menurut mereka, makin merinding makin laku. Mereka minta berita ditulis apa adanya, begitu pula nama etnis yang selama ini tidak ditulis eksplisit, agar ditulis apa adanya. Dalam rangkaian peristiwa politik ini, redaksi sangat berhati-hati memilih sudut pandang berita, memilih fakta lapangan dan gaya penulisan laporan. Tujuannya agar situasi tak memburuk dan demi keselamatan jiwa para reporter di lapangan. Dalam situasi seperti ini yang netral pun bisa salah, yang mencoba melerai pun bisa kena pukul. Tapi tampaknya para petinggi koran yang berurusan dengan uang sudah gemas. Karena dalam beberapa minggu rangkaian peristiwa ini redaksi dianggap tidak kunjung membuat berita yang bisa bikin 'menggigil'. Koran gagal dapat uang lebih banyak dari peristiwa yang mungkin hanya akan terjadi sekali dalam satu dekade ini. Jadi mereka berpendapat edisi selanjutnya adalah saatnya berita ditulis apa adanya: nama etnis ditulis, kemarahan dideskripsikan, rumor digulirkan, pernyataan sentimen tokoh adat ditulis lengkap, dst.
Perdebatan sengit itu saya akhiri dengan pernyataan paling atas, kemudian keluar ruang rapat. Di akhir rapat pemimpin redaksi memberitahu saya bahwa ia memutuskan tetap pada pola pemberitaan yang sebelumnya yang tak memanas-manasi. Kepentingan omzet dan laba harus mengalah dulu. Saya bersyukur. Di akhir tahun, ia menyerahkan jabatannya kepada saya yang saat itu masih berusia 27 tahun.
JURNALISME 'WHAT NEXT?'
Hidup di daerah dengan potensi letupan antaretnis seperti di Kaltim sebagai seorang wartawan, sangat membantu saya mengasah kepekaan. Setiap tahun rata-rata terjadi 3-4 kali letupan serupa dalam berbagai skala. Menulis dan menyunting berita tak cukup lagi 5W1H (what, who, why, when, where, how). Tapi yang terpenting adalah 'what next'. Apa yang akan terjadi setelah berita terbit. 'What next' memerlukan visi, cita-cita, analisa, kepekaan dan kearifan. 5W1H adalah wilayah kompetensi seorang wartawan. Sedangkan 'What next' adalah wilayah moral, kecerdasan sekaligus kecerdikan.
Kawan-kawan reporter atau kontributor Kaltim dari media Jakarta sering mengeluh. Laporan yang menyangkut konflik antaretnis yang mereka kirim ke redaktur di Jakarta seringkali diterbitkan 'sangat apa adanya'. Jadi, seringkali berita online tentang konflik antaretnis di Kaltim diberitakan sangat bombastis di media online Jakarta. Meski prihatin, saya maklum karena petinggi atau redaktur perusahaan berita tidak bersentuhan langsung dengan situasi riil. Mereka tak punya kepekaan, atau mungkin tak punya kepedulian bila berita itu bisa jadi bahan bakar tambahan kemarahan di lapangan.
Dalam teori klasik jurnalistik yang menekankan penyajian fakta apa adanya, itu tidak salah. Tapi jurnalistik juga mengajarkan nilai sebuah fakta. Kalau Anda punya istri 4 lalu menabrak orang di jalan, tentu akan menganggap judul ini sampah: "Seorang Pria Beristri 4 Menabrak Orang sampai Tewas". Anda punya istri 4, itu fakta. Tapi dalam peristiwa yang diberitakan, fakta itu tak bernilai -- meski ia eye catching. Dalam kasus konflik antaretnis, nilai fakta itu ditimbang secara cermat dampaknya. Nilai fakta itu adalah pergulatan moral bagi mereka yang membuat laporan dan menyunting berita. Bagi perusahaan media, nilai fakta itu adalah ujian bagi cita-cita media itu sendiri.
Mungkin sebagian orang akan berpendapat media atau orang seperti saya adalah jurnalis pengecut atau bernyali rendah. Tapi dalam merumuskan 'What Next?', salah satu pertanyaan terpentingnya adalah 'siapa yang dirisikokan?'. Risiko kantor akan diserang orang atau diancam, itu risiko kecil dan akan diabaikan. Kalau sudah ada ancaman atau risiko pembunuhan, pasti akan dievakuasi ke luar daerah atau minta perlindungan polisi. Begitu pula risiko dituntut ke pengadilan atau dilaporkan polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Itu urusan 'remeh'. Risiko yang jangan sampai diambil adalah merisikokan masyarakat.
Tak ada berita yang sebanding dengan risiko keamanan masyarakat dan keselamatan langsung jiwa seorang reporter.
JURNALISME PENGGEBUK
Teori klasik jurnalisme harus berhadapan dengan kemarahan masyarakat Amerika Serikat dalam pemberitaan Perang Vietnam tahun 1960-an. Gaya jurnalisme Amerika yang terkenal disiplin dengan fakta menyajikan foto dan berita heroisme perang pihak AS secara maraton dan bersama-sama. Ditambah, pers AS ketika itu bertransformasi menjadi authoritarian press sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengampanyekan perang. Sementara jumlah korban di pihak AS makin bertambah, APBN terkuras. Masyarakat ingin perang diakhiri dan anak-anak mereka dipulangkan dari medan perang. Tapi pemerintah dan media seolah terus membakar sentimen nasionalisme itu lewat nafsu bertempur. Akhirnya mereka kelelahan sendiri dan pulang tanpa membawa kemenangan.
[caption caption="Halaman muka salah satu surat kabar terkenal Amerika Serikat di era Perang Vietnam (New York Times)"]

Sosiolog Norwegia Johan Galtung memperkenalkan istilah Peace Journalism atau Jurnalisme Damai di awal 1970 setelah ia menyelesaikan Journal of Peace Research di tahun 1964. Sebagai bocah yang turut jadi korban Perang Dunia II, Galtung merasakan konflik atau perang sebagai peristiwa yang saling menihilkan. Tak ada yang di tengah. Yang ada hanya kita-mereka, kalah-menang, dehumanisasi dan siklus tanpa ujung soal siapa yang pertama 'melempar batu'. Kenyataannya perang selalu diputuskan di balik meja oleh orang-orang berdasi dalam ruang berpendingan yang seumur hidupnya tak pernah pegang senjata. Kenyataannya, mereka yang menderita adalah para warga di daerah konflik, pengungsi, anak-anak yang kehilangan orangtua dan ibu yang harus merelakan anaknya berperang. Perang tidak akan berhenti sebelum ada yang menang meski keduanya mesti menanggung kerusakan amat parah. Sehingga, perang sebenarnya tidak meninggalkan siapa yang menang atau kalah, tapi siapa yang tersisa.
Jurnalisme Perang akan mengedepankan siapa pihak yang harus disalahkan dan dihukum. Dehumanisasi akan dilancarkan kepada pihak seberang. Propaganda turut dikampanyekan dalam bentuk kebohongan menyangkut pihak lawan dan menutupi kesalahan pihak sendiri. Penyelesaian semata-mata digantungkan pada elite pembuat kebijakan, bukannya sebuah upaya bersama-sama. 'Sebagus-bagusnya' perang, ia tak hanya akan menghabisi orang yang kita benci. Perang kelak akan menjalar ke halaman rumah kita dan menewaskan orang-orang terdekat yang kita kasihi. Sesuatu yang mungkin tak pernah terbayangkan oleh mereka yang sangat bernafsu menghabisi orang lain.
Galtung menawarkan jurnalisme yang berorientasi pada kelangsungan peradaban dan menyoroti penderitaan manusia yang timbul akibat konflik. Orientasi win-win solution mungkin tak bisa tercapai, tapi jurnalisme mesti mendorong untuk membangun dialog yang terbuka agar kekerasan itu segera diakhiri. Bila sebelumnya keputusan menyangkut perang hanya dibuat di ruang-ruang tertutup, maka Jurnalisme Damai harus membuatnya terbuka dengan keterlibatan seluruh masyarakat untuk memutuskan -- atau setidaknya bersuara -- untuk mencapai kembali kedamaian.
Jurnalisme Damai pada akhirnya adalah sebuah jurnalisme dengan pemikiran skeptis mengenai manfaat aksi sebuah konflik dan hikmahnya bagi umat manusia serta masa depan. Ia akan lebih mementingkan nasib korban ketimbang ambisi kemenangan serta memberi porsi yang adil. Terpenting, Jurnalisme Damai adalah jalan bagi pihak yang bertikai menemukan kembali kedamaian. Bukan soal siapa yang salah dan yang benar, tapi siapa/apa yang mesti diselamatkan. Di masa sulit, jurnalisme harus hadir sebagai seorang pelerai, bukan penggebuk.
Jurnalisme Damai tidak pernah mudah. Ia menuntut sandaran moral, kepedulian, kerja keras di lapangan, serta kemampuan menahan diri.
TOLIKARA DAN DEKONTEKSTUALISASI
Keprihatinan saya menjadi-jadi ketika memantau perkembangan berita konflik di Tolikara. Nyaris semua berita tayang dan yang populer adalah berita opini. Opini-opini itu dikutip oleh mereka yang tinggal di luar Tolikara -- mereka yang samasekali tidak bersentuhan dengan peristiwa dan terdampak langsung. Sumber tangan pertama atau saksi mata selalu menempati urutan tertinggi dalam klasifikasi fakta dalam jurnalistik. Saksi mata ini bisa narasumber yang menyaksikan, pelaku, korban terdampak langsung, atau bisa juga wartawan itu sendiri. Jenis berita seperti ini sangat minim saya temukan di pemberitaan Tolikara. Sulitnya medan Tolikara juga membuat sedikit wartawan yang menjangkau daerah itu untuk menyaksikan langsung, apalagi siaran live. Kalaupun ada keterangan tangan pertama, wawancara dilakukan lewat telepon. Bila yang memberi keterangan adalah aparat atau pejabat, cenderung tidak dipercaya. Masyarakat 'bersikukuh' pada persepsi yang sudah mereka bentuk dan sumbernya berasal dari opini -- bukan kesaksian.
Membakar properti orang lain, apalagi tempat ibadah, itu kesalahan besar. Kita semua tahu. Tapi kebanyakan media lebih suka membahas apa yang terjadi di puncak kulminasi peristiwa: pembakaran itu. Sehingga gambar yang mayoritas ditampilkan adalah gambar api dan puing musala.
Menciptakan kebingungan (confusion) sebagai salah satu cara dalam Jurnalisme Perang juga tampak jelas di pemberitaan Tolikara. Tuntutan kecepatan media online untuk menayangkan konten membuat informasi kurang akurat dan sepotong-sepotong. Dalam arena konflik, jenis informasi seperti ini sangat berbahaya. Seperti soal speaker, musala atau masjid, siapa yang ditembak, dll.
Sampai sekarang saya belum mendapat informasi kontekstual soal peristiwa ini: mengapa dan lalu bagaimana. Belum ada informasi yang cukup mengapa GIDI sampai melarang pelaksanaan Salat Ied, pemakaian jilbab dan hubungannya dengan kehidupan beragam di sana sehari-hari. Begitu juga dengan ketiadaan antisipasi aparat setempat. Semuanya kabur dan tak lengkap. Yang berkembang hanya opini, asumsi atau tebakan yang disandarkan pada sentimen agama; dekonstekstualisasi. Jurnalistik masih belum bisa menguraikan konflik Tolikara sebagai lingkaran kekerasan, apalagi mengeksplorasi ide-ide rekonsiliasi. Jurnalisme di pemberitaan Tolikara belum menjadi jurnalisme yang melengkapi prasangka dan fakta. Tapi jurnalisme yang menambahi dugaan dan mengompori.
Tak ada yang bilang bahwa Jurnalisme Damai itu jurnalisme yang mudah dan laku. Sebaliknya, Jurnalisme Perang yang bikin merinding dan menggigil itulah yang bisa menaikkan oplah, rating, trafik dan share. Terlebih dalam situasi terkini sosial politik Indonesia di mana masyarakatnya 'perlu asupan bahan bakar' kebencian dan sentimen antarkelompok. Belakangan, banyak dari kita yang menganggap bahwa dunia ini adalah ladang pertempuran yang tak habis-habis. Tapi dalam setiap konflik, peperangan dan ketegangan, selalu ada segelintir orang yang menangguk untung. Sementara kita semua kalah. (*)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H