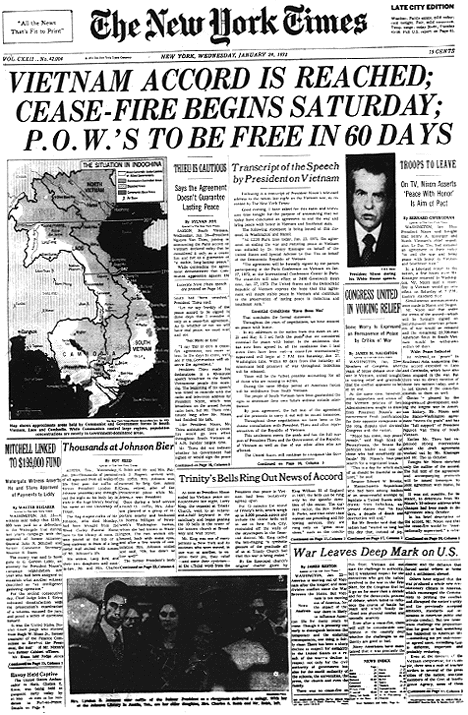Menciptakan kebingungan (confusion) sebagai salah satu cara dalam Jurnalisme Perang juga tampak jelas di pemberitaan Tolikara. Tuntutan kecepatan media online untuk menayangkan konten membuat informasi kurang akurat dan sepotong-sepotong. Dalam arena konflik, jenis informasi seperti ini sangat berbahaya. Seperti soal speaker, musala atau masjid, siapa yang ditembak, dll.
Sampai sekarang saya belum mendapat informasi kontekstual soal peristiwa ini: mengapa dan lalu bagaimana. Belum ada informasi yang cukup mengapa GIDI sampai melarang pelaksanaan Salat Ied, pemakaian jilbab dan hubungannya dengan kehidupan beragam di sana sehari-hari. Begitu juga dengan ketiadaan antisipasi aparat setempat. Semuanya kabur dan tak lengkap. Yang berkembang hanya opini, asumsi atau tebakan yang disandarkan pada sentimen agama; dekonstekstualisasi. Jurnalistik masih belum bisa menguraikan konflik Tolikara sebagai lingkaran kekerasan, apalagi mengeksplorasi ide-ide rekonsiliasi. Jurnalisme di pemberitaan Tolikara belum menjadi jurnalisme yang melengkapi prasangka dan fakta. Tapi jurnalisme yang menambahi dugaan dan mengompori.
Tak ada yang bilang bahwa Jurnalisme Damai itu jurnalisme yang mudah dan laku. Sebaliknya, Jurnalisme Perang yang bikin merinding dan menggigil itulah yang bisa menaikkan oplah, rating, trafik dan share. Terlebih dalam situasi terkini sosial politik Indonesia di mana masyarakatnya 'perlu asupan bahan bakar' kebencian dan sentimen antarkelompok. Belakangan, banyak dari kita yang menganggap bahwa dunia ini adalah ladang pertempuran yang tak habis-habis. Tapi dalam setiap konflik, peperangan dan ketegangan, selalu ada segelintir orang yang menangguk untung. Sementara kita semua kalah. (*)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H