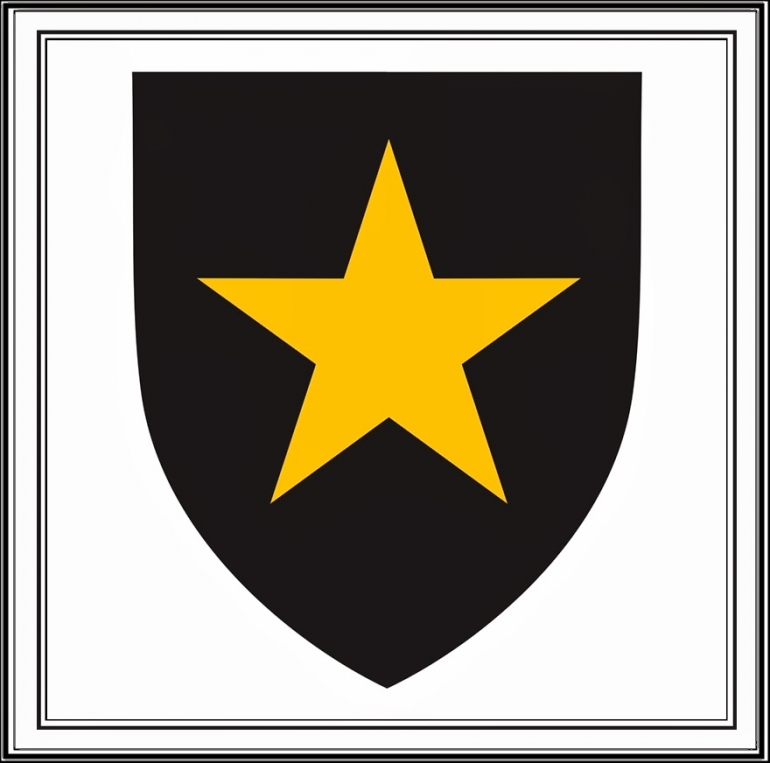"Penting dilihat bahwa dalam kenyataannya, Pasal 156A dipakai hanya selama sekitar 10 kali sejak tahun 1965 hingga 2000, dan tiba-tiba dalam 15 tahun terakhir demikian populer, telah digunakan sekitar 50 kali! Apakah setelah Reformasi ada makin banyak para penoda agama atau orang-orang yang sesat? Atau ada penjelasan lain dengan melihat transisi politik pada 1998?"
Saya ingin melihat polanya, dan satu satunya pola yang kelihatan adalah penodaan agama itu hanya berlaku atas penafsiran mayoritas terhadap sekelompok minoritas. Baik peristiwa di lombok maupun di Bali dan sekarang di Jakarta. Yang saya kritisi lalu seakan akan kalau itu dilakukan dari sekelompok mayoritas adalah sah sah saja, dan ini berkaitan dengan seluruh sila kemudian berkaitan dengan keadilan, demokrasi, dan juga tentu saja Ketuhanan itu sendiri. Untuk lebih jelas dan saya nilai sejak awal sebagai pasal politis mari kita ihat sejarah pasal ini.
Sejarah munculnya pasal 156 huruf a tidak lepas dari peran Presiden Soekarno dalam Penetapan presiden nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Oke, ini mungkin masih terlihat sebagai bentuk implementasi sila pertama. Tapi kemudian kalau dilihat lebih lanjut, perlu dikritisi secara jernih. pasal tersebut merupakan turunan dari hukum pidana yang pernah dibuat oleh pihak kolonial Belanda untuk mengatur tentang penistaan terhadap golongan.
Dr. Melissa Crouch Research Fellow di Melbourne Law School Australia menerangkan, aturan ini pertama kali diterbitkan melalui Ketetapan Presiden tanggal 27 Januari 1965 pada saat mulai memuncaknya kekhawatiran terhadap merebaknya komunisme dan berkembangnya aliran kepercayaan di Indonesia.
Dalam tulisan berjudul Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law yang dimuat pada Asian Journal of Comparative Law (2012). Crouch kembali menjelaskan bahwa pasal tersebut diperkuat dalam bentuk undang-undang pada tahun 1969.
Penguatan ini memberi kepastian bahwa pemuka agama dapat melindungi status, ajaran, dan penafsiran dari enam agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.
Hingga pada 20 Oktober 2009, beberapa LSM seperti LBH Jakarta, Imparsial, ELSAM, PBHI, DEMOS, Setara Institute, Desantara Fondation, berserta tokoh Musdah Mulia, M. Dawam Rahardjo, dan juga Abdurrahman Wahid mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kebali menguji secaran konstitusional terhadap pasal tersebut.
Saran pengujian itu muncul agar tidak terjadi praktik diskriminatif serta mendukung pluralisme di Indonesia. Akhirnya, MK memutuskan UU Penodaan Agama tetap konstitusional, meskipun MK mengakui bahwa perlu ada penyempurnaan dan kejelasan dari UU tersebut. Kata perlu penyempurnaan dan juga kejelasan harus diperhatikan di sini.
Saya sendiri, secara pribadi sepakat dengan hal ini bahwa mungkin saja tetap konstitusional. Tapi sebagai sebuah hukum konstitusi masih sangat lemah dan multitafsir. Pasalnya, kalau kita mau jujur sejak awalnya saja berkaitan dengan urusan pemerintah terhadap agama memunculkan banyak sekali tindakan dan juga kebijakan yang sangat diskriminatif. Di Indonesia ada banyak sekali agama agama yang sebenarnya berkembang. Itu di luar kepercayaan yang tidak diakui sebagai agama. Bahkan kalau mau lurus menilai agama itu apa, sudah terjadi perdebatan dan ketidakpastian. Agama itu apa dan bagaimana bentuk pengakuan negara serta efeknya. Katakanlah bagaimana kemudian negara mengatur pendirian tempat ibadah. Dan kalau diperhatikan dengan adanya 'itung-itungan' jumlah, mayoritas dan minoritas ini jelas sudah bertentangan dengan nilai nilai keadilan. Apa karena jumlahnya sedikit lalu tidak boleh mendirikan rumah ibadah?
Indonesia itu memang unik kalau dilihat bagaimana relasi negara dengan agama. Sekular bukan, negara agama juga bukan, mutualisme iya... tapi banyak yang tidak terwadahi. Mutualisme dengan agama yang mana? Apakah dengan semua agama agama? Sekali lagi, bahkan dengan adanya agama yang diakui dan tidak diakui saja, di situ sudah ada nilai nilai moral Pancasila yang dilanggar.
Ini benar kasus nyata: orang dari penganut kepercayaan menikah. Secara administratif, syarat sahnya sebuah pernikahan adalah yang secara agama. Lah, kalau agamanya saja tidak dianggap sah? konkritnya tidak sub departemen yang memfasilitasi sahnya perkawinan, bagaimana kemudian statusnya? Ya status perkawinannya tidak sah. Kalau tidak sah, lantas bagaimana dia mendapatkan layanan kependudukan yang lain? Bagaimana anaknya bisa sekolah yang mensyaratkan akte perkawinan orang tua dan juga akte kelahiran? Nah, maka kalau mau dihubungkan... apakah tindakan dan kebijakan diskriminatif ini sesuai dengan Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa?
Dengan ketidaksempurnaan hukum itu, kemudian wajar bila ada semacam perlawanan. Nuansa diskriminatifnya sangat terasa. Padahal sebuah nilai etis mestinya bersifat universal, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan standar yang sama seperti yang kemarin dijadikan bahan pertimbangan hakim, yang meskipun menolak adanya unsur politis, namun nuansanya sangat politis. Bagaimana mungkin sebuah keputusan didasari asumsi yang dirumuskan dengan kata 'seharusnya'? Kalau mau diskriminatif pertimbangan yang sama bisa berlaku pada kasus kasus serupa, bukan hanya kasus Ahok... tapi juga kasus kasus lain yang bisa diakses secara publik. Dan jujur saja, itu sangat banyak bertebaran di internet. Masa iya, semuanya harus dituntut dan diproses?