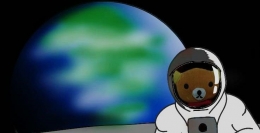Pada cangkir kopi kedua, Cukisno mulai mengeluarkan keluh kesah selama bekerja. Menceritakan bagaimana menyebalkan tempat itu. Jauh dari mana-mana dan tidak ada apa-apa. Ia merasa tak berhasil beradaptasi di lingkungan barunya itu.
Cukisno mulai membandingkan dirinya dengan rekan-rekannya yang ditempatkan di daerah asal. Bisa bertemu keluarganya setiap hari, bercengkrama dengan teman-temannya kapan pun ia mau.
Tidak perlu menunggu waktu cuti untuk pulang. Tidak perlu gelisah menghitung waktu tersisa sebelum kembali ke perantauan. Tidak perlu berkali-kali mengalami drama perpisahan di terminal keberangkatan dengan orang yang disayang. Atau merasakan sakitnya gagal menikah karena calon istri lebih memilih pria yang bisa hadir setiap hari. Cukisno merasa jadi pecundang dalam hidupnya.
Seperti biasa, Bilam mendengarkan dengan khidmat tanpa interupsi. Sesekali mengangguk, menyesap kopi, memompa rokok, lalu kembali menatap dalam lawan bicaranya. Seolah semua yang dikatakan Cukisno begitu penting dan punya pengaruh dalam hidupnya. Setelah Cukisno kehabisan bahan untuk ia keluhkan, Bilam mulai bersuara.
“Memilih lawan?” tanya Cukisno, “Kau selalu menggunakan istilah yang tak kupahami kawan. Coba jelaskan maksudmu,” pintanya pada Bilam.
"Kau selalu membandingkan dirimu dengan orang yang hidupnya jauh lebih baik darimu,” kata Bilam memulai penjelasan. “Temanmu yang dapat penempatan bagus lah, yang dipromosikan lah, yang dikembalikan ke daerah asalnya lah. Kau iri dengan mereka yang mudah mendapatkan pasangan, merasa gagal dengan dirimu yang kemarin dicampakkan. Kau terlalu fokus dengan perlombaan yang kau kalah di dalamnya. Hal itulah yang membuatmu terus merasa jadi pecundang. Padahal kalau kau mengubah lawanmu, banyak juga perlombaan yang telah kau menangi. Kau punya pekerjaan yang diimpikan hampir setiap anak di dunia ini. Gajimu tinggi, presiden saja mungkin kalah gajinya denganmu. Tidak ada orang tua yang akan menolak dirimu untuk dijadikan menantu. Dengan semua itu, kau harusnya bangga dengan dirimu.”
Bilam diam sejenak, membiarkan kawannya mencerna yang dia ucapkan.
“Kau bicara terlalu rumit untuk menyampaikan pepatah, lihatlah ke bawah supaya mudah bersyukur.”
Temannya itu tertawa beberapa saat. “Kau melakukan hal itu setiap hari, tapi sepertinya tidak bisa kau pahami dengan baik. Aku harus mencari cara lain untuk menjelaskannya padamu,” sanggah Bilam.
“Jadi itu yang selalu kau lakukan, sehingga selalu tanpa beban menjalani hidup?”
“Bisa dibilang begitu.”
“Lalu siapa yang kau jadikan lawan dalam perlombaan kehidupan?”
“Kau, tentu saja.”
“Sialan!”