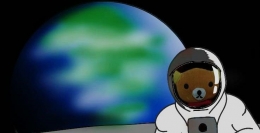“Kau bukan pecundang, cuma tak pintar saja dalam memilih lawan,” kata Bilam kala Cukisno berkeluh kesah padanya.
Ini adalah hari-hari menjelang Lebaran. Seperti kebiasaan para perantau, Cukisno pulang ke tanah kelahirannya. Melepas rindu yang tertahan pada orang tua, sanak keluarga, dan teman-temannya di kampung halaman.
Seperti lebaran sebelumnya, kepulangan Cukisno disambut orang tua dan saudara-saudaranya. Pemuda itu tersenyum getir. Tahun ini seharusnya ada seorang wanita lain yang ikut menunggu kedatangannya.
Wajah cantik wanita itu akan merona membara saat dirinya kelihatan di pintu kedatangan. Kemudian berlari secepat kuda ke arahnya, dan tanpa ragu-ragu memberikan pelukan sekuat beruang yang meremukkan tubuhnya. Cukisno teringat akan istri yang gagal dinikahinya.
Seharusnya memang romantis seperti itu, kalau saja tunangannya tidak meminta putus dua bulan sebelum hari pernikahan. Katanya, dia tidak yakin tahan menjadi istri yang ditinggal lama oleh suaminya. Dipisahkan jarak dan perbedaan waktu yang serba menyulitkan. Cukisno tentu saja kecewa, patah hati.
Dirinya sadar, itu memang jadi risikonya sebagai pekerja tambang di tempat antah berantah. Ia mencoba tegar, mencari hikmah akan musibah yang menimpanya.
Sayang, usahanya menjadi sia-sia karena seminggu setelah berpisah, si gadis mengumbar kemesraan dengan seorang pria yang tak ia kenal. Sakit hati Cukisno berlipat-lipat, kemudian mewujud menjadi tipes yang melemahkan badannya belasan hari.
Malam itu selepas tarawih, Cukisno sengaja mengajak Bilam, sahabatnya selama kuliah, untuk bertemu. Berbincang dengan Bilam menjadi salah satu ritual yang tak boleh dilewatkan setiap kali Cukisno mudik.
Sahabatnya itu adalah seorang pendengar yang baik. Bukan tipe manusia yang saat diminta menjadi wadah untuk mencurahkan isi hati, malah dengan jumawa menceritakan kisah dirinya sendiri. Sebuah kualitas yang mulai langka, dan tidak ia temukan lagi pada teman-taman barunya.
Malam itu mereka sepakat untuk bertemu di rumah kopi tak jauh dari tempat tinggal Bilam. Kalau saja ini bukan bulan suci, mungkin Cukisno akan mengajak Bilam ke pub dan minum-minum seperti masa kuliah.
Perbincangan mereka masih cair seperti dulu, mengeluarkan apa saja yang ada di kepala mereka tanpa ragu. Tidak ada pemanasan dan basa-basi untuk mengukur sejauh mana lawan bicara mereka berubah. Sebuah langkah yang biasa dilakukan dua orang yang sudah lama tidak bertemu.
Pada cangkir kopi kedua, Cukisno mulai mengeluarkan keluh kesah selama bekerja. Menceritakan bagaimana menyebalkan tempat itu. Jauh dari mana-mana dan tidak ada apa-apa. Ia merasa tak berhasil beradaptasi di lingkungan barunya itu.
Cukisno mulai membandingkan dirinya dengan rekan-rekannya yang ditempatkan di daerah asal. Bisa bertemu keluarganya setiap hari, bercengkrama dengan teman-temannya kapan pun ia mau.
Tidak perlu menunggu waktu cuti untuk pulang. Tidak perlu gelisah menghitung waktu tersisa sebelum kembali ke perantauan. Tidak perlu berkali-kali mengalami drama perpisahan di terminal keberangkatan dengan orang yang disayang. Atau merasakan sakitnya gagal menikah karena calon istri lebih memilih pria yang bisa hadir setiap hari. Cukisno merasa jadi pecundang dalam hidupnya.
Seperti biasa, Bilam mendengarkan dengan khidmat tanpa interupsi. Sesekali mengangguk, menyesap kopi, memompa rokok, lalu kembali menatap dalam lawan bicaranya. Seolah semua yang dikatakan Cukisno begitu penting dan punya pengaruh dalam hidupnya. Setelah Cukisno kehabisan bahan untuk ia keluhkan, Bilam mulai bersuara.
“Memilih lawan?” tanya Cukisno, “Kau selalu menggunakan istilah yang tak kupahami kawan. Coba jelaskan maksudmu,” pintanya pada Bilam.
"Kau selalu membandingkan dirimu dengan orang yang hidupnya jauh lebih baik darimu,” kata Bilam memulai penjelasan. “Temanmu yang dapat penempatan bagus lah, yang dipromosikan lah, yang dikembalikan ke daerah asalnya lah. Kau iri dengan mereka yang mudah mendapatkan pasangan, merasa gagal dengan dirimu yang kemarin dicampakkan. Kau terlalu fokus dengan perlombaan yang kau kalah di dalamnya. Hal itulah yang membuatmu terus merasa jadi pecundang. Padahal kalau kau mengubah lawanmu, banyak juga perlombaan yang telah kau menangi. Kau punya pekerjaan yang diimpikan hampir setiap anak di dunia ini. Gajimu tinggi, presiden saja mungkin kalah gajinya denganmu. Tidak ada orang tua yang akan menolak dirimu untuk dijadikan menantu. Dengan semua itu, kau harusnya bangga dengan dirimu.”
Bilam diam sejenak, membiarkan kawannya mencerna yang dia ucapkan.
“Kau bicara terlalu rumit untuk menyampaikan pepatah, lihatlah ke bawah supaya mudah bersyukur.”
Temannya itu tertawa beberapa saat. “Kau melakukan hal itu setiap hari, tapi sepertinya tidak bisa kau pahami dengan baik. Aku harus mencari cara lain untuk menjelaskannya padamu,” sanggah Bilam.
“Jadi itu yang selalu kau lakukan, sehingga selalu tanpa beban menjalani hidup?”
“Bisa dibilang begitu.”
“Lalu siapa yang kau jadikan lawan dalam perlombaan kehidupan?”
“Kau, tentu saja.”
“Sialan!”
Bilam kembali tertawa, cukup keras untuk membuat mereka menjadi pusat perhatian.
“Lalu, apa yang akan kau lakukan?” tanya Bilam.
“Aku mulai memikirkan untuk berhenti kerja dan memulai lagi dari awal. Atau, aku hanya akan melakukan yang kau bilang, mencari lawan yang lebih mudah kukalahkan.”
“Yah, yang mana pun, kuharap itu yang terbaik untukmu. Oiya, kapan kau akan kembali ke sana?” Bilam memberi isyarat dengan mengangkat cangkir.
“Seminggu setelah lebaran.”
“Kuharap kita masih bisa bertemu sebelum kau berangkat lagi.” Bilam memeriksa jam di tangan krinya, “Sudah malam. Aku takut tidak dibukakan pintu istriku,” tambahnya.
“Betapa dunia kian berubah. Bilam yang begitu disegani di kampus, kini takut pada istrinya,” ejek Cukisno.
“Tunggu saja giliranmu,” jawab Bilam santai.
“Aku sangat menunggu waktu itu,” balas Cukisno, “Kau duluan. Aku masih suka di sini.”
Jabat tangan dan gerakan mengadu bahu jadi penutup pertemuan mereka. Cukisno masih di mejanya, berteman kopi ketiganya dan obrolan samar di meja sebelah.
Pemuda itu mengarahkan wajahnya ke langit. Ada bulan yang menyambutnya dengan senyuman tipis, seolah sedang merayu Cukisno untuk datang padanya. Atau mungkin itu adalah sebuah mata yang sedang menatap licik ke arahnya.
Seperti seekor serigala yang tengah memberi muslihat dan menunggu waktu yang tepat untuk menyergap mangsanya. Seketika Cukisno merasa mual. Teringat olehnya akan kembali ke sana. Tempat yang membuatnya harus meninggalkan semua orang yang dikenalnya, ditinggalkan orang yang dicintainya.
Beberapa hari lagi Cukisno akan kembali ke perantauannya. Menempuh ratusan ribu kilometer, menembus atmosfer. Menghabiskan setahun ke depan di tanah tandus bernama bulan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H