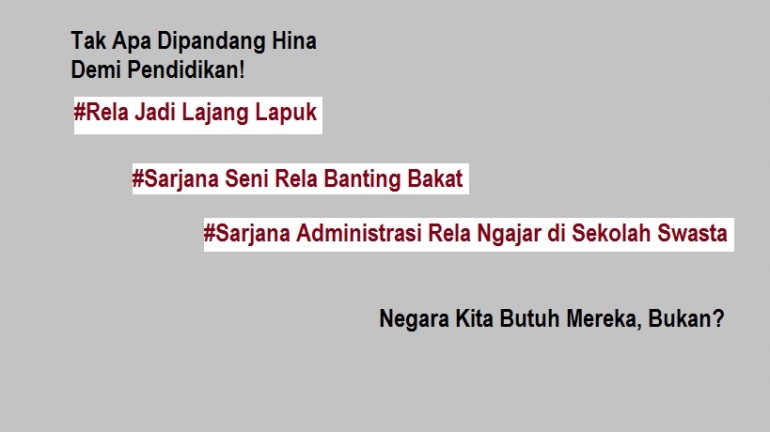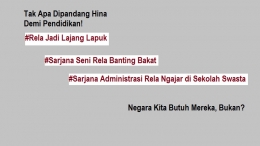Siapa yang tidak setuju pentingnya pendidikaan? Saya kira, kita semua setuju.
Alasannya, tidak lain: karena kehidupan yang baik tidak bisa lepas dari hasil pendidikan (belajar) yang baik pula. Anak yang baru lahir, tanpa diajari secara baik dan berkelanjutan, pasti di kala besar nanti akan timpang dalam menjalani aturan kehidupan—yang dibuat moyang terdahulu—itu sendiri.
Contoh sederhananya: seseorang yang sudah dewasa, sebut saja saya, dapat berkomunikasi dengan orang lain tak lepas sebab adanya pendidikan itu sendiri, secara perlahan dan dipaksakan para orang tua setiap hari mengajak anak-anaknya bicara, dan oleh waktu yang terus berlalu serta ‘memori’ telah menyimpan “kata-kata” yang pernah didengar, jadilah—secara perlahan anak itu bisa berbicara. Semua tidak terlepas dari pendidikan, bukan?
Contoh lainnya: Sekonyol-konyolnya maling di siang bolong, pasti belajar membobol kunci; sehina-hinanya seorang koruptor pasti mengecap pendidikan, apalagi yang berhasil menggondol hak rakyat berjumlah fantastis, wah, barang kali pelakunya sudah bergelar Master atau bahkan Doktor. (Catat: contoh ini perlu dibekukan).
Tidak bisa dipungkiri lagi, Negara kita Indonesia masih dalam pantauan sekarat akan rendahnya kualitas pendidikan. Terutama daerah yang tergolong 'kurang disentuh' oleh kemajuan. Meski demikian, terdapat banyak kabar juga kemerosotan pendidikan akibat kemajuan tadi.
Salah satu daerah yang kurang disentuh atau barang kali penyentuhnya yang kurang adalah Kabupaten Gayo Lues. Gayo Lues merupakan Kabupaten di daerah pendalam Aceh, asal penulis. Di tempat kelahiran penulis ini kualitas pendidikan masih (sangat) rendah. Entah pihak mana yang bertanggung jawab untuk itu.
Saya telah merasakan betapa dangkalnya kualitas pendidikan yang diperoleh ketika bersanding dengan teman-teman saya dari daerah lain Indonesia (2009). Saat itu saya mendapat anugrah, beasiswa dari pemerintah, sebagai siswa yang digolongkan berprestasi. Sebenarnya saya tidak merasa cukup berprestasi, ya, saya tidak merasa menaklukkan semua pelajaran-pelajaran jurusan IPA yang saya pilih. Alasannya, saya tidak tertarik belajar; sebab hitungan matematisnya saya tidak lanjut ke perguruan tinggi. Apa perlunya hanya sekedar SMA! Paham, kan? (kemudian saya mengaku keliru).
Tapi meski begitu, saya pemegang 'panggung' beberapa mata pelajaran di kelas: Matematika, Bahasa Inggris dan Fisika, bahkan dari SMP begitu penilaian guru dan teman-teman saya (saya senang ketika itu, karena yang lain menganggap pelajaran itu mematikan).
Tentu semua penghargaan kepada saya hanya sebatas versi kelas dan pengajar. Saya mengetahui saat kelas dua SMA. Saya mewakili sekolah untuk ikut bersaing dalam Olimpiade Sains tingkat Kabupaten, kebagian pelajaran Matematika. Di situ saya sudah sadar seperti apa kualitas matematika yang saya kuasai. Ya, peserta lain sibuk mengerjakan soal, saya masih sibuk memahami soal, sialnya semakin berusaha memahami semakin tidak mengerti. Anda sudah bisa tebak hasilnya? Saya juga tidak tau peringkat berapa, yang jelas saya tidak ikut dipanggil untuk bertanding di Provinsi.
Yang paling memprihatinkan saat kuliah. Berangkat dengan embel-embel nilai raport yang tinggi. Nyatanya, saya dipaksa kemampuan untuk menempati posisi buncit. Pelajaran yang dicap 'saya banget' oleh teman-teman SMA dan guru pelajaran itu, ternyata sukses membuat perasaan malu kambuh saat pembagian KRS. Ketiga mata kuliah yang serupa mata pelajaran 'saya baget' saat SMA tidak lebih baik dari sekedar nilai C dan D semata, dan sukses menempatkan saya di posisi 30 dari 30 mahasiswa dalam kelas saya. Menyedihkan.
Ketika curhat dengan teman asal Lampung tentang bagaimana prosesi belajar mereka saat SMA, saya tidak terlalu menyalahkan diri. Karena tempaan yang saya dapat memang tidak layang bertarung dengan teman kuliah lainnya. Teman saya bukan hanya dari Lampung juga daerah Jawa (minus Jogja), NTB, Sumut, Sumbar, Sulsel, Sulteng, Sultra, Kalteng dan kabupaten lain dari Provinsi Aceh: Banda Aceh dan Lhokseumawe.
Kalau SMA, saya kurang belajar tetap diperhitungkan. Tapi saat kuliah 'senantiasa' belajar tetap terpinggirkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dianggap konyol tak jarang saya lontarkan pada teman dan dosen. Misal: saat hendak praktikum Fisika, "Apa tu labu Erlenmeyer? Oh ini ya. Terus buat apa ini?" Saat mau praktikum Bahasa Inggris, "Bantuin dong, alatnya gak bisa berfungsi." Padahal saya tidak tau, sebab belum pernah praktik. Ah, memalukan.
Tapi, lama kelamaan, saya terus berusaha. Karena pulang lebih memalukan daripada bertahan. Saya memotivasi diri dengan kata: orang juga makan nasi! Kenapa saya gak bisa!
Akhirnya saya bisa mengikuti dari belakang. Ya, namanya mengikuti pasti tetap berada di belakang, meski di semester-semester akhir masuk sepuluh besar. Alhamdulillah.
Itu dulu. Bagaimana sekarang?
Menurut saya sekarang, tahun 2017, masih saja serupa. Di kampung saya misalnya: cukup banyak anak yang berusia sekitaran SMP dan SMA putus sekolah. Sekolah tidak mampu mengajaknya bertahan. Karena saat ditanya, bukan orang tua yang memutus pendidikannya, tapi dianya tidak mau. Lain lagi yang masih sekolah, pergaulan malamnya sama dengan yang tidak sekolah—bukan belajar atau mengerjakan PR di rumah.
Meski kondisi pendidikan begitu mengenaskan: kurang minat, kurang (peng)-ajar, kurang peralatan, dsb. Tapi masih ada kisah-kisah ‘heroik’ untuk memperjuangkan pendidikan. Meski kisah-kisah nyata mereka tergolong ‘basi’ tapi jelas tersimpan makna yang patut diteladani. Apalagi pelakunya masih muda. Berikut tiga yang saya bagikan:
Pertama, Rela Jadi Lajang Lapuk Demi Pendidikan Keluarga

Zul hanya tamatan SD. Bukan ia enggan sekolah. Lelaki yang sudah mendekati usia kepala tiga itu terpaksa tidak lanjut ke SMP. Karena, selain keluarga yang kurang mampu membiayai juga saat itu ada pemahaman keliru jika sekolah akan menjadi lawan dari pihak GAM, saat konflik Aceh.
Zul punya tiga saudara. Ia merupakan anak sulung. Orang tuanya yang termasuk sebagai korban konflik Aceh, bernasib menengah ke bawah. Bahkan, dapat digolongkan miskin. Karena raskin selalu singgah pada keluarganya. Apalagi lima tahuan terakhir, bapaknya sering sakit-sakitan dengan tambahan usia semakin menanjak senja. Hal itu membuat ia harus rela menjadi sandaran keluarga. Ia menghidupi keluarga dengan bertani cabe dan sere wangi.
Karena sudah jarang pemuda single seusianya, membuat sanak saudara sering mengusulkan agar ia segera menikah. Termasuk kedua orang tuanya tidak tega terhadapnya. Pasalnya, seliweran cemooh banyak terbawa angin ke telinga keluarganya. Tapi, ia tetap menolak.
“Saya tidak akan menikah sebelum adik tamat.”
Adik perempuannya sedang menempuh pendidikan Ekonomi di salah satu Universitas Swasta di Medan, kemungkinan 2017 ini menjadi sarjana. Awalnya kedua orang tuanya enggan melanjutkan adik perempuannya ke perguruan tinggi. Tapi, ia memaksa dan bertanggung jawab membiayai.
Berkat tenaganya adik nomor duanya telah lulus Diploma III. Kesulitan lapangan kerja membuat adiknya itu tidak terlalu bisa berbuat lebih, selain membantunya di kebun. Sedangkan adik bungsunya juga sudah tamat SMK, tapi tidak lanjut. Biar adik perempuannya tamat dulu, katanya.
Baginya, pendidikan itu penting. Ia sudah merasakannya sebagai orang kurang pendidikan. Karena itu, ia berusaha untuk menyekolahkan adiknya sebisa mungkin.
“Tidak. Bukan itu. Tidak ada maksud agar mereka bisa jadi PNS atau lainnya,” jawabnya saat ditanya apa maksudnya menyekolahkan adik-adiknya. “Hanya supaya mereka berpendidikan. Syukur kalau memang nasibnya baik. Bisa kerja kantoran. Kalau tidak, ya gak apa.” Tambahnya.
Kedua, Sarjana Seni Banting Bakat Demi Keluarga

Ditengah maraknya para sarjana, di Gayo Lues, berjuang untuk menjadi Pegawai pemerintah, tak apa walau hanya honorer yang sebagian menghalalkan segala cara. Ran malah tidak tertarik. Ia malah memilih jadi Tauke Cabe dan Bawang merah, meneruskan profesi almarhum ayahnya.
“Mau makan apa adik-adik nanti?” Ia balik bertanya saat ditanya kenapa tidak mau jadi pegawai. “Siapa yang membiayai sekolah mereka? 500 ribu buat saya aja tidak cukup. Gajian tiga bulan sekali lagi.” Pesimisnya menjadi tenaga honorer.
Ia memang bisa dapat puluhan juta perbulan menjadi tauke, meski tak jarang rugi puluhan juta juga. Ia juga pernah menolak tawaran temannya dari luar daerah untuk menekuni keahliannya, seni lukis. Ia menolak. Karena penghasilannya tidak jelas. Padahal dapur keluarganya tidak mau tau penhasilannya.
Ketiga, Sarjana Administrasi Rela Mengajar di Sekolah Swasta

Apa yang dilakukan Jamal lain dari umumnya. Ia rela mengajar di sekolah Swasta yang kekurangan pengajar. Upahnya sangat kecil, Rp. 300 rb saja perbulan, kadang juga kurang. Juga tidak ada iming-iming adanya SK pemerintah, yang nantinya ada kemungkinan pengangkatan jadi PNS atau bisa ikut tes K2—yang umumnya para honorer mengejar itu.
Saya tanya: kok mau jadi Guru?
“Ilmu itu harus diamalkan. Kita itu harus memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk yang lain.”
Saya kira, pemuda dengan pemahaman seperti itu yang negara kita butuhkan, terutama daerah penulis. Karena di Gayo Lues posisi pemuda seperti Zul, Ran dan Jamal sungguh langka, dan tak jarang dipandang ‘hina’ oleh lingkungan. Tapi mereka menelan mentah-mentah dengan pembuktiannya. #Salut!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H