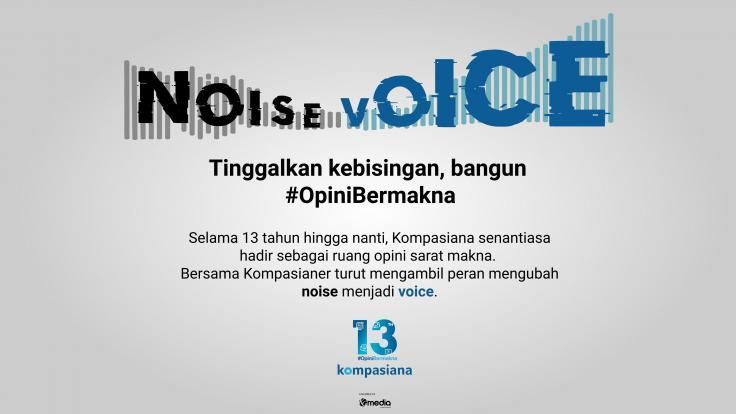Apa yang bisa saya sharingkan bertepatan dengan Kompasiana yang menginjak usia yang ke-13?
Saya hampir tidak mampu mengurai jawaban atas pertanyaan tersebut. Sebab bila orang hendak berbagi pengalaman itu mengandaikan orang tersebut sudah banyak makan asam garam kehidupan. Atau bila mau ditempatkan dalam konteks berkompasiana, orang tersebut sudah memperoleh pencapaian yang fantastis. Salah satunya dapat dilihat dari jumlah artikel yang sudah pernah ditulis.
Bagaimana dengan saya? Pencapaian saya masih jauh dari memuaskan. Sudah satu tahun lebih bergabung di Kompasiana, artikel yang sudah pernah saya tulis masih sangat minim. Jangan tanya soal K-Rewards. Sampai detik ini saya belum pernah merasakan seperti apa sensasinya mendapat K-Rewards.
Sesuatu yang wajar dan masuk akal. Dan rasanya tidak perlu saya ratapi. Sebab, sedari awal bergabung di Kompasiana saya memiliki tujuan utama, yakni memperkenalkan suku Dayak dengan segala kekayaan tradisi dan budayanya kepada masyarakat luas. Oleh karena itulah, tulisan-tulisan saya lebih banyak berkisar tentang kebudayaan suku Dayak Desa dan tema-tema lain sekitar dunia perladangan (kearifan berladang).
Meski lebih banyak memokuskan diri pada kedua tema tersebut, saya akui kalau ide-ide untuk menulis tidak selalu mengalir dengan lancar. Di samping tentu saja ada kegiatan lain yang menyita perhatian. Bagi saya, menulis tentang kebudayaan daerah, meski kebudayaan itu sendiri sudah menjadi bagian dari hidup saya, tidak bisa sesuka hati.
Saya tidak bisa menuliskannya hanya berdasarkan pengamatan dan penilaian saya. Tema apa pun yang hendak saya kaji harus saya tanyakan terlebih dahulu kepada para tokoh adat dan orang-orang tua agar penafsiran dan pemahaman yang dihasilkan bisa sungguh memadai. Bukan sebuah penafsiran dan pemahaman sepihak.
Rendahnya produktivitas dalam menulis saya pandang sebagai sebuah konsekuensi dari keputusan bila memusatkan diri pada tema-tema spesifik (baca: kebudayaan lokal). Saya selalu memandang hal tersebut bukan sebagai sebuah kegagalan, melainkan sebagai bagian dari proses. Atau dalam bahasa Michel Foucault sebagai sebuah seni menjalani hidup (estetika eksistensi).
Juga saya lihat sebagai bentuk pengakuan bahwa dengan kemampuan otak saya yang terbatas, tidak semua hal dapat saya ketahui.
Beberapa orang mungkin akan menyarankan agar keterbatasan itu mestinya diatasi dan dilampaui. Sebuah saran yang baik tentunya. Akan tetapi, untuk apa pun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Demikian ditulis dalam Kitab Pengkhotbah.
Suatu kali saya pernah mengirim sebuah artikel opini terkait dengan kearifan berladang suku Dayak kepada salah satu website yang secara khusus menyajikan berita-berita tentang Gereja Katolik maupun isu-isu lain yang mempengaruhi kehidupan komunitas Katolik.
Dalam artikel tersebut saya menempatkan kearifan berladang suku Dayak sebagai locus theologicus (ruang berteologi). Artinya, konteks kebudayaan lokal menjadi medan pewartaan Gereja dalam menyebarluaskan dan menguraikan pewartaan tentang Kristus. Gereja Katolik meyakini bahwa Warta Gembira tentang Kristus dan kebudayaan manusia itu mempunyai hubungan yang sangat erat.
Oleh website yang bersangkutan, sama seperti artikel-artikel dari penulis lainnya, artikel saya itu dibagikan di akun Facebook. Di dalam kolom komentar saya menemukan ada seorang netizen yang menanggapi artikel saya dengan cukup panjang.
Di akhir komentarnya, dia memberikan masukan kepada teolog budaya - begitu istilah yang dia gunakan - agar refleksi tidak hanya berhenti pada hal-hal teologis saja, tapi juga menyentuh pada hal-hal kebijakan praktis tentang bagaimana metode lain dalam membuka dan menggarap ladang selain dari membakar.
Saya menahan diri untuk tidak membalas komentar tersebut. Saya berpikir sudah ada pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam memikirkan metode yang tepat bagi masyarakat Dayak dalam berladang, jika memang cara membakar tidak lagi diperbolehkan.
Dengan melihat kearifan berladang dari perspektif teologis, saya hanya mau menunjukkan bahwa kodrat manusia dan konteks manusia itu sendiri adalah baik, kudus dan bernilai. Bila Gereja ingin sungguh menghadirkan Kerajaan Allah di tengah dunia, atau bila pemerintah dengan segala kebijakan peraturan yang dikeluarkan bertujuan mendatangkan kebaikan bersama (bonum commune), maka kenyataan tentang kodrat manusia dan konteksnya itu sama sekali tidak boleh diabaikan.
***
Masih minimnya jumlah artikel yang pernah ditulis bukan berarti tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Di saat beberapa rekan K-ners mendapatkan K-Rewards dalam bentuk sejumlah nominal uang, saya juga mendapatkan "K-Rewards" dalam bentuk yang lain.
Beberapa hari yang lalu, saya kaget ketika ada salah seorang mahasiswa mengirim e-mail ke saya. Dia adalah mahasiswa di salah satu Universitas Negeri di Pontianak. Mengambil jurusan antropologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).
Di dalam e-mail tersebut dia mengatakan kalau sedang menggarap sebuah tugas yang topiknya berkaitan dengan salah satu seni budaya dalam suku Dayak Desa, yakni kana. Tentang apa itu kana silakan baca di sini.
Dengan sangat jujur dia mengatakan kalau mengalami kesulitan menemukan sumber referensi tentang suku Dayak Desa dan tentang seni kana itu sendiri. Di tengah kesulitannya itu, dia pergi bertanya ke Mbah Google lalu memasukkan beberapa kata kunci terkait dengan suku Dayak Desa. Dan, dia pun menemukan beberapa artikel yang sudah pernah saya tulis di Kompasiana.
Maksud dia mengirim e-mail ke saya ialah untuk menyampaikan hal tersebut sekaligus meminta izin untuk menjadikan tulisan-tulisan sebagai sumber referensi. Tentu dengan senang hati saya mengizinkannya, karena saya juga menyadari buku-buku maupun artikel-artikel yang membahas suku kami Dayak Desa masih sangat sangat minim.
***
Tidak ada kata lain selain terima kasih yang dapat saya ucapkan kepada Kompasiana yang telah memberikan ruang bagi saya untuk mengurai manusia Dayak dengan segala kekayaan tradisi dan budayanya.
Terima kasih karena berkat Kompasiana tulisan-tulisan saya bisa menjadi suluh bagi mereka yang sedang berada dalam kesulitan.
Saya doakan semoga para pengelola selalu diberi kesehatan yang baik serta kebijaksanaan hati (sapentia cordis) agar bisa mengelola Rumah Bersama ini dengan baik dan bijaksana.
Selamat ulang tahun yang ke-13 Kompasiana. Semoga semakin maju dan sukses!
Salam.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H