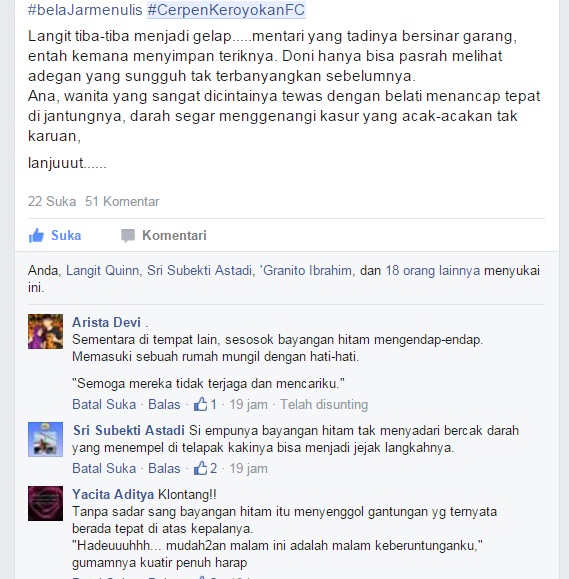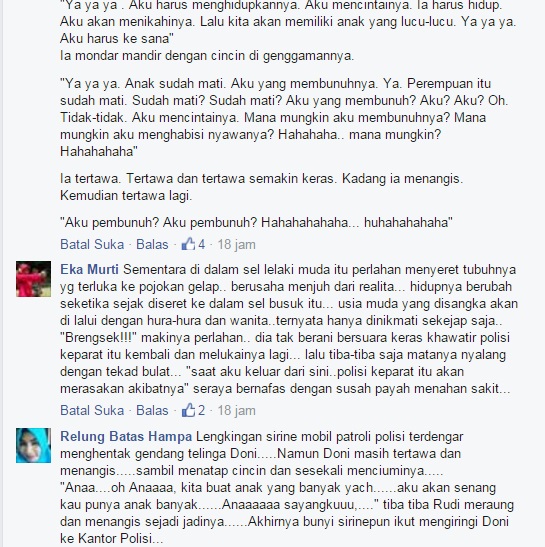Rabu, jam 3.15 – sore.
Awan gelap berarak membawa gumpalan air bersamanya, sebentar lagi akan tiris menghunjam bumi. Cepat sekali menutupi birunya langit, menghalangi garangnya terik mentari.
Doni—35 tahun—menapak ke tanah, bertumpu dengan kedua lutut. Menengadah pasrah ke cakrawala menghitam, mengharap hujan turun saat itu juga, membasuh dan menghanyutkan lara tak berbentuk di relung terdalam. Bersimpuh di samping tubuh tak bergerak. Kepala lemah tertunduk, bulir air mata mendahului sang hujan. Satu per satu menampar bumi.
Ana—27 tahun—sang kekasih, menelungkup di atas tanah tak berumput. Dengan tangan gemetar, Doni membalikkan tubuh Ana.
Cairan merah masih menganak sungai dari pisau perak bergagang hitam yang menembus dada kiri Ana, meski tak sederas sebelumnya.
Doni menjerit, memeluk erat belahan jiwa yang telah pergi untuk selamanya.
Sepasang mata tua mengawasi punggung Doni yang terisak dari balik jendela nako lantai satu. Selaksa rasa bias di wajah yang keriput. Sosok tua bersetelan hitam-hitam meninggalkan jendela, membiarkan Doni di halaman belakang itu bersama kedukaannya.
Pandangan iba dan penyesalan juga tertumbuk ke punggung Doni. Hadi—60 tahun—adik dari mendiang ayah kandung Doni, Hary. Sang paman menghela napas dalam.
“Aku akan membalasmu, Kamal.” Bayangan Hadi menghilang dari jendela di lantai dua. “Dan kuharap… ini malam keberuntunganku.”
Klontang…
Langkah Hadi tertahan. Hanya sesaat sebelum meneruskan langkahnya. Mungkin wanita tua itu memang sudah buta, pikirnya.
Di salah satu kamar, Nunik—31 tahun—mengawasi keadaan. Mengumpat kecerobohannya menendang kaleng cat, menumpahkan isinya, hingga permukaan lantai berlapis ambal biru terang memerah.
“Jahanam… aku harus mendapatkan benda itu!”
***
Rabu, jam 3.30 – sore.
Di kantor Kepolisian. Kamal—37 tahun—mematung lama memandangi gerimis dari jendela. Di tangan, masih menggenggam ponsel, ibu jari bermain-main mesra di layarnya, tanpa perhatian.
“Permisi, Ndan,” Jamil datang menghadap.
“Haa, Jamil. Kamu pastikan detail pembunuhan berantai wanita muda itu,“ Kamal menyerahkan map tebal kepada Jamil, lantas melangkah ke arah pintu. “Dan satu lagi—“ kembali Kamal membalikkan tubuh. “Paling tidak, besok pagi sudah ada di mejaku. Kau mengerti?”
“Siap, Ndan.”
Di waktu yang sama, Doni masih memeluk tubuh kekasihnya, tak menghiraukan tetes-tetes gerimis yang mulai membasahi sekujur tubuh.
Ana, mendapati dirinya tengah memandang tak berkedip pada Doni. Hanya sesaat, pandangan Ana menghangat.
“A—aku, mati?” Ana mengenali tubuh dalam pelukan Doni itu, tubuh dirinya sendiri. “Aku sudah mati…” Lantas berteriak kencang menyeru sang kekasih. “Kenapa kau tidak mendengarku, Doni…?” Ana mencoba memeluk Doni, namun hanya memeluk kehampaan.
Sekuat apa pun usaha Ana untuk menangis, bulir air mata tiada lagi di sana. Yang ia tahu, kini ia di alam berbeda. Bahkan rapatnya rintik hujan, tak setetes pun membasahinya. Satu bayang putih menyilaukan mengagetkan Ana, meski tiada seorang pun yang bisa memberi tahu, tapi Ana yakin, itu Sang Maut.
Ana tak bisa berbuat banyak, menatap sayu pada Doni. Namun Ana yakin, seseorang pasti akan memberikan kebenaran untuk Doni.
“Don… mungkin kau tidak memahami—tapi, aku mencintaimu, bahkan dengan keadaanku ini.”
Sang Maut membawa paksa tubuh halus Ana, dalam sekejapan mata telah menjauh meninggalkan kenyataan yang menyakitkan di belakang.
“Aku tetap mencintaimu, Don…”
***
Rabu, jam 12.45 – lewat tengah malam.
Di lantai satu rumah besar bak vila sang raja disesaki petugas kepolisian, juga. Sementara itu, tidak menghiraukan para polisi yang hilir mudik mengumpulkan barang bukti, Nunik pun tak kalah sibuknya. Dengan alasan ingin membantu pihak kepolisian, ia “mengacak-acak” kamar pribadi mendiang Ana.
Tatapannya membentur lusinan tas berbagai merek di satu lemari, Nunik tersenyum seribu makna. “Bingo…”
Di lantai bawah, sejak sepuluh menit yang lalu Doni hanya mematung di sudut kiri perapian yang tak pernah terpakai sekali pun. Entah siapa yang mendesain bangunan ini, terlalu kebarat-baratan, begitu yang selalu diprotes Doni kala sang ayah masih hidup.
“Pak Doni,” seru Jamil, ia butuh kesabaran ekstra untuk yang satu ini. “Anda belum menjawab pertanyaan kami.”
Petugas sialan! Tidak bisakah pertanyaanmu itu menunggu kesedihanku berlalu? Namun, hanya tatapan bak sembilu tajam yang menanggapi teguran Jamil.
“Bangsat…!” rutuk Nunik. Ia tidak menemukan tas yang ia cari di antara lusinan tas yang berjejer rapi. “Terkutuk kau, Ana. Di mana kau simpan tas itu…?
“Anda menemukan sesuatu, Mbak Nunik?”
“Eh, enggak. Hanya salah lihat, iya.” Nunik menyumpah, namun hanya di dalam hati. Petugas muda itu nyaris saja membuat tali jantungnya putus. Hmm… tampan juga.
“Baik, Ndan. Siap, 86.” Jamil menyimpan kembali ponselnya.
“Bagaimana?”
“Atasan, mengingatkan detail olah TKP…” Jamil mengempaskan napas panjang, memancing perhatian sang rekan.
“Jujur saja.”
“Entahlah,” Jamil melirik ke arah Doni yang masih saja bersikap sama. “Ada yang aneh di sini—maksudku, atasan kita.”
Lama sang rekan terdiam, sebelum berujar, “Sudahlah. Biar sisanya kami yang menyelesaikan.”
Jamil mengangguk, lantas meninggalkan rumah besar. Di Luar garis kuning kepolisian, beberapa tetangga cukup bernafsu untuk mengetahui kenyataan di balik pembunuhan Ana. Jamil tidak menghiraukan itu, terus saja memacu motor besar dengan raungan sirenenya.
***
Kamis, jam 9.07 – Malam.
Rudie—30 tahun—menyusuri jalanan bersama mobil Pajero hitamnya. Di sampingnya, tergeletak sebuah tas kulit berwarna hitam dengan logo D&G. Rudie tidak menyangka, Ana akan berbaik hati memberikan tas itu kepada Nunik, setidaknya itu yang diketahui Rudie dari Nyonya Besar.
“Sepertinya kau tahu, ya, Ana,” gumam Rudie didahului tawa renyah. “Aku menyukai Nunik. Tapi—“ bayang kesedihan menghempaskan sumringah yang sedari tadi menghias wajah. “Ana…”
Di rumahnya, Nunik masih saja uring-uringan. Tak pernah betah berlama-lama pada satu sudut saja. Lima menit, dan ia akan melangkah lagi ke sudut lainnya.
“Jahanam kau Ana. Di mana tas D&G hitam itu kau simpan, haa…?” Nunik berteriak seperti kehilangan akal sehatnya. “Di mana berlian dua puluh lima karat itu…?”
Di satu rumah. Seseorang dengan gerak-gerik tak biasa, perlahan membuka pintu kamar. Wajahnya tertutup topeng menyeramkan, seolah hari itu adalah perayaan Halloween. Di tangan kanan tergenggam sebilah belati besi putih dengan gagang hitam.
Di atas pembaringan, seorang wanita muda tertidur pulas. Orang bertopeng mendekati. Perlahan ia meraih bantal, belati di tangan berkilau ditimpa cahaya lampu.
“Hmmpp… hmmpp…”
Cleptt!
Wanita muda dengan wajah tertutup bantal berhenti bergerak. Belati yang terhunjam ke dada kiri melepas perlawanan, sekaligus melepas nyawanya.
Orang bertopeng meninggalkan belati di dada jasad itu, berlalu dan menghilang di balik tanaman di samping rumah.
Hadi menatap hening permukaan sungai, gelap hanya sesekali cahaya sorot dari lampu kendaraan yang bisa memberi tahu bahwa malam ini, adalah malam kesekian yang teramat berat baginya.
Dering pesan masuk di ponsel di balik jaket hitamnya, memaksa Hadi untuk menghentikan lamunan.
“Dua wanita muda lagi, Hadi. Dan kau tidak akan melihat berita kematian anakmu.”
Dua kalimat, dan itu cukup untuk membakar dada Hadi.
“Jahanam…!”
Hadi tiada pernah menyangka kisruh skandal keluarga besarnya akan dimanfaatkan seseorang demi pangkat dan jabatan yang lebih tinggi. Tidak, Hadi belum tahu kenyataan yang sesungguhnya.
Kamal tersenyum menang, kilat di kedua bola mata begitu liar. Kembali memasukkan ponsel ke kantung celana dinas kepolisiannya. Ia melangkah menuruni undakan anak tangga.
Ruang bawah tanah ini, sebuah penjara yang telah lama tidak digunakan. Ada tujuh sel di sisi kanan. Kamal melangkah ke sel paling ujung, satu-satunya yang berisi tahanan.
Sesosok pemuda kumal bergulung di sana. Ia masih terlihat hidup, meski dalam keadaan hening.
Kamal meraih ember kaleng di lantai, lantas menyiramkan begitu saja air di dalam ember ke tubuh di balik jeruji itu.
Pemuda 25 tahun gelagapan. Kamal membuka pintu sel. Semakin Kamal mendekatinya, pemuda itu semakin bergeser ke sudut sel.
“Dua nyawa lagi,” Kamal terkekeh. “Jika bapakmu gagal, jangan pernah berharap kau akan melihat matahari!” Kamal menjambak rambut pemuda tersebut. “Aku rasa kau harus tahu… Ana, tunanganmu sudah mati,” ucapan Kamal diakiri dengan tawa membahana.
Duaaakh…
Pemuda itu melenguh pendek, kepala yang membentur dinding berdengung kencang. Tidak ada jeritan yang keluar dari mulutnya, hanya sepasang mata liar memerah dan gemeretak rahang yang bergesek kuat.
Ia memang tidak lagi mencintai Ana, meski gadis itu adalah calon istrinya. Kenyataan yang dibongkar Kamal, menyudutkan dan menghapus kata cinta di dirinya terhadap Ana.
Ana, adalah anak hasil perselingkuhan Om Hary, ayah kandung Doni. Yang berarti gadis itu adalah sepupu—patrilineal—yang tidak akan mungkin bisa ia nikahi. Dan sialnya, wanita yang menjadi selingkuhan Om Hary, adalah ibu kandung dari polisi jahanam itu. Di sinilah bermula “permainan berdarah” yang digelar Kamal terhadap keluarga besar Hary dan Hadi. Meski permainan itu juga menyeret nyawa Ana yang secara tidak langsung adalah adik satu ibu dari Kamal, namun iblis di diri Kamal tak mengizinkan kata prihatin muncul di hatinya.
Dan ya, meski nanti jika ia terlepas dari cengkeraman Kamal, pemuda itu tidak akan lagi meneruskan niat memperistri Ana, namun fakta yang tadi diucapkan Kamal… tetap saja menumbuk perasaannya. Berderai tak sanggup ia susun kembali.
Nunik begitu terpesona kala Rudie datang menyambanginya. Lebih terpesona lagi dengan tas di tangan Rudie.
“Apaan sih isinya, Yang?” keinginan Rudie untuk melihat isi tas sudah muncul sejak Nyonya Besar menitipkan tas itu kepadanya. Namun sayang, tas itu dikunci gembok kecil berbentuk hati. Dan kuncinya, entah bagaimana bisa ada di tangan Nunik.
“Ahh, mau tau aja kamu itu,” Nunik mengedipkan sebelah mata. Duduk di sofa mewah, berusaha membuka gembok. Rudie mengambil posisi di kanan Nunik.
Baru saja kunci gembok terlepas, dan kancing tas sedikit terbuka, sesuatu dengan cepat keluar dari dalam tas. Ular tanah. Ular berwarna hitam itu dengan cepat menyambar punggung tangan Nunik.
Nunik terpekik, begitu juga Rudie yang kaget setengah mati. Di saat keduanya kalang kabut, ular berbisa mematikan itu meluncur mencari jalan keluar, meninggalkan Nunik yang tiba-tiba ambruk dan Rudie yang panik menyeru-nyeru nama gadis pujaannya.
***

Jumat, jam 2.57 – siang.
Halaman belakang rumah keluarga mendiang Hary, di dekat gudang tua di samping kolam besar tak terurus.
Nyaris saja sosok itu tidak bisa dikenali, sosok Doni yang begitu berubah drastis, dua hari semenjak kematian misterius orang yang ia sayangi melebihi apa pun. Tragedi itu telah memutar balik akal pikiran pria yang sesungguhnya gagah bersahaja tersebut.
“Mati, kamu mati!” racaunya, sembari membacok-bacok boneka beruang berwarna pink milik mendiang Ana. “Ana… kau kejam, kau tega meninggalkanku, Ana… jahanam, perempuan sialan. Matilah kau, mati… mati…!!!”
Hancur sudah apa yang pernah tersimpan indah di relung jiwa, seperti boneka beruang hadiah cintanya pada Ana. Terburai tiada berbentuk lagi.
Triing…
Kegilaan Doni terhenti, mata kapak menyentuh sesuatu yang lain di dalam perut boneka yang hancur. Cincin berlian dalam balutan emas putih. Doni terperangah, bersimpuh di atas tanah. Perlahan meraih cincin berlian dua puluh lima karat itu. Ia mendesah lemah, mendekap cincin ke dada, bergulung hingga kening menyentuh permukaan tanah.
Lambat laun, isak tertahan menjadi tangis menggelegar. Pilu. Nama Ana selalu terucap dalam lengkingan sengau itu.
Tangis terhenti berganti tawa membuncah kesetanan.
“Ana… matilah kau Ana… hahaha…”
Hening lagi, tertunduk lagi. Sepasang mata sayu memandang berlian berkilau di sela jemari.
“Ya-ya-ya, aku harus menghidupkannya. Aku akan menghidupkanmu Ana. Aku akan menikahimu, persetan dengan si Nito. Lalu… lalu,” Doni terkulai lemah, membiarkan tubuhnya rebah di atas tanah, nanar memandangi langit tinggi. “Ki—kita, lari dari sini. Punya anak yang lucu-lucu… Ana.”
Sepasang mata tua belumlah buta, sangat jelas melihat luka di hati anak semata wayangnya yang berbaring di tanah itu. Lelehan air mata telah melembabkan kerah bajunya yang tinggi. Terkutuk kau Hary… kau telah membawa kehancuran untuk anak kita. Membusuklah kau di neraka.
Di dalam sel bawah tanah. Pemuda lusuh yang adalah Nito, menyeret langkah ke sudut tergelap ruang. Tidak ada lagi yang mampu membuat hidupnya bergairah andai kata bisa keluar dari mimpi buruk ini. Tidak ada. Hasrat yang dulu ingin membina rumah tangga bahagia, pupus sudah. Seandainya Ana tetaplah bukan anak Om Hary, ahh… itu percuma jika benar ayah telah membunuhnya juga, pikir Nito.
Hanya satu alasan saja yang mampu menopang kehidupan tubuh ringkih itu. Dendam berkarat yang tertanam paksa ke relung jiwa. Dan itu, akan sempurna bila Kamal meregang nyawa di tangannya.
***
Jumat, jam 11.00 – malam.
Lengking sirene mobil kepolisian mengentak keheningan. Beberapa petugas segera turun dan langsung memasuki rumah yang tiada lagi rona kehidupan.
Jamil menghela napas dalam kala pandangannya tertumbuk sosok Doni yang mencangkung di sudut perapian. Teramat sulit untuk mengorek keterangan dari sosok yang sekarang kehilangan akal sehatnya itu kini, pikir Jamil.
Dua orang rekan Jamil segera naik ke lantai dua. Sebentar saja telah kembali turun, kali ini dengan mengapit perempuan 65 tahun.
Dengan sedikit gerakan kepala, Jamil memerintahkan kedua rekannya, membawa perempuan tua ke kantor guna penyelidikan lebih lanjut. Jamil juga memberi tahu seorang ART muda, untuk bisa memberi perhatian pada Doni.
Jamil mendekati Doni yang mendekap serpihan-serpihan boneka beruang.
“Ana Sayang… kita buat anak yang banyak yaaa. Aku suka anak-anak, Ana. Kamu suka, kan? He-he, aku tahu… ayoo Ana, jangan diam saja…”
Sekali lagi, Jamil menghela napas teramat dalam. Terlalu berat apa yang ditanggung punggung lebar itu, bisiknya dalam hati.
“Pak Doni,” Jamil tahu, mungkin Doni tidak akan mendengar apa yang ia ucapkan, tapi entahlah… ia merasa harus melakukannya, itu saja. “Maaf, Nyonya Sinna akan kami bawa. Sepupumu, Nunik, ditemukan tewas akibat patukan ular berbisa. Dan pada tas kulit hitam itu, kami menemukan sidik jari ibunda Anda. Maaf, selamat malam.”
“Ahh Ana… biarkan saja mereka. Ayolah Sayang, Cinta, Manis… hehehe…”
Jamil menggelengkan kepala, detik selanjutnya ia meninggalkan Doni dalam pengawasan sang ART muda.
Di dalam mobil patroli, Nyonya Sinna tak sedikit pun menampakkan penyesalan atas rencana yang telah ia rancang dan berhasil merenggut nyawa Nunik.
“Kau pantas mati, Nunik. Pantas mati seperti ibumu. Kau memojokkan Doni-ku, hingga mencuci pikirannya untuk mencintai anak haram itu. Ahh, aku lupa, kau tidak tahu soal itu. Hanya anak angkat? Hahaha… Kau pantas mati! Kalian berdua pantas mati!” Namun, kata-kata itu tertindih raungan sirene yang semakin menjauh dan menjauh.
Rudie tiba-tiba hadir di ruang tengah rumah besar, terengah-engah demi sebuah kepastian. Namun ia harus menelan ludah. Tidak seorang pun ia temui di sana yang bisa ia tanyai, kecuali Doni yang bertingkah aneh, dan ART muda yang baru saja muncul dari arah ruang belakang.
Rudie menjelepok begitu saja, meraung panjang. “Apa yang terjadi pada keluarga kalian…?”
***
Jumat, jam 4.00 – dini hari.
Bruakkk.
Tubuh molek dengan pakaian serbaminim tergolek lemah di samping sebuah tempat sampah kuning persegi.
Orang bertopeng lari menjauhi korban kedelapan tersebut. Terus berlari masuk gang keluar gang, hingga di satu tempat ia menghentikan larinya. Melepas topeng yang sedari tadi ia kenakan. Terengah-engah, ia bersandar ke pipa-pipa besi pembatas tepian sungai.
Hadi. Melepas pakaian terluar, menyapu percikan darah yang mengotori beberapa sisi tubuhnya. Dan membuang baju itu ke dalam sungai.
Hadi melepaskan emosi diri pada tembok pembatas, meraung panjang dan lantas berlutut. Andai saja ia tidak menyayangi anak semata wayangnya… tentu membunuh gadis-gadis muda tersebut bukanlah pekerjaan yang dengan sukarela ia lakukan.
Delapan gadis telah ia bunuh. Dari gadis baik-baik sampai gadis-gadis nakal yang suka merusak rumah tangga orang lain.
“Arrgg… sampai kapan ini akan berakhir? Tuhan…”
Lagi-lagi dering pesan masuk di ponselnya membuyarkan “keheningan” Hadi.
“Kurasa… tersisa satu nyawa lagi, bukan? Selamat berusaha Hadi hahaha…”
“Bangsat kau Kamal…!!!” Teriakan Hadi menembus keheningan subuh. Dan lagi-lagi, dinding tembok menjadi sasaran pelampiasan, hingga kepalan tangan pecah berdarah.
Hadi bangkit. Apa pun pilihan yang ada, ia sudah terlanjur jauh menjalani permainan Kamal.
Pukul 4.40 – subuh.
Jamil dan seorang rekan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak ada dalam list yang dijadwalkan atasan mereka.
Insting dan kecurigaan Jamil akan sang atasan membawanya pada kenyataan yang tak ingin ia percayai. Jamil dan sang rekan, berhasil membuntuti Kamal hingga ke penjara bawah tanah di luar kota.
“Kau berpikiran seperti apa yang kupikirkan?”
Jamil mengangguk, untuk itulah ia mengajak rekan tersebut. “Dua saksi lebih baik dari satu orang.”
“Pemuda bodoh!” Maki Kamal seiring sepatu PDL-nya melayang ke tulang kering Nito. Nito melenguh menahan sakit. “Andai ayahmu mampu menyelesaikan permainan ini, kau tetap tidak akan aku lepaskan. Setidaknya, tidak dalam keadaan utuh, hahaha…”
“Jahanam, terkutuk kau, cuiih…”
Kamal meradang, ludah menjijikkan menempel telak di wajahnya. Tangannya melayang memaksa Nito terbungkuk, disusul tendangan keras ke punggung pemuda tersebut.
Braakk…
Nito tersungkur menabrak tumpukan peti usang. Kamal menginjak kuat pinggangnya. Puas menyiksa, Kamal menyeret kaki pemuda tersebut meninggalkan ruang bawah tanah.
“Cukup sampai di situ!”
Kamal sempat gugup, tidak menyangka bawahannya—Jamil dan seorang lagi—memergoki apa yang tengah ia perbuat.
“Jadi… kau sudah tahu, ya, Jamil.”
“Jangan pikir saya bodoh, Komandan!” kata terakhir penuh penekanan.
Kamal mendengus, melepaskan kaki Nito. “Persetan dengan kalian…”
Dorr
Doorrr…
Pukul 4.59 – subuh.
Hadi mengendap-endap menuju pintu belakang rumah Nunik. Hanya anak dari adik Nyonya Sinna itulah nyawa terakhir yang bisa ia dapat. Tidak mungkin mencari yang lain, tidak sempat, sementara satu jam lagi adalah batas terakhir dari permaianan ini, setidaknya itulah ancaman dari Kamal.
Namu Hadi tak mengira, ternyata rumah dalam keadaan ramai. Dan suasana ini, seperti ada seseorang telah mati saja, bisik hatinya.
Dan benar, begitu Hadi memberanikan diri untuk muncul di tengah keramaian di ruang depan itu, beberapa kerabat mengatakan padanya jika Nunik tewas karena gigitan ular beracun.
Di mata orang-orang, Hadi terlihat terpukul akan kematian Nunik, dan menangis sejadi-jadinya. Namun, bagi Hadi sendiri, ratapannya tak lebih dari bayang kematian sang anak di depan mata. Ya, kematian sebab ia gagal menyelesaikan permaiannya.
Lima belas menit kemudian, tiga mobil kepolisian berhenti di depan rumah mendiang Nunik. Hadi masih menjelepok di sana saat beberapa petugas berseragam lengkap menghampiri.
“Pak Hadi, kami minta Anda ikut kami ke kantor,” Jamil mengedarkan pandangannya. Dari tempat ia berdiri, ia bisa melihat dua rekannya tengah berada di ruang tengah. Menelisik TKP ditemukannya tubuh Nunik yang membiru dengan mulut berbusa. “Mungkin… hukuman Anda akan mendapat keringanan.”
Hadi terperangah, ia menatap ke dalam sepasang mata itu. Jamil mengangguk, memastikan apa pun yang dipikirkan Hadi tentang hal yang ia ucapkan adalah benar.
“Dan berharap saja, masalah pelik keluarga Anda bisa diurai satu per satu.”
“Anak saya?”
Jamil sedikit tersenyum, bagi Hadi itu adalah kabar yang tak terhingga. Dan bila ia harus menjalani hukuman seumur hidupnya, atau bahkan kematian, ia rela. Asal Nito sang anak, bisa diselamatkan.
“Akan aku buka semuanya,” jelas Hadi sembari bangkit dan menyorongkan kedua tangannya kepada Jamil.
***
Sabtu, jam 8.00 – malam.
Rudie memandang gulungan ombak yang berkejaran ke tepian. Membiarkan sang angin mempermainkan rambut dan baju kemejanya.
Ia menatap langit tinggi yang menghadirkan rajutan sang bintang. Terlalu indah untuk bisa ia nikmati seorang diri.
Rudie memejamkan mata, mendesah berat. “Keluarga seperti apa mereka itu…?”

Cerpen ini dirangkum oleh Ando Ajo admin di Fiksiana Community.
Cerpen ini ditulis oleh; Arista Devi, Sri Subekti Astadi, Yacita Aditya, Rudie Chakil, Langit Quinn, Nunik Hidayanti Utami, Mustafa Kamal, Eka Murti, Relung Batas Hampa, dan Al-muru'ah Sayyid Jumi Anto.
TULISAN INI MERUPAKAN HASIL DARI #BELAJAR-MENULIS & #CERPEN-KEROYOKAN DI WALL FB FIKSIANA COMMUNITY. COPASING HARUS SIIZIN ADMIN FIKSIANA COMMUNITY.
FC - 11 Februari 2016.
ilustrasi dari laman group Fiksiana Community.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H