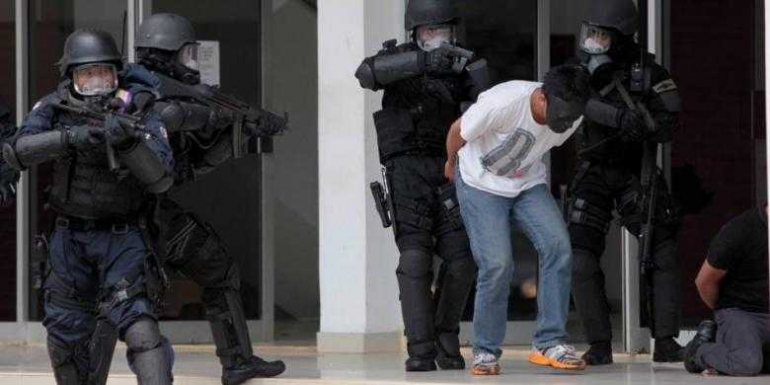Dari aspek hukum formil, masih menurut Nasrullah merujuk pada pasal 7 UU No. 15/2003. Dimana ada frasa “bermaksud” yang dapat bermakna niat dapat ditindak dan diartikan sebagai tindak pidana.
Padahal niat tersebut belum terealisasikan menjadi sebuah ancaman yang mengandung rasa ketakutan dan teror. Hal ini akan memberi kewenangan kepada pihak intelijen untuk menangkap siapa saja yang belum tentu terbukti melakukan aktivitas teror tanpa perlu adanya proses penyelidikan dan pembuktikan secara hukum. Tentu kewenangan ini dapat disalahgunakan untuk menyadap atau bahkan menangkap seseorang tanpa orang tersebut berbuat sesuatu.
Disinilah celah besar bagi penyidik/penyelidik untuk dapat melakukan manipulasi dan kriminaliasi terhadap seseorang.
Dalam pasal 20 dan pasal 22 terdapat permasalahan yang dapat menjerat seseorang seolah melakukan tindakan terorisme atau turut merintangi proses peradilan atas kasus terorisme. Pasal-pasal ini membuat seseorang merasa khawatirkan akan dapat dituduh dan dijerat karena sebagai teroris atas tindakan-tindakan yang sebenarnya mengandung faktor kealpaan atau kelalaian
Masalah penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup pun mendapat sorotan. Dalam pasal 26 ayat 1 “Untuk dapat memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.... dst”
Hal ini menjadi masalah karena laporan intelijen bersifat preventif dan prediktif negatif sehingga sulit diuji dan masih memerlukan tindak lanjut dan kurang tepat dijadikan bukti permulaan. Penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan menimbulkan celah hilangnya hak pembelaan diri atas tersangka dan timbulnya keputusan yang subjektif.
Masa penangkapan yang hanya berdurasi 7x24 jam jika ditinjau dari proses penegakkan hukum dan semangat pemberantasan terorisme masih jauh dari cukup namun perspektif HAM akan mempermasalahkan viliditas proses hukum penangkapan seseorang. Dalam hal ini mengingat terorisme merupakan extraordinary crime maka diperlukan pengecualian dan penyesuaian sesuai konteks dan anatomi kejahatan terorisme sehingga proses hukum dapat berjalan tanpa menabrak nilai-nilai HAM.
Dalam hal alat bukti, UU No. 15/2003 dalam pasal 27 menyebut adanya alat bukti selain yang tercantum dalam KUHAP. Alat bukti dimaksud dalam pasal 27 diantaranya :
1. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik atau dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
2. Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, termasuk tetapi tidak terbatas pada (1) Tulisan, suara atau gambar; (2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya dan (3) Huruf, angka, tanda, simbol atau perforasi
Alat-alat bukti dalam pasal 27 tersebut memang tidak disebut dalam KUHAP. Namun alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai data penunjang bagi alat bukti dan yang penting bagi penyidik adalah bagaimana memperoleh alat bukti penunjang tersebut. Jika diperoleh secara tidak sah maka menjadi tidak sah dijadikan alat bukti di pengadilan.