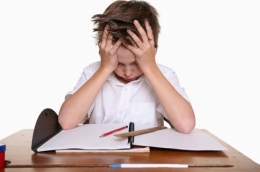Problema keluarga tentang orangtua yang terlalu memaksakan anaknya mengikuti berbagai les tambahan masih banyak terjadi di perkotaan. Sejak masih duduk di sekolah dasar (SD), anak-anak zaman sekarang sudah dijejali dengan seabrek kegiatan ekstrakulikuler di samping tekanan untuk mendapatkan nilai bagus dari mata pelajaran di sekolah.
kisah nyata yang mengisahkan seorang anak yang depresi karena terlalu dipaksa untuk belajar. Cerita ini dikutip dari laman akun Facebook Esther Liem
"Umur 2,5 tahun, Dino (nama samaran) anakku, mulai aku sekolahkan di sebuah sekolah unggulan. Rutinitasnya setiap pagi tidak lagi bergelayut manja di lenganku, tapi ribet dengan urusan persiapan sekolah. Tak jarang, Dino berangkat mandi masih terhuyung dalam kantuknya. Sering saat berangkat ke sekolahnya di mobil dia kembali tertidur. Namun aku mengabaikan perilaku ini, karena aku yakin suatu saat akan berubah seiring bertambahnya umur. Dan lagi, saat bermain dengan teman-temannya Dino terlihat gembira.
Dino termasuk anak pintar, di umur 3.5 tahun sudah mampu berhitung angka sampai bilangan 100, menghafal kata-kata dalam bahasa Inggris, bernyanyi dalam bahasa Inggris yang memang menjadi bahasa utama di sekolahnya. Siapa orang tua yang tidak bangga? Saat berkumpul dengan teman atau keluarga besar, Dino selalu mengundang decak kagum. Pun, postinganku di media sosial, penuh dengan pujian.
Tepat di usia 6 tahun 2 bulan, Dino masuk Sekolah Dasar. Selain kegiatan sekolah, hari-hari Dino diisi dengan bermacam les semua mata pelajaran, berenang, dan bermain musik. Dino patuh sekali mengikuti jadwal yang aku buat. Pada penerimaan rapor semester pertama-nya, semakin aku dibuat kagum dengan hasilnya yang sangat baik. Apalagi saat guru-nya mengatakan bahwa Dino adalah siswa unggulan di kelasnya.
Petaka dimulai saat liburan. Dino tidak mau bangun dari tidurnya. Matanya sayu dan tidak bercahaya. Badannya lemas, tapi tidak panas, Dino pun tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi di tubuhnya. Singkat cerita keadaan ini berlangsung hampir 2 minggu, semua dokter ahli bahkan profesor punya berbagai diagnosa namun selalu meleset saat dihadapkan pada hasil test darah dan test lainnya.
Di tengah kebingungan kami, seorang teman menyarankan membawa Dino ke seorang psikolog. Saran yang pada awalnya membuatku emosi karena seolah-olah menganggap Dino sebagai anak yang sakit mental. Untunglah suami saat itu kekeuh memaksa mencoba cara ini.
Di ruang "curhat" psikolog, Dino hanya bicara berdua saja. Kami menunggu di ruang lain. Hampir 2 jam kami menunggu sampai akhirnya giliran kami tiba. Dino yang diijinkan menunggu di ruangan yang sama, namun dengan jarak yang membuatnya tidak bisa mendengar pembicaraan kami, dibuat sibuk oleh si psikolog dengan buku warna.
Bagai guntur di siang bolong saat kami mendengar penjelasan psikolog itu. Dino mengalami kelelahan mental, namun dia tidak mampu mengungkapkan. Jadwal aktifitasnya yang bertubi-tubi sejak pertama kali dia sekolah (yang berarti 3.5 tahun lalu) adalah penyebabnya. Dino tidak menikmati aktifitasnya, tapi dia berusaha menurut untuk menyenangkan kami (sungguh ini menusuk hati kami).
Kami pulang dan sama-sama terdiam. Air mataku meluncur tidak tertahankan. Bagaimana bisa aku merusak mental anakku selama ini, bahkan malah menganggap itu sebagai proses kebaikan untuknya.
Sampai di rumah, Dino langsung masuk ke kamarnya, sementara kami berembuk, memutuskan apa yang harus kami lakukan. Pertama yang kami lakukan malam itu adalah meminta maaf pada Dino. Selama ini kami benar-benar mengabaikan hak-nya. Selanjutnya kami memutuskan mengurangi dengan sangat drastis jam-jam les Dino. Hanya mempertahankan apa yang Dino mau yaitu les musik saja.
Tidak lama setelahnya, kami mulai mendapatkan Dino yang sesungguhnya, Dino yang ceria, Dino yang bersemangat. Tanpa mengikuti les pelajaran yang bejibun, nilai - nilai Dino tetap membanggakan (padahal kami sudah bersepakat tidak akan mempermasalahkan nilai sekolahnya apapun hasilnya).
Dalam tulisan yang hingga kini sudah dibagikan 28 ribu kali itu, Esther Liem juga mencantumkan sebagian nasihat dari psikolog yaitu:
1. Sistem Pendidikan di Indonesia kebanyakan masih mengutamakan kecerdasan intelektual. Tidak heran di usia yang masih sangat dini, anak sudah diajari membaca, menulis dan berhitung. Sebisa mungkin carilah pra sekolah yang 'hanya bersenang-senang', tanpa membebani otak anak dengan hal-hal yang belum waktunya diterima oleh otak anak. Atau kalau pun itu tidak bisa dihindari, di luar jam sekolah jangan lagi menambahi beban mental anak dengan memaksa belajar hal-hal yang belum perlu benar.
2. Arahkan anak pada hal-hal yang positif namun harus tetap mengedepankan apa keinginan anak.
3. Tidak membebani anak dengan tugas 'kamu harus menjadi nomor satu' untuk hal apapun. Tunjukkan dan buktikan, bahwa tanpa anak menjadi nomor satu, anak tetaplah istimewa untuk orang-orang di sekitarnya.
4. Tidak mengekspos kepandaian anak di muka umum dan di media sosial, karena itu menjadi beban besar untuk anak.
Di akhir postingannya, Esther berharap semoga kisah yang ia sampaikan menjadi pencerahan dan tentunya bisa jadi pelajaran untuk semua orang tua.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H