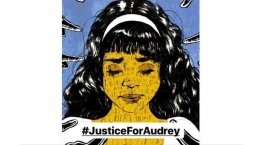Jagat belantara maya saat ini sedang memberikan perhatian penuh pada kasus Audrey. Bocah perempuan 14 tahun asal Pontianak itu menjadi korban perundungan (bully) oleh 3 anak SMA yang juga perempuan, 29 Maret 2019 lalu.
Awalnya, dikabarkan pelaku pengeroyokan adalah 12 orang, namun kabar terakhir yang diduga melakukan pengeroyokan hanya 3 orang. Sementara 9 siswi lainnya hanya sebagai suporter. Ikut bahagia melihat Audrey dikeroyok tanpa memberikan pertolongan.
Namun sebelum saya meneruskan tulisan ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sebagai penulis sekaligus berlatar wartawan, saya sudah ikut membuat kesalahan yakni menulis lengkap nama korban. Padahal sesuai ketentuan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang dirilis Dewan Pers, tidak diperbolehkan menyebut nama korban dan pelaku.
Khusus Audrey berbeda. Justru bocah perempuan ini dengan berani meminta wajahnya tidak usah diburamkan, dan meminta namanya boleh ditulis lengkap. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa dirinya kuat dan berani. Apa yang dilakukan diharapkan bisa menjadi simbol perlawanan pada aksi perundungan yang bisa menimpa siapa saja dan kapan saja.
Kasus seperti ini seperti fenomena gunung es. Tak terlihat, tapi banyak terjadi. Korban memilih diam karena trauma dan berada di bawah tekanan. Saya dulu ketika masih sekolah juga pernah jadi korban bully. Dipukul teman sekelas di tempat sepi. Juga memilih diam. Beruntung saat ini sudah paham teknik terapi mandiri, sehingga semua trauma itu bisa saya atasi sendiri dengan mudah.
Kembali pada kasus Audrey. Bocah ini benar-benar menjadi korban. Target para pelaku sebenarnya adalah sepupunya. Sang kakak sepupu yang juga duduk di bangku SMA, ternyata pernah menjalin asmara dengan pacar salah satu pelaku pengeroyokan. Akibat persoalan asmara inilah berlanjut di media sosial, kemudian berujung pada aksi penganiayaan.
Beruntung kasus ini kemudian viral, sehingga langsung menyedot perhatian publik. Presiden Joko Widodo pun ikut memberikan perhatian. Harapannya, penegak hukum tak punya celah bermain-main. Kenapa? Karena masyarakat pasti akan ikut mengawasinya.
Dari kasus tersebut bisa dilihat betapa aksi perundungan di era media sosial ini sudah sangat mengkhawatirkan. Bully secara verbal apalagi secara fisik, memberikan dampak luar biasa bagi korbannya. Tak hanya terluka secara fisik, bahkan berdampak luka batin secara psikologis.
Sebagai informasi, hampir sebagian besar kasus yang saya tangani di ruang praktik hipnoterapi, akar masalahnya disebabkan bully yang dialami di masa lalu. Sama seperti yang dialami Audrey saat ini. Jika tidak segera mendapatkan pemulihan secara psikologis, tentu dampaknya akan sangat berbahaya bagi masa depan Audrey. Beruntung bocah tersebut kini sudah mendapat penanganan serta perlindungan secara maksimal. Termasuk mendapat pendampingan psikolog.
Mencuatnya kasus Audrey juga diharapkan memperkuat semangat dan motivasi anak-anak korban bully lainnya agar berani menceritakan apa yang dialaminya. Sehingga kasus itu tidak didiamkan begitu saja. Kalau didiamkan, pelaku akan merasa apa yang dilakukannya adalah hal wajar. Sementara sang korban akan menanggung dampak trauma mendalam secara terus-menerus, bertahun-tahun. Bahkan bisa sampai dibawa mati.
Lantas kenapa ketiga pelaku bisa melakukan perbuatan seperti itu? Anak berbuat, orang tua yang disalahkan. Umumnya orang akan berpendapat seperti itu. Sebagai hipnoterapis, saya pun akan berpendapat sama.
Anak yang berani melakukan kekerasan verbal maupun fisik, boleh jadi disebabkan pola asuh yang kurang tepat. Ingat, ini hanya sebatas dugaan. Namun berdasarkan temuan di ruang praktik, pola asuh memang sangat menentukan tumbuh kembang anak. Selain pola asuh, lingkungan juga ikut menentukan.
Coba perhatikan kasus Audrey. Betapa para pelaku itu sudah begitu tipis hati nuraninya. Tak hanya tega melakukan kekerasan, namun merasa tak bersalah ketika kasus itu muncul di permukaan. Ketiga terduga pelaku bahkan sempat berswafoto dan mengunggahnya di akun media sosialnya. Termasuk sempat mengunggah kalimat bernada menantang para warganet yang mengikuti perjalanan kasus ini.
Fakta lain dari warganet, apa yang mereka lakukan ternyata bukan kali ini saja. Kabarnya, para terduga pelaku yang merupakan satu kelompok genk itu sudah pernah melakukan pengeroyokan. Bedanya, kali ini mencuat ke permukaan.
Lantas, kenapa anak seusia itu bisa melakukan tindakan sadis? Kira-kira apa penyebabnya? Tentu saya pun tidak bisa melakukan penghakiman terlalu cepat. Harus ditelusuri dengan cermat bagaimana pola asuh dan kondisi lingkungan dari para pelaku.

Apalagi konon katanya para pelaku anak orang kaya atau punya jabatan. Maka boleh jadi pola asuh yang didapatkan selama ini selalu dimudahkan dan dimanjakan. Apa pun yang diinginkan selalu terpenuhi. Akibatnya, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai keinginan, kekerasan dipilih menjadi jalan keluarnya.
Boleh jadi mereka sudah biasa melakukan pengeroyokan. Bisa dilihat dari bukti yang beredar di media sosial dan mengenali para pelaku. Ada rasa bangga dan puas memiliki identitas diri dari aksi yang dilakukan. Belum lagi ada yang menyampaikan bahwa mereka berani melakukan itu karena merasa selalu mendapat backing alias perlindungan kedua orang tuanya. Tentu tidak semua anak orang kaya dan punya jabatan seperti itu. Banyak pula yang baik dan mampu mendidik anaknya dengan baik.
Audrey memang korban. Tapi sejatinya, para pelaku juga korban dari ketidakmampuan orang tuanya memberikan pola asuh yang tepat. Yang menjadi pertanyaan mendasar, kenapa anak di bawah umur itu sampai berani melakukan tindakan begitu kejam? Apakah kekerasan dan kekejaman sejatinya sudah akrab dalam kehidupan sehari-hari mereka? Bukankah sebuah kekerasan terus menerus, jelas akan memberikan dampak fatal secara psikologis.
Lagi-lagi saya ingin mengambil contoh nyata dari ruang praktik yang pernah saya lakukan. Beberapa kali saya mendapat klien dari keluarga yang seolah-olah baik, tapi nyatanya ada 'sesuatu' di baliknya. Umumnya masalah yang dikeluhkan adalah stress, emosi yang tidak terkendali, dendam, sakit hati, hingga trauma.
Ternyata, yang menjadi akar masalah dari persoalan di atas adalah pola asuh dari orang tua yang kurang maksimal memberikan kasih sayang. Fakta penting inilah yang perlu saya ungkapkan agar menjadi pelajaran penting bagi semuanya.
Pelaku sampai tega melakukan pengeroyokan yang tidak semestinya, boleh jadi karena pola didik yang diajarkan jauh dari kelembutan dan kasih sayang. Sehingga membuat para pelaku berani mengambil tindakan di luar nalar. Namun sekali lagi, ini hanya analisis. Soal kejadian yang sebenarnya, biarlah pengadilan nanti yang membuktikan.
Selain itu, dari kejadian ini, sudah sepatutnya kita mengambil hikmah dan pelajaran, agar mendidik anak dengan kelembutan dan kasih sayang. Tak selamanya kekerasan bisa menyelesaikan masalah. Sebaliknya, ketenangan dan kelembutan hati, akan mampu menaklukkan siapa saja.
Andai saja diberikan kesempatan bertemu para pelaku pengeroyokan dan bisa berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar mereka, tentu akan mudah diketahui, apa akar masalah sesungguhnya yang membuat mereka sampai berani melakukan penganiayaan.
Saya sangat yakin 1.000 persen, yakin seyakin-yakinnya, pasti ada akar masalah utama yang menjadikan para pelaku memiliki keberanian seperti itu. Namun akar masalah itu hanya bisa diketahui dalam proses hipnoanalisis pada kedalaman pikiran bawah sadar yang presisi. Sebab, pada kedalaman itulah semua data dan fakta akan keluar dengan sendirinya secara rinci.
Dari pola asuh tersebut, biasanya ditemukan benang merah yang membuat si anak melakukan berbagai perilaku menyimpang tersebut.
Setidaknya, ada empat hal yang menjadi alasan, kenapa anak melakukan tindakan yang membuat gempar media massa dan media sosial itu. Ini seperti yang ditulis pakar teknologi pikiran, Adi W. Gunawan dalam bukunya Hypnotherapy for Children.
Pertama, untuk mendapat perhatian. Ya, di era digital dan serba sibuk seperti sekarang ini, tak sedikit anak yang memang sangat kekurangan perhatian dari kedua orang tuanya. Ayah sibuk bekerja, begitu juga sang ibu juga tak mau melepas karirnya yang sedang bersinar. Akibatnya, anak menjadi korban dan kurang perhatian.
Alih-alih menuruti semua permintaannya sebagai ganti perhatian dan kasih sayang, namun faktanya semua yang diberikan itu tidak dapat menggantikan kebutuhan kasih sayang anak dari kedua orang tuanya.
Dalam buku Lima Bahasa Cinta karya Gary Chapman disebutkan, orang tua wajib mengisi kasih sayang anak. Mengisi kasih sayang anak tidak boleh dilakukan pembantu, baby sitter, atau kakek dan neneknya. Yang paling utama harus dilakukan kedua orang tuanya. Cara mengisi baterai cinta anak adalah dengan pujian, hadiah, waktu yang berkualitas, sentuhan, dan layanan.
Umumnya, orang tua yang super sibuk, hanya bisa memenuhi kebutuhan hadiah. Namun empat bahasa cinta lainnya, sangat diabaikan. Tidak pernah memberikan pujian pada anak. Kalau pun memuji hanya sekadarnya, tidak tulus dari dalam hati.
Anak juga jarang memiliki waktu berkualitas dengan kedua orang tuanya. Momen kebersamaan jarang didapatkan anak dengan kedua orang tua yang sangat sibuk. Bahkan ketika anak sedang berjalan-jalan dengan orang tuanya ke pusat perbelanjaan, secara fisik memang berdekatan. Namun, hati mereka saling berjauhan, karena masing-masing sibuk dengan gadget-nya.
Apalagi sentuhan dan layanan, anak jarang sekali mendapatkan hal ini ketika mendapati kenyataan, kedua orang tuanya mengabaikan keberadaannya. Sentuhan dan layanan umumnya diberikan oleh pembantu atau baby sitter. Jangan heran jika anak kemudian lebih dekat dan sayang dengan pengasuhnya.
Orang tua hanya memproduksi anak, sementara sejatinya anak itu sudah menjadi anak pengasuh, atau anak dari kakek dan neneknya.
Kedua, untuk mendapatkan kekuasaan atau mengalahkan orang tua. Kedengarannya memang ekstrem. Ya anak yang selama ini tertekan, tentu pikiran bawah sadarnya akan berontak. Pikiran sadar, tentu kalau ditanya tidak akan merasa melakukan hal ini. Namun ketika diakses ke dalam pikiran bawah sadar, ternyata sudah terbentuk pola, anak harus bisa menguasai dan mengalahkan orang tua. Pembaca tentu pernah melihat, ada anak yang bisa mendapatkan semua hal yang dia inginkan.
Jika minta sesuatu dan tidak diberi, maka anak akan mengamuk dan menangis sembari berteriak sekencang-kencangnya. Ini adalah indikasi, anak selama ini tertekan. Akibatnya, dia ingin membalas tekanan itu kepada orang tuanya. Anak akan merasa sangat puas jika melihat kedua orang tuanya kebingungan dengan sikapnya.
Anak akan merasa menang dan bangga setelah bisa mengendalikan orang tuanya. Coba saja perhatikan anak-anak yang dititip sama kakek-neneknya atau dengan pengasuhnya. Ketika dengan pengasuh atau kakek-neneknya, si anak terbukti anteng saja dan tidak bermasalah. Tetapi ketika kedua orang tuanya datang, biasanya langsung berubah total.
Lagi-lagi, itu adalah indikasi bahwa anak selama ini sudah merasa disisihkan dan merasa tidak berguna, sehingga dia pun berbalik ingin menguasai perasaan orang tuanya. Melihat anaknya seperti ini, orang tua biasanya mau tidak mau menuruti kemauan anak, sebagai ungkapan rasa bersalah, sudah meninggalkan anaknya untuk bekerja.
Ketika beranjak dewasa, dan tetap kurang kasih sayang, anak kemudian mendapatkan hal tersebut dari kelompok, komunitas, atau genknya. Inilah yang kemudian perlahan menjadi pengendali anak, yakni identitas kelompok yang harus dipertahankan.
Ketiga, untuk membalas dendam dan menghukum orang tua yang menolak memberikan perhatian pada anak, atau yang memaksa anak menuruti kemauan mereka. Dari sini bisa dilihat bahwa anak sengaja melakukan penyimpangan perilaku untuk memuaskan dendamnya kepada orang tuanya yang selama ini sudah mengabaikan dirinya.
Secara sadar, anak memang tidak tahu jika dia melakukan hal tersebut. Namun di dalam pikiran bawah sadarnya, sudah terbentuk pola bahwa dia harus bertindak aneh, agar orang tuanya bisa 'tersiksa'. Pikiran bawah sadar anak sudah membentuk pola, bahwa orang tua yang tidak perhatian juga layak mendapat hukuman dengan cara mereka. Misalnya meminta sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal, sehingga membuat orang tuanya stres.
Yakinlah, orang tua pelaku pasti tidak nyaman ketika anaknya saat ini menjadi perhatian publik. Sementara bagi pelaku, hal-hal tersebut sengaja dilakukan supaya orang tuanya stres. Jika orang tuanya puyeng dengan sikap mereka, maka program yang dijalankan anak otomatis berhasil. Begitu pula jika orang tua terlalu memaksakan kehendaknya, maka anak pun punya cara tersendiri untuk berbalik menekan orang tua dengan permintaan tertentu.
Hal seperti ini, jarang terjadi pada anak yang sudah mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya secara utuh. Anak akan mudah menuruti kemauan orang tuanya, jika selama ini memang sudah terjalin kebersamaan dan kasih sayang yang sangat mendalam.
Keempat, menjadi tidak produktif atau sakit, dan memaksa orang tua merasa kasihan dan melayani anak. Pernah mendapati anak yang mudah sakit? Padahal, sakitnya ya itu-itu saja. Demam, flu, atau sakit ringan lainnya, yang sejatinya bisa sembuh hanya dengan istirahat yang cukup. Ternyata, anak sengaja merasa sakit, agar dirinya bisa mendapat pelayanan dari kedua orang tuanya.
Mendidik anak memerlukan keseriusan. Tidak sekadar memenuhi kebutuhannya secara materi. Lebih dari itu, berikan kasih sayang melalui lima bahasa cinta dengan tatapan mata yang tulus dan penuh empati. Sebagai penutup, berikut kutipan dari Dorothy Law Notle yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia:
Bila seorang anak hidup dengan kritik,
Ia belajar untuk menyalahkan.
Bila seorang anak hidup dengan kekerasan,
Ia belajar untuk berkelahi.
Bila seorang anak hidup dengan ketakutan,
Ia belajar untuk menjadi penakut.
Bila seorang anak hidup dengan rasa benci,
Ia belajar untuk tidak menghargai hidup.
Bila seorang anak hidup dengan ejekan,
Ia belajar menjadi pemalu.
Bila seorang anak hidup dengan rasa malu,
Ia belajar merasa bersalah.
Bila seorang anak hidup dengan perasaan iri,
Ia belajar menjadi iri hati.
Bila seorang anak hidup dengan berbagi,
Ia belajar kemurahan hati.
Bila seorang anak hidup dengan toleransi,
Ia belajar menjadi sabar.
Bila seorang anak hidup dengan dukungan,
Ia belajar kepercayaan diri.
Bila seorang anak hidup dengan pujian,
Ia belajar untuk menghargai.
Bila seorang anak hidup dengan penghargaan,
Ia belajar untuk mempunyai tujuan hidup.
Bila seorang anak hidup dengan rasa adil,
Ia belajar tentang keadilan.
Bila seorang hidup dengan rasa aman,
Ia belajar memiliki kepercayaan diri.
Bila seorang anak hidup dengan persetujuan,
Ia belajar menyukai dirinya sendiri.
Bila seorang anak hidup dengan penerimaan dan persahabatan,
Ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan.
Jika anda hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan,
Anak anda akan hidup dengan pikiran yang damai
Kehidupan seperti apa yang anak Anda jalani? (*)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H