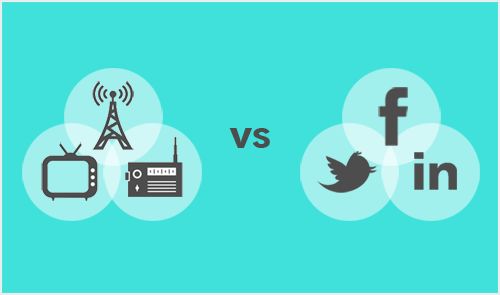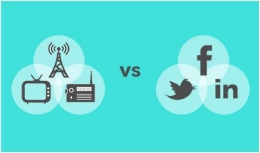Atas nama keamanan dan ketertiban, pemerintah akhirnya mengintervensi media sosial. Meski konon untuk sementara saja. Dua tiga hari ini, menyusul aksi demo yang diikuti tindak kerusuhan pasca pengumuman hasil akhir pemilu oleh KPU. Ada kesan pemerintah panik menghadapi dampak media sosial.
Meski akurasi fakta adalah problem utama media sosial---sebagaimana banyak dibincangkan secara akademis, media ini justru menjadi kanal rasa frustasi sebagian orang. Setelah media sosial rusak kredibiltasnya, dengan berbagai kasus hoaks, diandaikan orang akan kembali mengandalkan media arus utama (mainstream).
Setidaknya itu yang diramalkan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam bukunya 'Blur' (2011). Kenyataannya, ada sekelompok orang yang justru makin yakin media sosial merupakan alternatif ketika semua media dianggap telah 'dibeli'.
Itu yang saya (dan mungkin juga Anda) rasakan, setelah ketemu dengan beberapa orang yang anti media arus utama. "Media sudah dibungkam". "Media sedang sakit". Itu beberapa ungkapan mereka. Saat berdebat dengan mereka tentang satu isu, saya sebut berita dari media popular, saya malah di-bully. "Pantes saja kesimpulanmu keliru. Kamu masih percaya TV dan koran," kata dia. Duh!
Tidakkah mereka sadar media sosial telah menjadi sarana massal penyebaran kabar bohong? Entahlah. Saya sering mendapat informasi hoaks dari teman-teman ini. Saya katakana ini tidak benar alias palsu. Tapi mereka bergeming, dan terus saja berkirim kabar yang saya ragukan otentisitasnya. Mungkin mereka terus berusaha agar suatu saat nanti saya tersadar, bahwa media sosial lah satu-satunya harapan kini, setelah pemerintah tersandera oleh kepentingan Asing dan Aseng. Hehe..
Di perjalanan dari sekolah tadi siang, anakku bercerita tentang temannya yang panik menjelang liburan. Dia warga keturunan Arab. Dia khawatir, karena mendapat kabar kalau Jokowi menang akan ada Razia warga keturunan Arab. Dalam hati, aku pengen ketawa sekaligus sedih. "Pasti temannmu lebih banyak baca WA, ketimbang baca koran atau TV," kataku. Anakku membenarkannya.
Okelah, akhirnya aku memberi kuliah singkat pada anakku tentang media sosial dan media mainstream. Kenapa aku masih lebih percaya media arus utama? Media mainstream bisa kita batasi sebagai media popular, dengan badan hukum yang jelas, dan terverifikasi oleh Dewan Pers. Dia bisa berbentuk koran, radio, televisi, atau media online. Pada umumnya, media seperti ini sudah berdiri lama dan mendapat tempat di hati khalayak.
Sebagai perusahaan yang berorientasi bisnis, media mainstream lazimnya akan menjaga kredibilitas. Dengam modal kepercayaan, media seperti ini akan masih bias diterima khalayak. Sekali salah, bisa hilang pembaca atau pemirsa. Jadi atas nama bisnis, media seperti akan akan mengubur diri sendiri jika menyajikan berita palsu.
Para wartawan di media mainstream pada umumnya para professional. Mereka adalah para sarjana yang telah mendapat pembekalan khusus tentang etika jurnalistik. Mereka juga umumnya tergabung dalam serikat profesi yang diikat oleh kode etik. Jadi para wartawan itu bekerja untuk mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi dengan kerangka etis. Mereka hanya boleh mengkabarkan fakta, bukan fantasi.
Apakah para wartawan itu pasti benar? Tentu saja tidak. Mereka manusia, tentu sangat bisa salah. Pernah terjadi di Indonesia, beberapa media besar menyiarkan hoaks. Jawa Pos misalnya, pernah wartawannya melakukan wawancara palsu. TVOne juga pernah melakukan hal serupa. Metro TV pernah menyiarkan video palsu. Mungkin bukan media itu yang berniat jahat, tapi ada oknum yang bekerja di luar kaidah etik.
Pada media seperti ini, khalayak mudah mengontrol. Lembaga dan orang-orangnya jelas. Maka, dalam kasus di atas, praktik disiinformasi itu segera bisa diketahui. Nah, bayangkan kalau ini terjadi di media sosial, yang kadang bahkan penulisnya kita tidak tahu.
Pada akhirnya, kepercayaan pada media mainstream ini lebih pada sistem yang mengontrolnya. Orang bisa salah, tetapi ada sistem yang bisa mengoreksinya. Ada Dewan Pers yang memantau kerja media-media ini. Juga ada asosiasi wartawan yang melakukan kontrol pada para anggotanya.
Inilah kendala media sosial. Media ini memang bisa menjadi alternatif. Ketika media besar hanya bisa diakses mereka yang punya kuasa, media sosial menjadi milik siapa saja. Ini media rakyat. Gagasan pewarta warga (citizen journalism) menjadi makin nyata dengan hadirnya media sosial.
Tapi satu kendala bagi pewarta warga ini adalah belum hadirnya sistem kontrol. Selain yang tergabung dalam komunitas yang jelas, sebagian besar netizen yang menjadi pewarta ini sejatinya adalah kerumunan besar yang sulit diidentifikasi siapa sesungguhnya mereka. Penumpang gelap kebebasan informasi ada dalam kerumunan ini. Mereka inilah para penyebar hoaks.
Para pembuat dan penyebar hoaks inilah yang mengancam dan merusak demokratisasi informasi melalui media sosial. Mereka memanfaatkan kecenderungan sebagian netizen yang emosional, reaktif, dan tidak berpikir terbuka. Faktanya, kabar bohong laku, sehingga telah menjadi industri tersendiri.
Bagaimana dengan media saat ini yang sebagiannya partisan? Oke, kita tak bisa menampiknya. Tanpa bermaksud membenarkannya, keberpihakan mereka rasanya tak sampai pada manipulasi fakta. Paling banter kebepihakan itu ditampilkan dalam bentuk 'framing': berita menjadi favorable untuk kelompoknya dan unfavorable untuk sebelah.
Dalam benak teman-teman yang tak percaya media arus utama ini, semua sudah 'terbeli'. Bagi yang tahu kerja para wartawan, sulit membayangkan semua wartawan itu bersekutu untuk menyebarkan informasi palsu. Okelah, seandainya para pemimpinnya sudah 'dipegang', misalnya untuk kepentingan politik tertentu, muskil rasanya para wartawan akan menurut begitu saja. Saya pernah jadi wartawan, sehingga tahu persis bagaimana praktik jurnalistik di lapangan.
Sungguh saya tak bermaksud memuja media arus utama. Tentu banyak catatan untuknya. Tapi dalam konteks disinformasi yang makin parah, keberadaan media populer ini menjadi relevan, khususnya untuk soal akurasi fakta.
Dalam silang sengkarut informasi, antara media mainstream dan media sosial bisa saling melengkapi. Para professional di media arus utama bisa menjadi standar praktik jurnalistik yang akurat. Sedangkan netizen di media sosial bisa menutupi kelemahan wartawan professional dalam menjangkau fakta yang tersebar luas.
Tak terasa kami sudah sampai di depan rumah. Entahlah apakah anakku paham atau belum. Setidaknya, dengan ceramah singkat itu, terasa ada sedikit beban yang berkurang sebagai pengajar jurnalistik. Hehe
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H