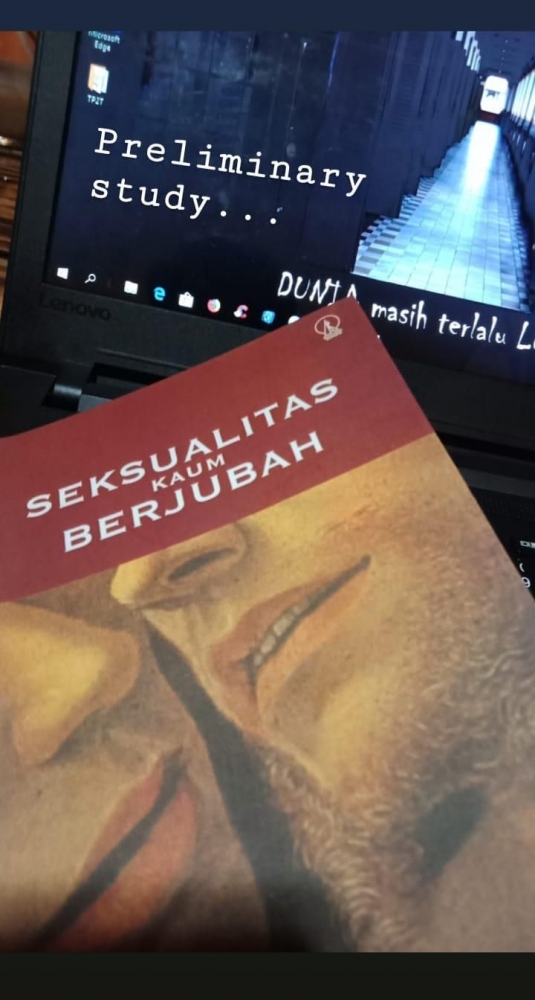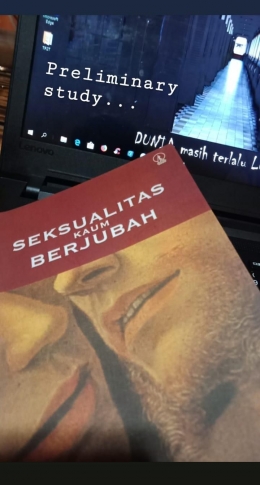Kasus pelecehan seksual oleh rohaniwan Katolik, adalah fakta yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan, Sekretaris Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Paulus Christian Siswantoko pun mengakui secara jelas bahwa ada cukup banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh para rohaniawan Katolik di Indonesia.
Siswantoko mengakui bahwa kasus tersebut menjadi persoalan tersendiri di internal Gereja Katolik di Indonesia yang kadang lamban ditangani. Ia pun tak menampik bila ada segelintir kalangan rohaniawan yang belum memiliki kematangan pribadi meskipun sudah melewati berbagai tahapan dan tingkatan pendidikan dalam proses formasi menjalani hidup selibat, (CNN Indonesia | Rabu, 11/12/2019).
Sebagai data pembanding, saya meneruskan berita dari Katolik-News.com pada 30 Desember 2019 yang mengutip Majalah Warta Minggu yang diterbitkan oleh Paroki Tomang-Gereja Maria Bunda Karmel (MBK), Keuskupan Agung Jakarta. Dalam majalah tersebut disajikan laporan yang memicu pembicaraan luas, terkait pelecehan seksual di dalam Gereja Katolik di Indonesia.
Majalah milik paroki yang dilayani para imam Karmel itu melaporkan setidaknya sekitar 56 orang mengalami pelecehan seksual di dalam Gereja Katolik di seluruh Indonesia. Laporan yang berjudul “Pelecehan Seksual di Gereja Indonesia: Fenomena Gunung Es?” itu, diterbitkan pada edisi Minggu, 7 Desember 2019. Saya kira ini belum seberapa, karena kita tahu ada 37 keuskupan di Indonesia, dan kalau satu Keuskupan terdapat 5 kasus saja, maka jumlahnya jelas sangat banyak.
Dari fenomena ini, salah satu hal yang perlu diperhatikan secara serius adalah bentuk dan proses formasi para calon Pastor atau para Rohaniwan/Biarawan-ti Katolik (kaum selibater pada umumnya). Saya kira dalam menghadapi era saat ini, mereka tidak boleh dan tidak bisa hanya belajar Filsafat dan Teologi saja, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah pendidikan seks atau pemahaman mengenai seksualitas.
Mungkin sudah ada dalam masa formasi tersebut, tetapi kurang intens diperhatikan sehingga tidak diresapi dan direfleksikan secara mendalam. Karena itu, guna meminimalisir persoalan pelecehan seksual para rohaniwan Katolik, maka pendidikan seks atau pemahaman tentang seksualitas perlu menjadi kebutuhan yang urgen.
Dalam kasus ini, saya coba beri kisah dari proses pendidikan dan pembinaan di Seminari Tinggi. Di tingkat ini, seorang Seminaris biasa dikenal dengan sebutan Frater (Latin: Saudara). Seorang Frater merupakan panggilan bagi laki-laki beragama Katolik yang memutuskan untuk hidup selibat dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan.
Bagi laki-laki yang memilih untuk menjadi seorang frater, berarti dirinya telah memutuskan untuk mengabdikan hidupnya hanya kepada Tuhan dan tinggal di dalam Seminari hingga akhir hidupnya, sehingga ia harus secara sukarela meninggalkan setiap kehidupan duniawinya di luar Seminari.
Selain itu, proses pembinaan yang dijalani para frater bertujuan untuk persiapan menjadi seorang Imam atau Pastor Katolik dengan menjalani hidup selibat. Hidup selibat atau kaul kemurnian ini harus dilakukan, ditaati, dan dihayati oleh setiap frater yang menjalani pilihan hidupnya, meskipun tidak mudah untuk menjalaninya.
Kehidupan perkuliahan yang dijalani, interaksi dengan lawan jenis, serta pembinaan hidup rohani yang lebih dalam bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan dan dihayati oleh masing-masing frater. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban, tetapi seorang frater juga manusia biasa yang sama seperti manusia lainnya.
Mereka juga mengalami dan merasakan dorongan kenikmatan duniawi dengan berbagai macam kebutuhan, salah satunya adalah kebutuhan seks. Ini tidak bisa dicegah. Jangan pernah menganggap bahwa ketika seorang frater menerima Sakramen Imamat dalam tahbisan, maka serta merta dirinya menjadi suci dan kudus. Jangan mengira bahwa Sakramen Imamat menjadikan mereka kehilangan hasrat seksual. Itu pemahaman yang keliru.
Berangkat dari situ, saya ingin menghantar kita pada pemahaman tentang hasrat seksual seoang laki-laki pada umumnya. Kita tentu tahu bahwa laki-laki dapat terangsang secara seksual oleh berbagai rangsangan, termasuk rangsangan taktil yang dilakukan oleh pasangan mereka, juga rangsangan visual, atau fantasi seksual. Terlepas dari sumber rangsangan, respons seksual pria, ereksi, dan ejakulasi dapat terjadi secara refleks (Rathus, Nevid & Rathus, 2011: 121).
Hormon seksual pria diketahui mempengaruhi dorongan seks dan respon seksual pada pria (Bialy & Sachs, 2002; Cooke et al., 2003, dalam Rathus, Nevid & Rathus, 2011: 145). Gairah seksual juga dapat dipengaruhi oleh salah satu bagian otak, yang disebut korteks serebral (cerebral cortex). Ketika seorang laki-laki memikirkan aktivitas seksual, gambar, keinginan, dan fantasi seksual, maka sel yang ada di dalam korteks serebral akan menafsirkan informasi sensorik tersebut untuk mengaktifkan atau mematikannya.
Sel ini akan mengirim pesan melalui saraf tulang belakang yang mengirimkan darah ke alat genital dan akhirnya menimbulkan ereksi. Setelah hal ini terjadi, korteks serebral pun juga dapat berfungsi untuk menyadarkan apakah aktivitas seksual tersebut merupakan sesuatu yang tepat atau tidak tepat, dapat menenangkan atau membuat semakin cemas, dan menimbulkan perasaan bersalah atau kepuasan, (Rathus, Nevid & Rathus, 2011: 142).
Prasetya (1992: 199) menyatakan bahwa terdapat beberapa cara sebagai kompensasi yang umumnya dilakukan manusia untuk mengelola kebutuhan psikologis terkait dengan kehangatan dan kepuasan seksual, khususnya biarawan/rohaniwan-ti (dalam hal ini para Frater-calon Pastor dan Pastor Katolik). Beberapa di antaranya adalah dengan melakukan kegiatan lain yang positif, seperti berolahraga, memelihara dan merawat hewan peliharaan, atau dengan cara-cara lain yang dapat dilakukan sesuai minat masing-masing.
Setidaknya saya sepakat dengan William Kraft dalam Celibate Loving, Encounter in Three Dimensions (Suparno, 2007: 83-89), yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki dorongan seksual, namun tidak harus untuk mengungkapkan dorongan itu secara badaniah.
Inilah yang mungkin perlu diperhatikan secara bijak oleh para Pastor, atau calon Pastor, dan juga oleh para Rohaniwan/Biarawan-ti Katolik (atau kaum selibater pada umumnya). Menurut Kraft, setidaknya ada lima cara untuk menghadapi dorongan seksual dalam diri. Silahkan dipilih sesuai kemampuan masing-masing:
Cara yang pertama adalah represi. Secara sederhana, represi mengesampingkan pengalaman seksual dari kesadarannya dengan cara menekan perasaan seksual yang ada, seakan-akan tidak terjadi dalam dirinya. Represi ini bersifat negatif, dapat menimbulkan stress, menjadikan orang mudah marah, merasa sakit, atau kadang dapat menjadikan orang menjadi sedih sendiri dalam komunitas. Represi ini menolak kenyataan bahwa kita manusia yang seksual. Kita menolak bahwa kita diciptakan Tuhan dengan tubuh seksual.
Cara kedua yang dapat dilakukan adalah supresi. Cara ini seperti represi, tetapi dengan kesadaran dan pilihan. Orang mengatakan ‘tidak’ pada sesuatu yang sebenarnya ‘ya’. Supresi ini kadang disebut mortifikasi, mematikan sesuatu dalam diri kita, demi suatu nilai yang lain. Ia tetap seksual, tetapi tidak mau menyalurkannya.
Cara ketiga yang dapat dilakukan untuk menghadapi dorongan seksual adalah sublimasi. Sublimasi adalah tindakan mengarahkan dorongan seksual kepada suatu tindakan atau kegiatan yang lain, seperti kerja, melakukan karya sosial, seni, dan sebagainya. Biasanya, tindakan sublimasi dilakukan karena bertentangan dengan nilai yang ingin dikejar.
Cara keempat yang dapat dilakukan adalah gratifikasi atau pelampiasan. Orang melampiaskan dorongan seksualnya dengan cara melakukan pemuasan secara fisik seperti masturbasi, sanggama, onani dan sebagainya. Pemuasan ini sering dipakai untuk mengurangi loneliness, kekosongan, dan kesepian. Sesudahnya, kekosongannya akan semakin bertambah, dan muncul rasa bersalah. Bagi kaum selibater Katolik, cara ini dinilai tidak baik dan tidak sehat karena tidak mengembangkan pribadi secara menyeluruh.
Cara kelima adalah integrasi. Menurut Kraft, supresi dan sublimasi menjadi cara yang cukup efektif secara psikologis dalam menghadapi dorongan seksual. Tetapi, kelemahan dari kedua cara itu adalah tetap memandang dorongan seksual atau genitalia secara fisik saja, padahal genitalia mempunyai segi lain yang perlu diperhatikan pula.
Karena itu, Kraft menyarankan adanya integrasi yang bernilai, yaitu mengalami genitalia atau dorongan seksual sebagai suatu gejala yang membuka seluruh pribadi manusia. Integrasi berarti melihat dorongan seks sebagai manifestasi seluruh pribadi manusia. Dengan munculnya dorongan itu, kita diundang untuk melihat dimensi yang lebih dalam dari diri kita dan orang lain.
Cara terakhir yang dapat dilakukan adalah menerima hal tersebut sebagai persembahan kepada Tuhan. Banyak Pastor, atau calon Pastor, dan juga para Rohaniwan/Biarawan-ti Katolik (atau kaum selibater pada umumnya), dalam praktek hidup selibat, mengatasi dorongan seksual yang kadang muncul dengan mempersembahkan dorongan itu kepada Tuhan, sambil bertahan dalam tekanan dorongan tersebut.
Mereka sadar bahwa mereka akan sering mengalami dorongan seksual itu seperti setiap orang lain (awam) mengalaminya. Mereka dapat mensyukuri dorongan itu karena menjadi tanda bahwa mereka ternyata memang manusia yang normal. Mereka juga menyadari bahwa pilihan hidup selibat demi Kerajaan Allah, memang tidak mau menyalurkan dorongan itu secara badani lewat hubungan seks.
Maka dorongan itu disadarinya sebagai sesuatu yang memang dipersembahkan kepada Tuhan sekaligus bertahan dalam situasi dorongan ini, akhirnya dorongan itu secara alamiah juga bisa teratasi dengan sendirinya.
Saya kira, pilihan cara yang terakhir ini, bisa menjadi rujukan penting bagi para Pastor, atau calon Pastor, atau para Rohaniwan/Biarawan-ti Katolik (kaum selibater pada umumnya), dalam menjalani hidup panggilan (hidup selibat) demi Kerajaan Allah.
Semoga dengan pemahaman ini, pendidikan seks atau seksualitas dalam proses pembinaan Katolik calon Pastor, atau para Rohaniwan/Biarawan-ti Katolik, bisa menjadi hal yang paling urgen untuk diindahkan, agar ke depan, persoalan pelecehan seksual dalam Gereja Katolik bisa teratasi. Berusahalah untuk ‘lebih ajar’ tentang seksualitas agar tidak ‘kurang ajar’ dengan bebas.
Sumber Bacaan:
Prasetya, F. M. (1992). Psikologi Hidup Rohani 2. Yogyakarta: Kanisius
Rathus, S.A., Nevid, J.S. & Rathus, L.F. (2011) Human Sexuality in a world of Diversity. Edisi ke-8. USA: Pearson Education, Inc.
Suparno, P. (2006). Spiritualitas dan Seksualitas dalam Hidup Membiara. Rohani Menjadi Semakin Insani: Menopang Impian Terpendam. Yogyakarta: Kanisius.
Suparno, P. (2007). Seksualitas Kaum Berjubah. Yogyakarta: Kanisius.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H