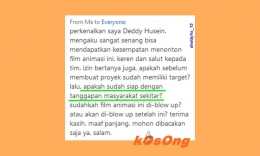Saya berusaha tahu bagaimana perasaan si lelaki, karena dia terus diejek oleh teman seperkumpulannya. Siapa sih orang yang mau diejek oleh temannya sendiri?
Tetapi, sebagai seorang lelaki dan kepala rumah tangga seharusnya dia bisa melakukan tindakan yang sepantasnya ia lakukan, yaitu membela istrinya. Sebagai suami, seharusnya dia sangat tahu apa yang terjadi pada istrinya. Itulah yang kemudian dapat menjadi modalnya untuk menangkal suara-suara sumbang yang meneror telinganya.
Babak keempat. Ini lebih ke konflik batin perempuan zaman sekarang. Itu tidak lepas dari usia si tokoh perempuan keempat yang masih 'kepala dua', dan dia sudah menikah.
Artinya, dia memiliki tantangan yang selangkah lebih maju dari perempuan lajang. Apa itu?
Memiliki momongan.
Sebenarnya, saya sempat memasang label feminisme kepada tokoh ini. Tetapi, ketika saya tahu bahwa si suaminya juga masih belum siap punya momongan, maka saya pikir ini faktor psikologis.
Artinya, pemicu dari pasangan suami-istri yang belum memiliki momongan itu bukan hanya karena pola pikir, tetapi juga kesiapan mental. Pada faktor ini, saya pun setuju. Mengapa?
Banyak anak di semua generasi sering terlihat susah tumbuh dan berkembang dengan baik, karena mereka lahir di orang tua yang cenderung belum siap mental untuk mengasuh dan mendidiknya. Anak itu bukan hanya barang titipan yang diterima lalu dipajang, atau malah hanya ditaruh di atas lemari pakaian.
Anak itu harus dirawat, dididik, dan diberi kasih sayang yang cukup. Ingat, cukup. Bukan berlebihan.
Supaya itu terjadi, maka pihak orang tua harus siap. Tidak hanya siap secara ekonomi, tetapi juga secara pengetahuan dan mentalitas. Itulah mengapa, saya juga sejalan dengan keluhan si perempuan keempat.
Babak kelima. Cerita di babak ini juga takkalah menarik dengan cerita-cerita perempuan sebelumnya. Ada pernikahan dari seorang perempuan yang sudah paruh baya. Ia menikah dengan mantan pengidap skizofrenia (schizophrenia).